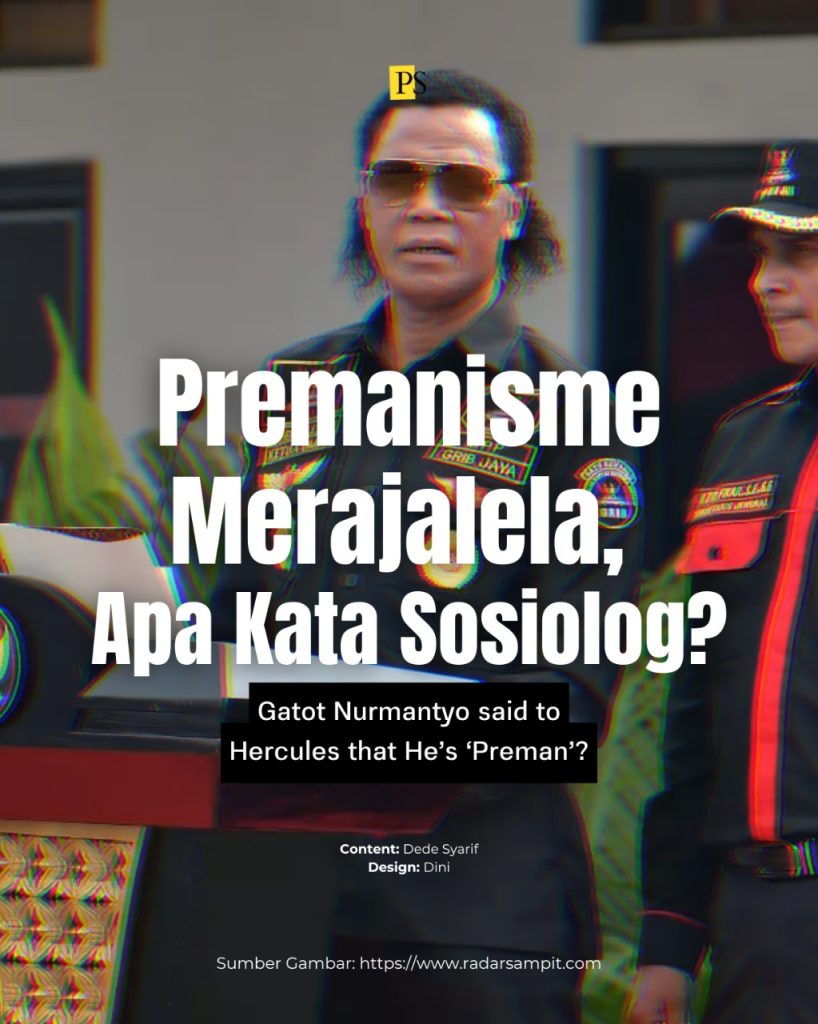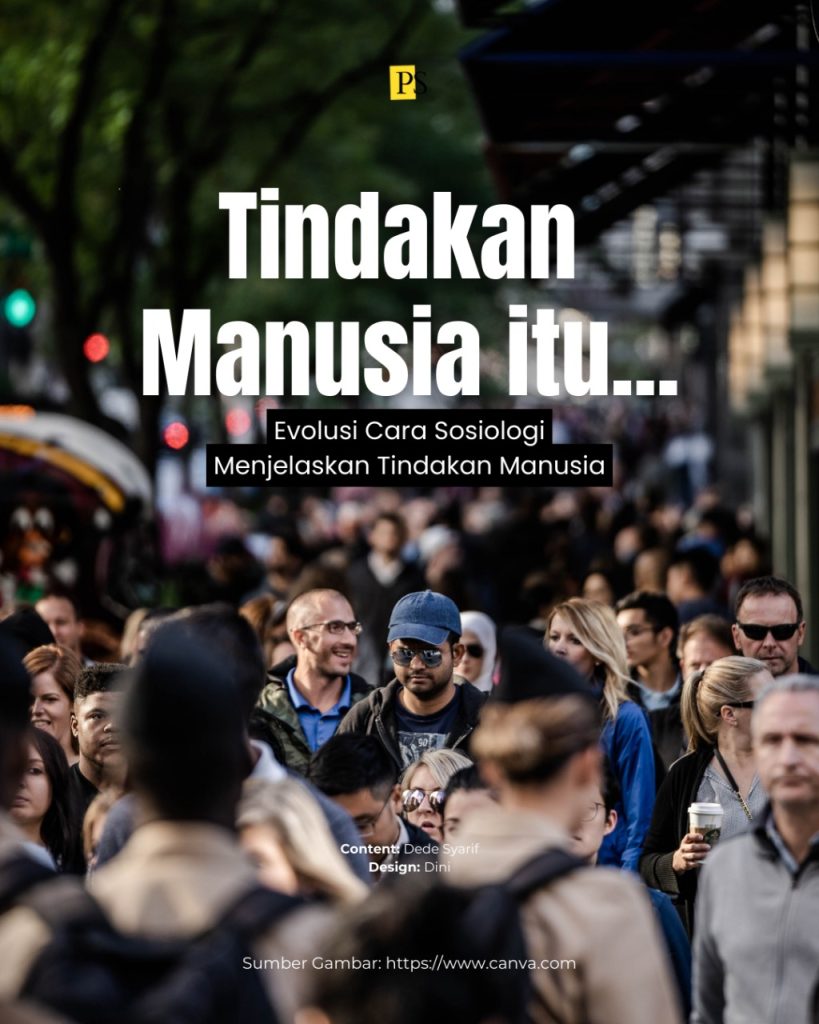
Dalam sejarah pemikiran sosiologi, cara para sosiolog memahami dan menjelaskan tindakan manusia telah mengalami evolusi yang signifikan. Pada tahap awal, pemikiran sosiologi sangat dipengaruhi oleh pendekatan struktural yang melihat bahwa perilaku individu sepenuhnya ditentukan oleh struktur sosial yang mengelilinginya.
Karl Marx adalah salah satu pelopor pendekatan ini. Ia menyatakan bahwa ideologi, politik, agama, dan bahkan budaya manusia sangat ditentukan oleh struktur ekonomi masyarakat atau yang disebutnya sebagai base structure, yaitu cara produksi (mode of production). Dalam masyarakat kapitalis, misalnya, maka cara berpikir dan bertindak pun menjadi kapitalistik. Cara pandang ini dikenal dengan istilah economic determinism—yakni pandangan bahwa ekonomi adalah penentu utama bentuk dan arah kehidupan sosial.
Sejalan dengan Marx, Emile Durkheim juga menganggap bahwa tindakan manusia bukan murni berasal dari individu, melainkan ditentukan oleh apa yang disebutnya sebagai social fact (fakta sosial). Bagi Durkheim, faktor eksternal seperti norma sosial, budaya, dan struktur masyarakat memiliki kekuatan untuk memaksa individu bertindak dengan cara tertentu. Contohnya adalah fenomena bunuh diri (suicide), yang oleh Durkheim tidak dipandang sebagai keputusan pribadi, melainkan sebagai gejala sosial akibat krisis kolektif yang melanda masyarakat.
Pendekatan seperti Marx dan Durkheim ini kemudian dikenal sebagai sosiologi positivistik. Ciri khas pendekatan ini adalah upayanya untuk menjelaskan perilaku manusia dengan hukum-hukum sosial yang obyektif, mirip seperti ilmu-ilmu alam menjelaskan gejala fisik.
Namun, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Max Weber, misalnya, menolak gagasan bahwa perilaku manusia semata-mata ditentukan oleh faktor eksternal. Menurut Weber, karena manusia adalah makhluk yang hidup dan sadar, maka tindakan sosial mereka harus dipahami melalui verstehen, yakni penafsiran subjektif yang dilakukan oleh individu atas realitas sosial yang mereka hadapi. Dalam karyanya yang terkenal The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber menjelaskan bahwa etos kerja dalam masyarakat Protestan bukan hasil langsung dari ajaran agama tersebut, melainkan dari cara individu menafsirkan doktrin keagamaan itu dan mewujudkannya dalam tindakan nyata. Dari sinilah lahir pendekatan baru yang disebut sosiologi interpretatif.
Perkembangan ini membawa sosiologi pada perdebatan antara dua pendekatan besar: struktur versus tindakan aktor, atau positivistik versus interpretatif. Perdebatan ini menciptakan semacam dualisme dalam dunia sosiologi.
Namun, tokoh seperti Anthony Giddens dan Pierre Bourdieu menolak dikotomi tersebut. Mereka menawarkan jalan tengah dengan konsep duality, bukan dualism. Giddens memperkenalkan Teori Strukturasi (structuration theory) yang menyatukan peran struktur dan tindakan aktor dalam membentuk realitas sosial. Sementara itu, Bourdieu mengembangkan Teori Praksis Sosial, yang menjelaskan bagaimana struktur sosial dan kebiasaan individual (habitus) saling membentuk secara dinamis.
Dengan demikian, evolusi pemikiran dalam sosiologi menunjukkan bahwa penjelasan atas tindakan manusia tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Baik struktur maupun interpretasi individu memiliki peran penting dalam membentuk tindakan sosial. Pendekatan yang integratif ini menjadi landasan penting dalam memahami kompleksitas masyarakat kontemporer.