Modernitas: Janji Kemajuan yang Menyimpan Luka Sosial
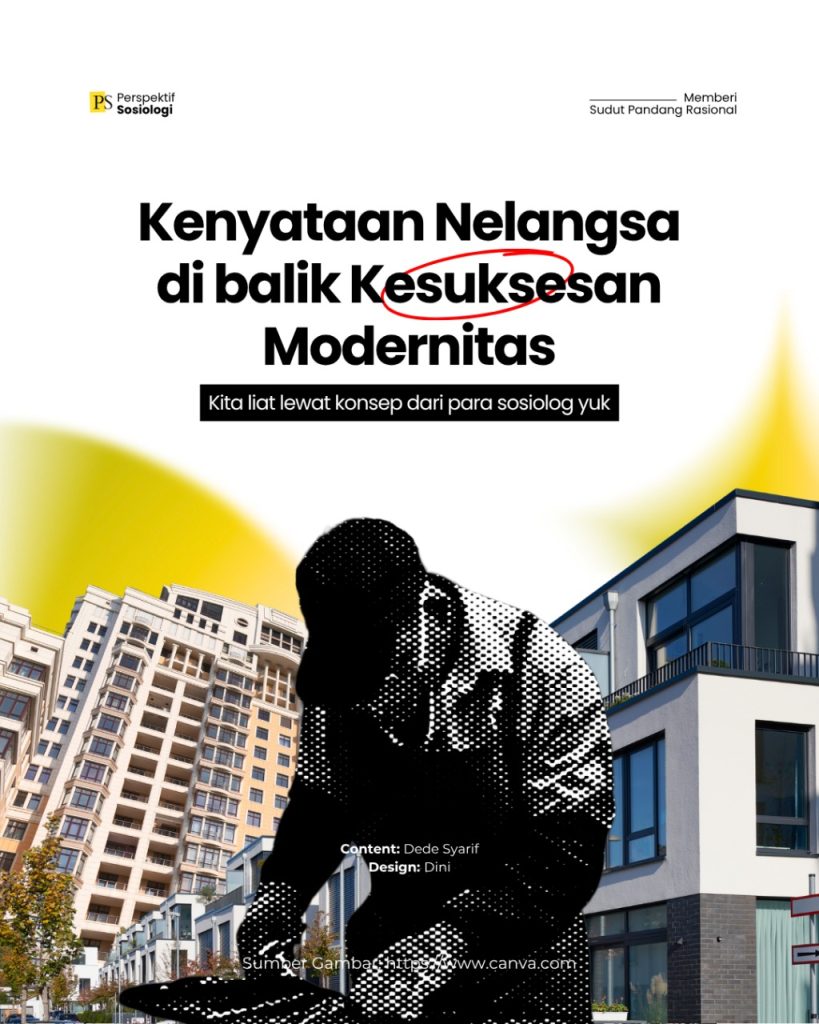
Di era modern, hidup terasa semakin cepat dan canggih. Kita bisa berkomunikasi lintas benua dalam hitungan detik, bekerja dari mana saja, dan menikmati kemudahan teknologi dalam setiap aspek kehidupan. Namun, modernitas juga membawa konsekuensi sosial yang tidak selalu terlihat di permukaan. Di balik janji kemajuan dan kesejahteraan, ada realitas sosial yang nelangsa—seperti yang ditunjukkan para sosiolog dalam konsep-konsep berikut ini.
1. Alienasi: Keterasingan dalam Dunia Modern
Konsep alienasi atau keterasingan pertama kali diperkenalkan oleh Karl Marx sebagai kritik terhadap sistem kapitalisme. Dalam dunia kerja modern, banyak orang merasa tidak lagi memiliki hubungan yang bermakna dengan apa yang mereka kerjakan. Alienasi ini muncul dalam empat bentuk:
Keterasingan dari hasil kerja: Pekerja membuat produk, tapi tidak memiliki kendali atau rasa kepemilikan atasnya. Produk itu milik perusahaan.
Keterasingan dari proses kerja: Pekerjaan jadi rutinitas tanpa makna, hanya demi gaji, bukan aktualisasi diri.
Keterasingan dari orang lain: Persaingan membuat relasi sosial antarindividu menjadi kaku dan individualistis.
Keterasingan dari diri sendiri: Manusia kehilangan arah, merasa asing dengan dirinya sendiri, dan sulit menemukan makna hidup.
Di balik semua kemajuan, banyak orang justru merasa hidupnya kosong dan terjebak dalam rutinitas tanpa jiwa.
2. Anomie: Kehilangan Arah di Tengah Perubahan
Sosiolog Émile Durkheim memperkenalkan istilah anomie untuk menggambarkan kondisi sosial ketika norma-norma rusak atau menghilang. Dalam situasi ini, individu kehilangan pedoman tentang bagaimana seharusnya hidup dan bertindak.
Beberapa aspek utama dari anomie meliputi:
Ketiadaan norma: Norma sosial tidak lagi memberikan arah yang jelas.
Putusnya ikatan sosial: Individu merasa terisolasi dari komunitasnya.
Hilangnya nilai bersama: Masyarakat kehilangan prinsip-prinsip kolektif tentang benar dan salah.
Disorientasi dan kebingungan: Orang merasa tersesat, tanpa tujuan dan makna.
Fenomena ini sering muncul saat terjadi perubahan sosial yang sangat cepat—seperti krisis ekonomi, pandemi, atau revolusi digital.
3. Patologi Sosial: Ketika Masyarakat Sakit
Dalam dunia medis, patologi berarti penyakit. Dalam sosiologi, patologi sosial digunakan untuk menggambarkan kondisi-kondisi menyimpang atau bermasalah dalam masyarakat, yang menunjukkan bahwa ada “penyakit” sosial yang sedang berkembang.
Perilaku menyimpang seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, atau disintegrasi keluarga, sering kali dianggap sebagai gejala dari kondisi sosial yang lebih dalam—ketimpangan ekonomi, hilangnya nilai bersama, atau keterasingan yang terus menumpuk.
Patologi sosial bukan sekadar kesalahan individu, melainkan cerminan dari sistem sosial yang tidak sehat.
Refleksi: Menyadari Luka di Tengah Kemajuan
Modernitas memang memberi banyak hal baru yang memudahkan hidup. Tapi kalau kita tak peka terhadap dampak sosialnya, kita bisa kehilangan hal-hal paling mendasar sebagai manusia: makna, relasi, dan arah hidup. Memahami konsep seperti alienasi, anomie, dan patologi sosial penting—bukan cuma bagi akademisi, tapi juga bagi siapa saja yang ingin hidup lebih sadar, lebih terhubung, dan lebih manusiawi di tengah dunia yang terus berubah.
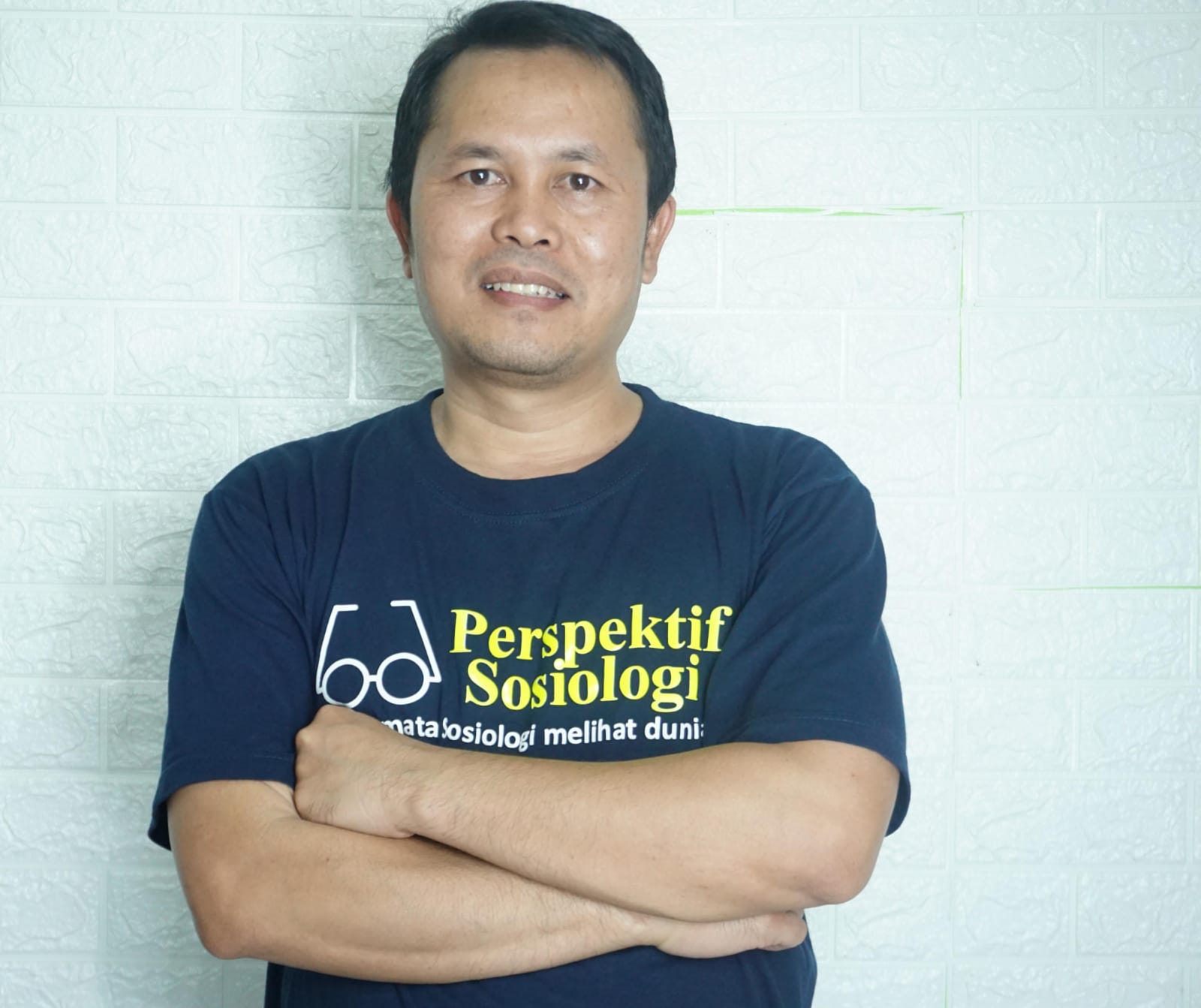
Dr. Dede Syarif
Dr. Dede Syarif adalah seorang akademisi dan sosiolog dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang menempuh pendidikan sosiologi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia dikenal aktif dalam pengembangan ilmu sosiologi melalui berbagai kegiatan akademik, termasuk mengikuti short course di Jerman dan Australia. Selain itu, Dr. Dede merupakan pendiri komunitas kajian Perspektif Sosiologi yang berfokus pada analisis isu-isu sosial kontemporer. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Sosiologi di tingkat S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Bandung
