Konsep
Kekerasan Simbolik: Tak Terlihat, Tapi Nyata Pengaruhnya
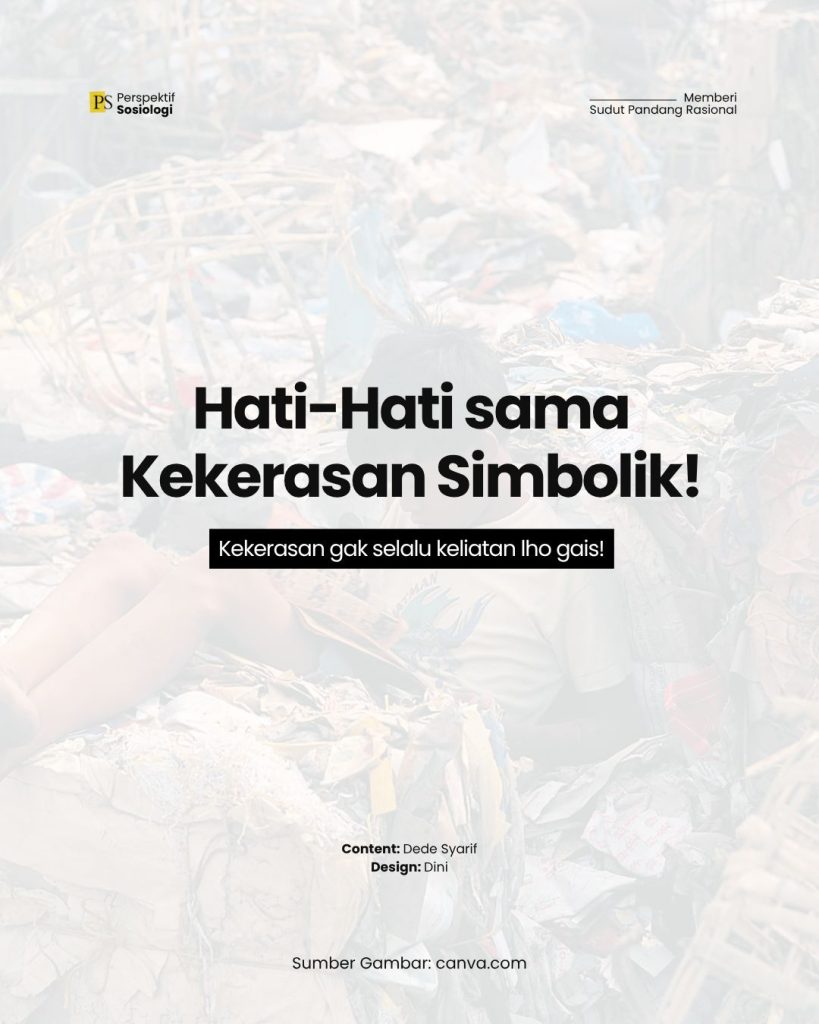
Kekerasan simbolik merupakan konsep yang sering kali tidak tampak oleh mata kita, tetapi pengaruhnya jauh lebih dalam dan jauh lebih luas daripada yang kita sadari. Pierre Bourdieu, sosiolog terkemuka asal Perancis, memperkenalkan konsep ini untuk menggambarkan bentuk-bentuk dominasi yang lebih halus dan terkadang tak disadari yang terjadi melalui norma-norma sosial, nilai-nilai, dan praktik budaya yang ada dalam masyarakat. Dengan memahami konsep kekerasan simbolik, kita bisa lebih jelas melihat bagaimana struktur dan institusi sosial mempertahankan ketimpangan dan status quo yang ada.
Pada dasarnya, kekerasan simbolik beroperasi melalui simbol, gagasan, dan keyakinan, bukan melalui kekuatan fisik atau kekerasan yang terlihat. Ini adalah bentuk kekuasaan yang bersifat budaya, yang membentuk cara kita memandang dunia, preferensi kita, dan perilaku kita. Bourdieu berpendapat bahwa kekerasan simbolik ini sangat efektif, terutama karena ia seringkali diinternalisasi oleh individu yang terlibat. Alih-alih berperang melawan sistem, individu justru menerima dan bahkan memperkuat hierarki dan ketimpangan sosial yang ada tanpa disadari.
Salah satu aspek yang paling menarik dan menantang dari kekerasan simbolik adalah kemampuannya untuk diinternalisasi oleh mereka yang mengalaminya. Proses internalisasi ini berarti bahwa individu mulai melihat tatanan sosial yang ada sebagai sesuatu yang alami dan tak terhindarkan. Mereka mulai menerima posisi mereka dalam struktur sosial dan hierarki, seringkali tanpa bertanya lebih lanjut atau mempertanyakan apakah sistem ini adil atau tidak. Hal ini difasilitasi oleh proses sosialisasi di mana individu, sejak usia dini, mulai mempelajari dan menyerap nilai-nilai serta norma-norma dominan dari masyarakat mereka. Proses ini terjadi melalui apa yang disebut Bourdieu sebagai habitus, yaitu pola-pola kebiasaan, cara berpikir, dan tindakan yang diinternalisasi sepanjang hidup.
Misalnya, dalam masyarakat yang sangat patriarkal, perempuan sering kali diajarkan untuk menerima peran tradisional mereka tanpa banyak pertanyaan. Mereka belajar untuk menerima bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab mereka, atau bahwa posisi mereka dalam dunia kerja atau politik kurang penting dibandingkan laki-laki. Semua nilai ini disosialisasikan dan diterima sebagai norma yang “alami” dan tak terhindarkan. Ini adalah contoh kekerasan simbolik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mempengaruhi tidak hanya perilaku, tetapi juga cara kita memandang dunia di sekitar kita.
Kekerasan simbolik juga sangat efektif karena tidak ada pemaksaan secara fisik. Tidak ada cambuk atau kekerasan langsung yang diterapkan untuk membuat seseorang mematuhi norma tersebut. Sebaliknya, kekerasan simbolik bekerja dengan cara yang lebih halus, melalui pengaruh budaya yang berulang-ulang hingga membentuk pikiran dan perilaku kita. Hal ini memungkinkan struktur dominasi untuk bertahan, karena kita cenderung melihat dunia melalui lensa yang telah dibentuk oleh nilai-nilai dan norma yang kita internalisasi sejak kecil.
Melalui internalisasi ini, orang yang mengalami kekerasan simbolik tidak lagi melihat ketimpangan sosial sebagai sesuatu yang salah atau bisa diubah. Sebaliknya, mereka mulai mempercayai bahwa sistem sosial yang ada adalah sesuatu yang alami dan tak terhindarkan. Sebagai contoh, ketika anak-anak dibesarkan dalam keluarga dengan struktur kekuasaan yang jelas—di mana ayah dianggap sebagai otoritas utama, sementara ibu dan anak-anak harus patuh—mereka belajar untuk menerima hierarki ini sebagai bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Mereka menjadi bagian dari habitus tersebut, yang pada gilirannya mengarah pada reproduksi sistem yang sama di generasi berikutnya.
Pentingnya proses sosialisasi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Melalui sosialisasi, kita diprogram untuk menerima nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat kita, bahkan ketika nilai-nilai tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesetaraan. Tanpa disadari, kita menjadi bagian dari sistem yang menjaga ketimpangan tersebut. Namun, jika kita mulai mengkritisi norma-norma tersebut dan menyadari bagaimana mereka bekerja, kita bisa mulai membebaskan diri dari pengaruh kekerasan simbolik dan berusaha untuk menciptakan perubahan yang lebih adil dalam masyarakat.
Sebagai kesimpulan, kekerasan simbolik adalah kekuasaan yang tak terlihat tetapi sangat nyata. Dengan mempelajari dan memahami konsep ini, kita bisa lebih jernih melihat bagaimana ketimpangan sosial bertahan dalam kehidupan kita. Pierre Bourdieu mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana habitus kita, yang terbentuk dari sosialisasi sosial, membentuk cara kita memandang diri sendiri dan dunia sekitar, serta bagaimana hal itu memperkuat struktur sosial yang ada. Ini adalah tantangan besar bagi kita untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan setara di masa depan.
Referensi:
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Dr. Dede Syarif
Dr. Dede Syarif adalah akademisi dan sosiolog UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lulusan Sosiologi UGM. Ia aktif dalam pengembangan ilmu sosiologi, termasuk melalui short course di Jerman dan Australia. Pendiri Perspektif Sosiologi ini kini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi FISIP UIN Bandung.

Editor: Paelani Setia
Lulusan Sosiologi yang pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa di Unisel, Selangor, Malaysia. Aktif menulis di bidang kajian sosiologi, agama, dan religious studies. Saat ini menjabat sebagai Manajer sekaligus Co-Founder komunitas kajian Perspektif Sosiologi.
