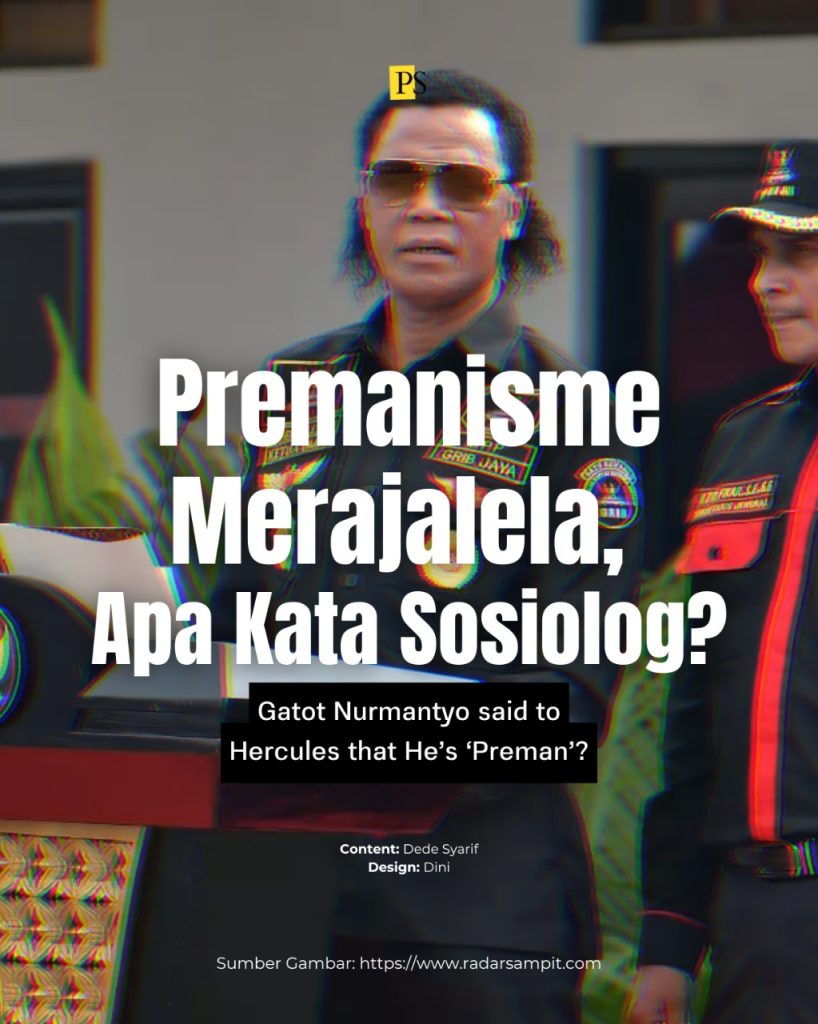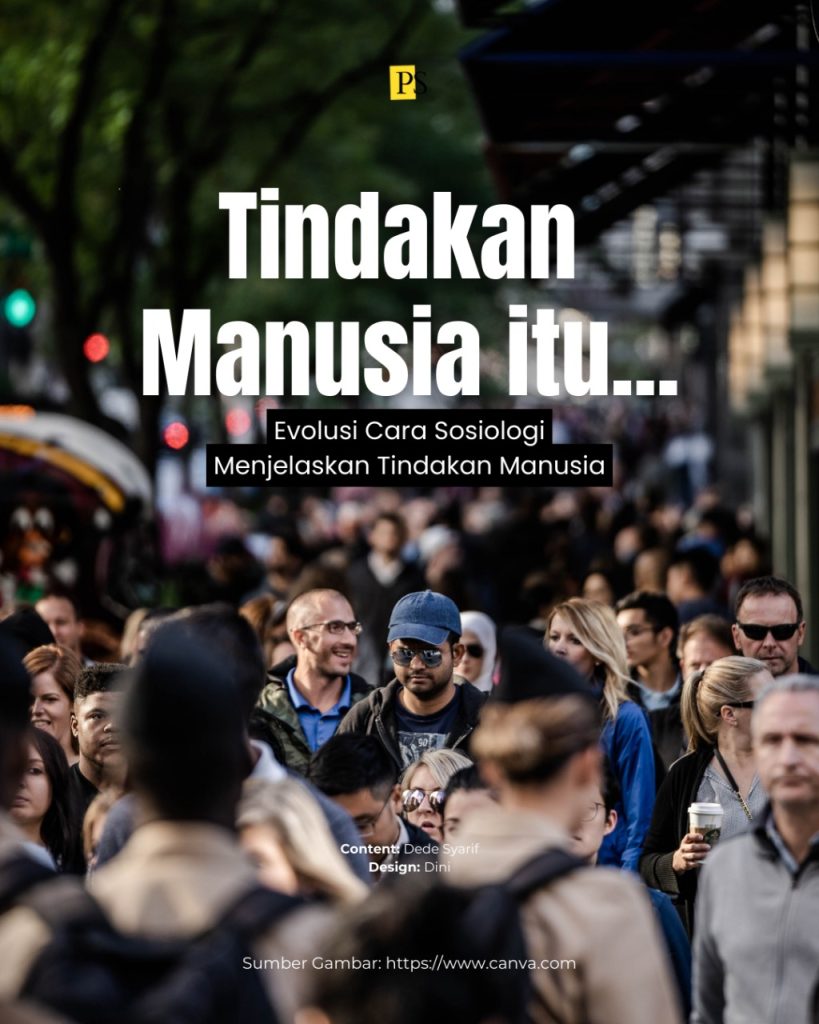Bayangkan sebuah percakapan imajiner antara para pemikir besar yang masing-masing memperdebatkan status keilmuan sosiologi. Thomas Kuhn, sang filsuf ilmu pengetahuan, membuka dialog dengan pertanyaan tajam: “Apakah sosiologi itu sebuah ilmu atau hanya kumpulan common sense belaka? Bukankah sebuah pengetahuan baru bisa disebut ilmu jika ia memiliki paradigma khas yang membedakannya dari ilmu lain?”
Pertanyaan ini segera dijawab oleh Auguste Comte, Bapak Sosiologi, yang menyatakan dengan tegas bahwa sosiologi adalah ilmu. Menurutnya, keilmiahan sosiologi terletak pada kemampuannya meniru metode ilmu alam dalam memahami hukum-hukum yang mengatur masyarakat. Emile Durkheim menambahkan, bahwa sosiologi memang ilmiah karena mempelajari fakta sosial (social fact), yaitu cara berpikir, merasa, dan bertindak yang berada di luar individu namun memengaruhi individu secara kuat.
Namun, pandangan ini tidak diterima begitu saja. Max Weber mengangkat tangannya, mengingatkan bahwa memperlakukan manusia seperti objek dalam ilmu alam adalah sebuah kekeliruan. Baginya, masyarakat adalah entitas yang hidup, sadar, dan penuh makna. Oleh karena itu, sosiologi tidak cukup hanya mengamati fakta sosial, tetapi harus memahami makna tindakan individu melalui pendekatan verstehen—pemahaman empatik terhadap tindakan sosial.
Mendengar perbedaan pandangan ini, Thomas Kuhn mengernyit. Ia merasa bahwa jika sosiologi tidak memiliki paradigma tunggal dan justru dipenuhi keragaman pendekatan, maka jangan-jangan sosiologi bukanlah ilmu sejati, melainkan kumpulan pemikiran sehari-hari yang belum matang secara paradigmatik.
Namun, George Ritzer segera menanggapi. Ia menegaskan bahwa keunikan sosiologi justru terletak pada keberadaannya sebagai ilmu multiparadigma. Tidak seperti ilmu alam yang lebih monolitik, sosiologi mengakomodasi keragaman pendekatan teoritik dan metodologis, dan dari situlah kekayaannya berasal.
Anthony Giddens turut menambahkan bahwa untuk memahami masyarakat, kita tak bisa hanya melihat individu atau struktur secara terpisah. Keduanya saling terkait dalam proses strukturasi, yaitu bagaimana manusia menciptakan struktur sosial sekaligus dibentuk oleh struktur tersebut. Giddens mengajak untuk menghindari dikotomi dan berpikir dalam hubungan timbal balik antara aktor dan struktur.
Senada dengan Giddens, Pierre Bourdieu menawarkan jalan tengah melalui teori praktik sosial dan konsep habitus. Bagi Bourdieu, masyarakat tidak bisa dipahami secara terpisah sebagai individu atau struktur semata. Habitus menjembatani keduanya—menggambarkan bagaimana struktur sosial tertanam dalam diri individu dan diwujudkan melalui praktik sehari-hari.
Mendengar berbagai pandangan yang saling memperkaya ini, Thomas Kuhn akhirnya mengangguk perlahan. “Baiklah, sekarang aku paham. Sosiologi memang tidak tunduk pada satu paradigma tunggal, tetapi justru karena itulah ia hidup dan berkembang. Ia adalah ilmu yang menantang sekaligus memikat.”
Dengan demikian, perdebatan tentang status keilmuan sosiologi tidak berakhir pada dikotomi ilmu versus common sense, tetapi justru membuka pemahaman baru: bahwa sosiologi adalah ilmu yang khas, kompleks, dan reflektif, yang terus bergulat dengan makna, tindakan, dan struktur dalam kehidupan manusia.