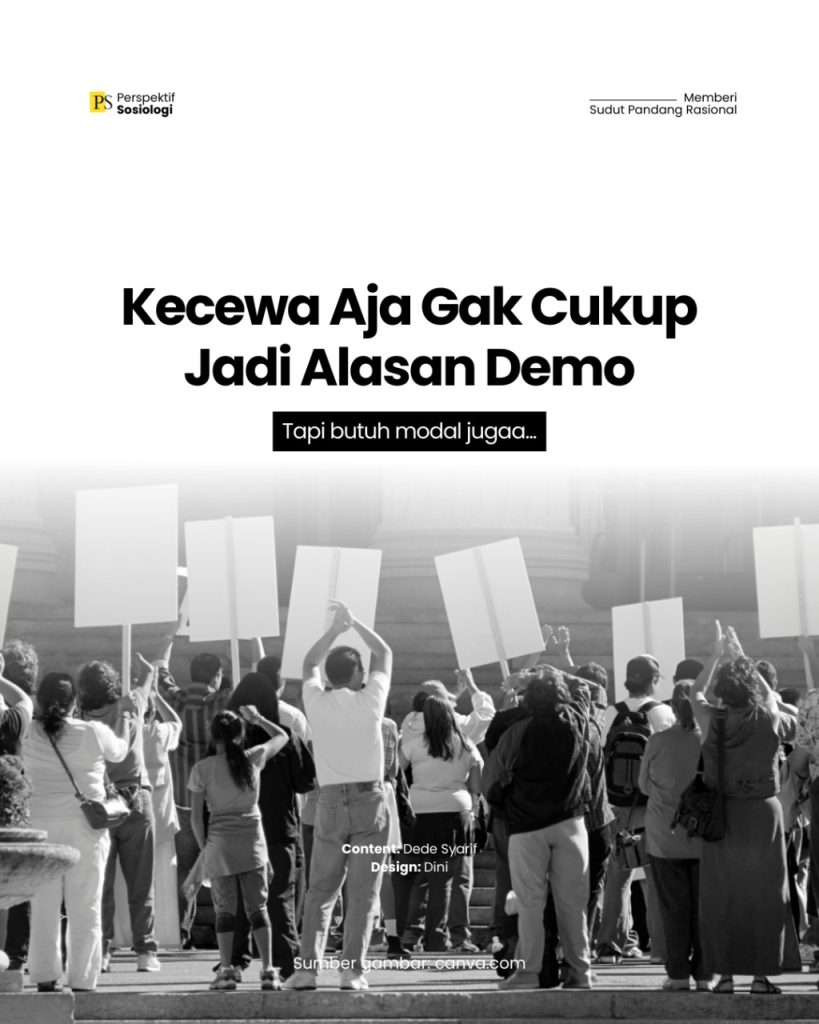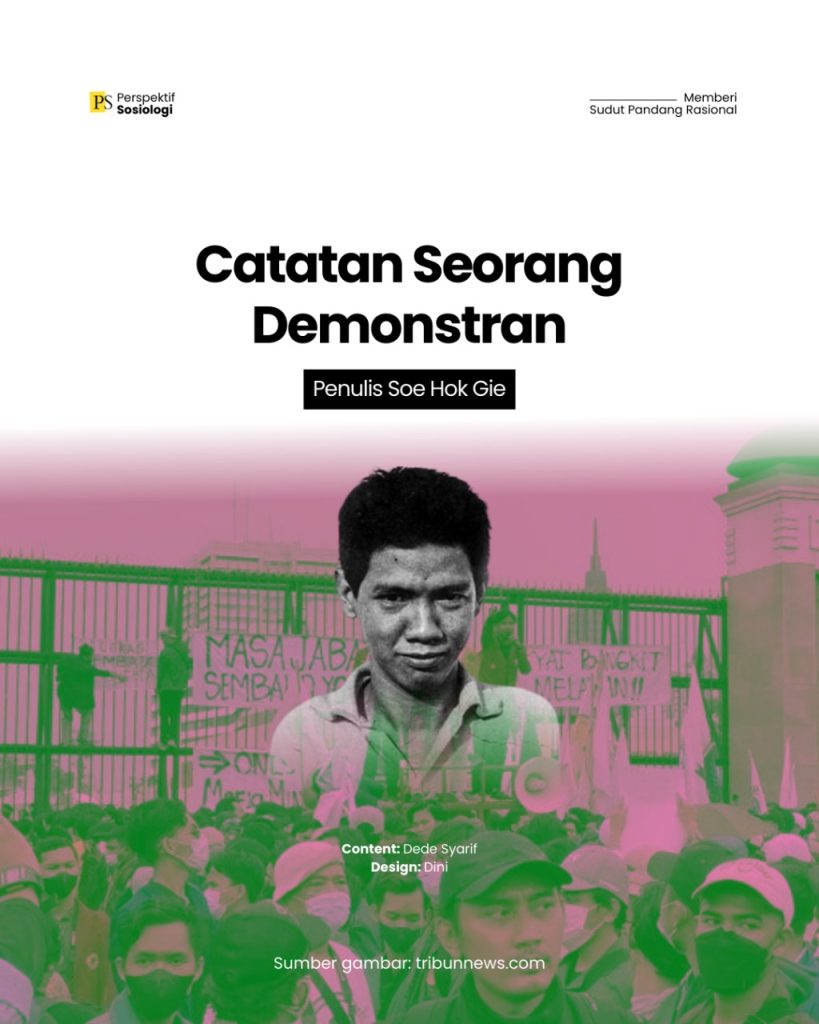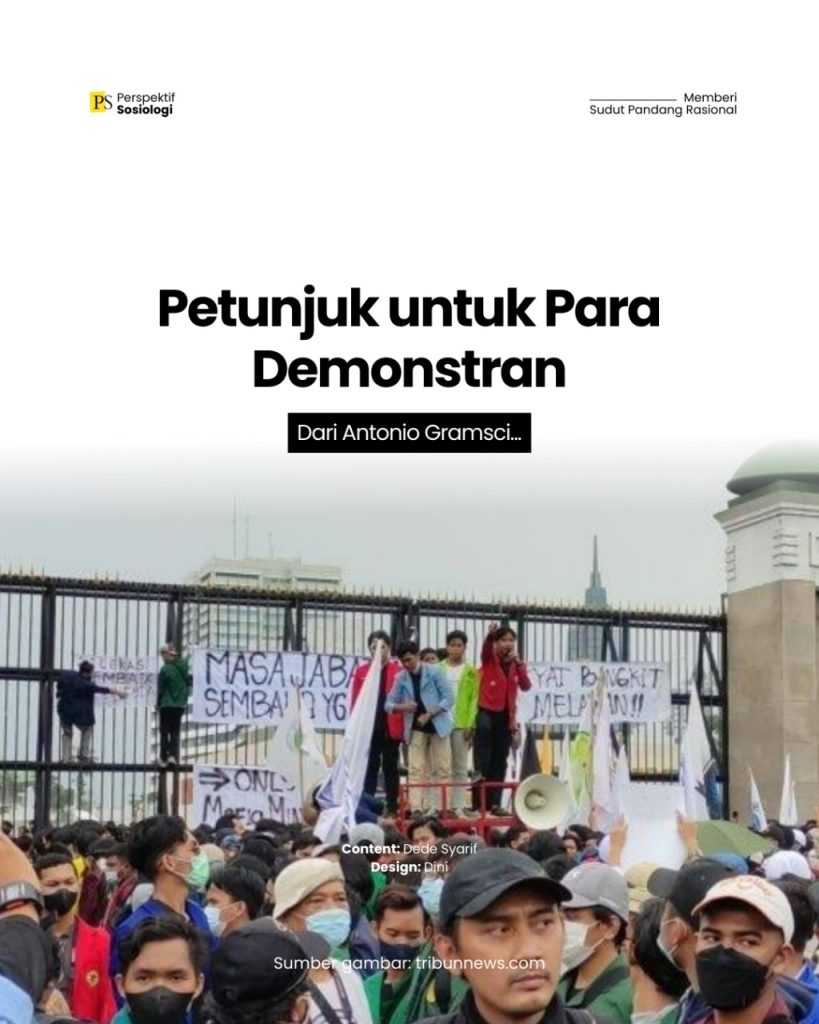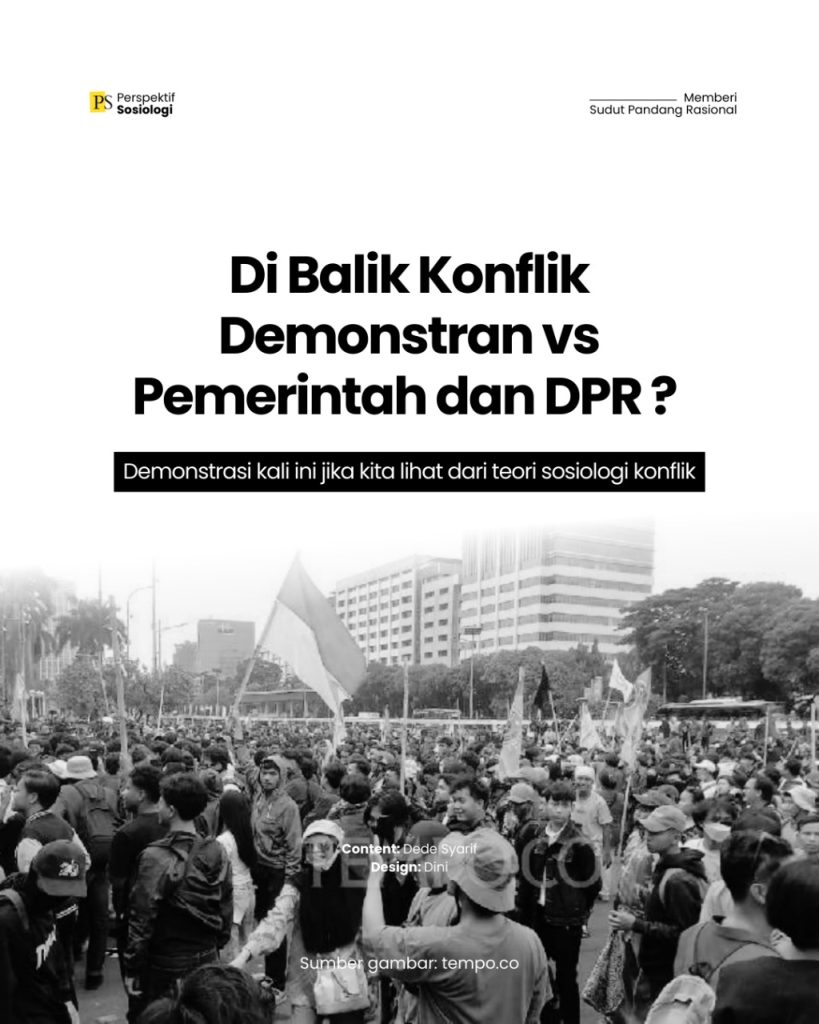Skripsian anti Mood Swing ala Teori Strukturasinya Giddens
Kolom Skripsian anti Mood Swing ala Teori Strukturasinya Giddens Apa sih momen mendebarkan di dunia perkuliahan? salah satu jawabannya adalah skripsi. Ya menulis skripsi itu ibarat drama panjang yang penuh lika-liku, naik turun seperti roller coaster. Saat mengerjakannya, kadang semangat sampai lupa waktu, tapi kang juga nge freez depan laptop gak ngapain. Belum lagi kalau dospemnya susah ditemuin padahal deadline sudah di depan mata. Kalau sudah seperti itu, menulis skripsi bukan lagi sekedar tugas akhir tapi juga ujian mental yang sama berat dengan tuntutan akademiknya sendiri. Kalian ngalamin fase yang sama? Kalau iya, tenang aja, kalian engga sendirian kok. Skripsi itu medan tarik-ulur antara tekanan dari luar dan bagaimana cara kita meresponsnya. Bukan sekedar cari teori yang tepat, ngumpulin data yang tepat, lalu menulis bab perbab lembaran skripsi. Kalau dijalani, skripsi itu jauh lebih kompleks dan mendrama. Ada tekanan dari keluarga, budaya kampus yang penuh aturan, sampai omongan teman yang bikin kit amakin tertekan. Nah, situasi seperti itu dapat kita jelasin pakai perspektif Teori Strukturasi dari Anthony Giddens. Dengan perspektif strukturasi, hidup kita itu berada dalam tarik menarik antara struktur vs. agen. Strukturnya itu seperti standar kampus, deadline, dan aturan. Sedangkan agennya adalah diri kita sendiri dengan pilihan kita untuk meresponsnya bagaimana. Struktur bisa membuat kita tertekan, tetapi memberikan kita arah. Sementara agen, maka kita bisa memilih antara mau melawan, menyesuaikan, atau mencari jalan pintas. Kalau kita terapkan teori ini ke dalam dunia skripsi, mood-swing skripsi itu lahir dari kombinasi keduanya. Struktur itu hadir lewat aturan akademik yang ribet, tenggat waktu yang mepet, sampai ekspektasi orang sekitar. Sementara kita sebagai agen, punya cara sendiri bagaimana menghadapinya. Ada yang disiplin bikin jadwal mengerjakan skripsi, rajin bimbingan, atau nyari dukungan dari teman. Ada juga yang versi rebahan, main game, sampai ada yang pura- pura lupa demi menjaga kewarasan. Semua itu wajar kok manusiawi banget. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus stuck atau mengulang pola ini? Gimana caranya agar kita tidak kalah dengan mood swing pas ngerjain skripsi? Nah, jawabannya bisa kita mulai dari hal sederhana: Pertama, terima prosesnya, jangan berharap kita bisa produktif tiap hari. Kerjain sedikit demi sedikit yang penting konsisten. Kedua, jangan jalan sendirian, skripsi itu lebih ringan kalau ada support system. Entah itu curhat ke Dosen Pembimbing, minta pendapat dari teman, atau minta doa dari keluarga. Ketiga, jaga pola hidup, skripsi itu akan lebih lancar kalau badan dan hati kita sehat. Ibadah ditingkatkan, tidur cukup makan teratur, dan olahraga sewajarnya. Keempat, ubah cara pandang, lihat skripsi itu bukan sebagai beban akhir kuliah, tetapi juga latihan mental supaya kita lebih tahan banting di dunia kerja atau kehidupan setelahnya. Jadi, berdamai dengan mood skripsian itu bukan soal menghilangkan stress atau rasa malas sepenuhnya, tetapi bagaimana kita belajar agar tetap melangkah meski mood tidak stabil. Skripsi itu memang melelahkan, tapi dari hal itu kita belajar disiplin, sabar dan seni bertahan hidup. Yang paling penting perjalanan skripsi itu pasti punya akhir. Jadi kalau sekarang kita lagi stuck, ingat aja siding itu nyata, wisuda itu mungkin, dan rasa lega setelahnya bakalan sepadan dengan proses yang kita lewati. Nina Khoirunnisa Alumni Sosiologi FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung Share artikel ini yuk! Facebook-f Link Twitter Instagram Whatsapp