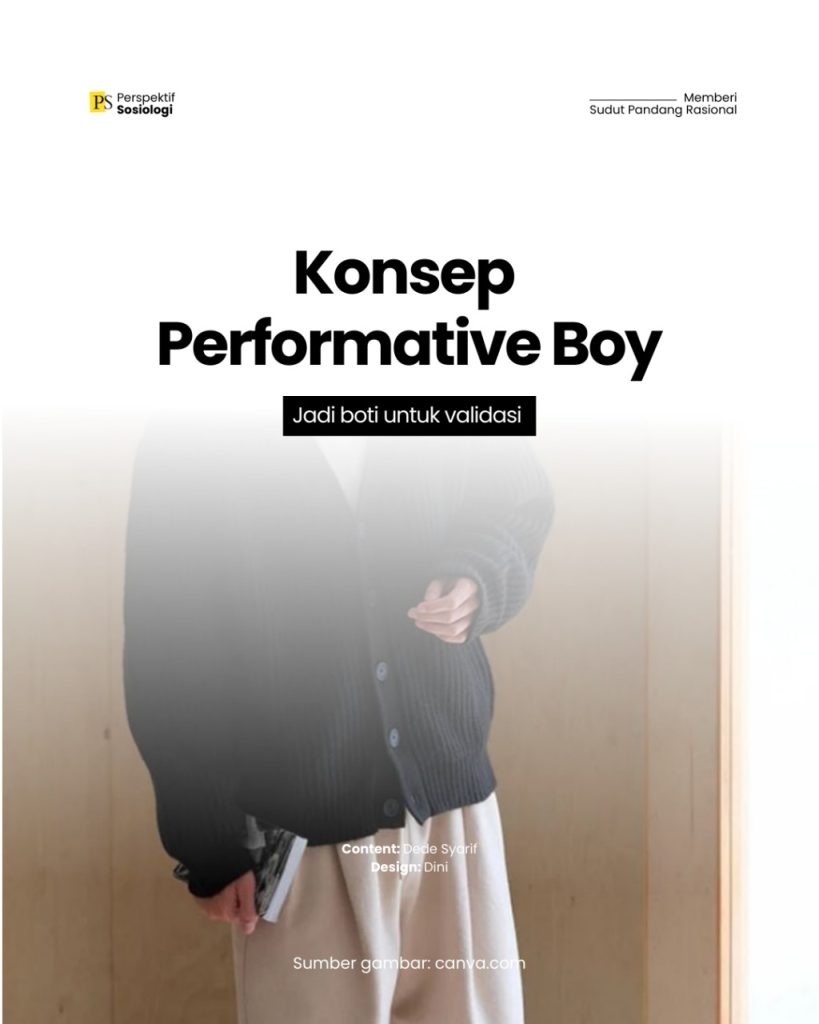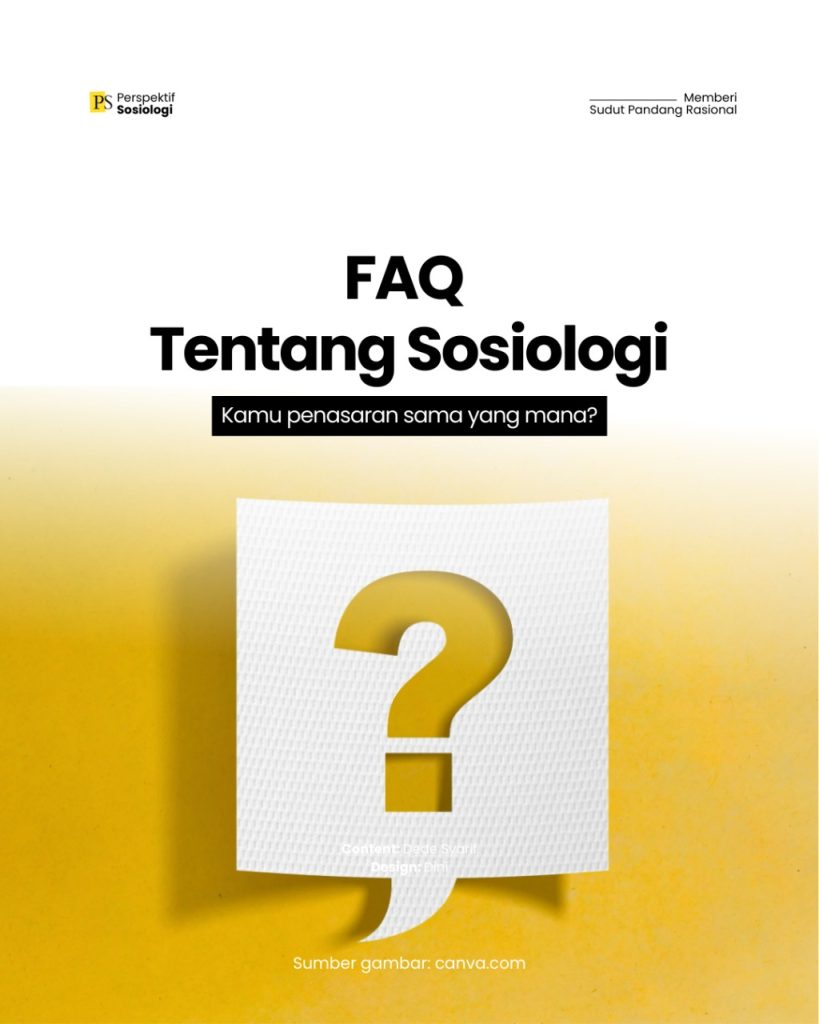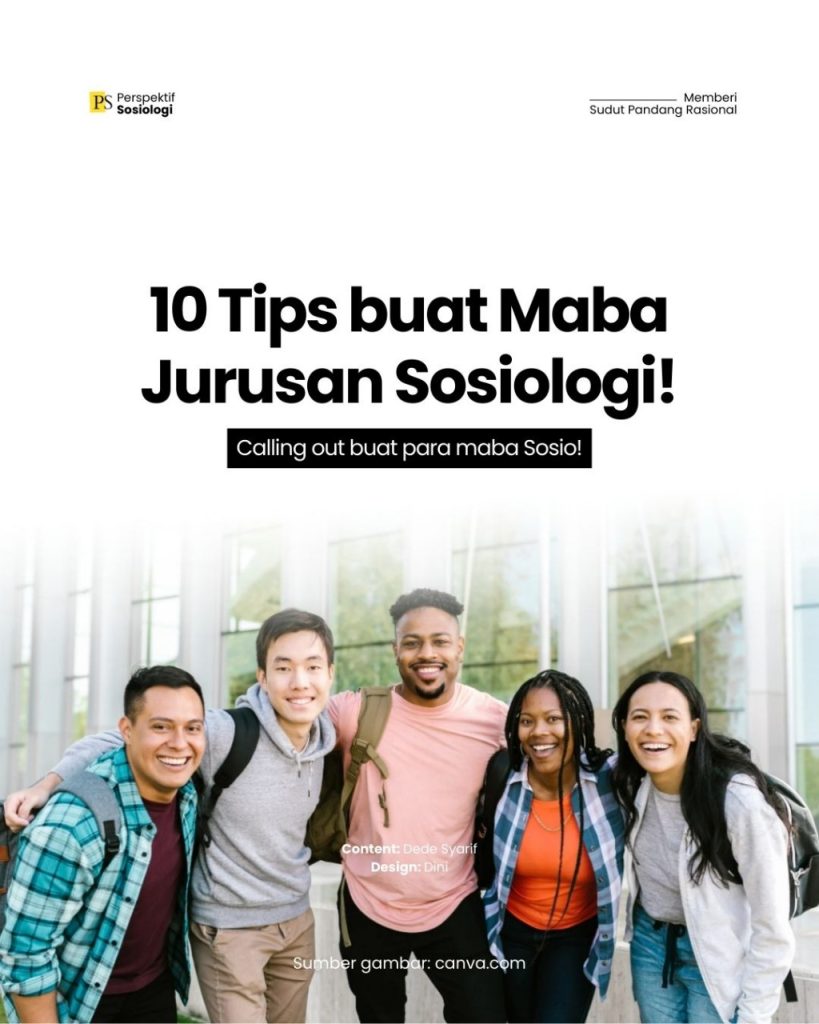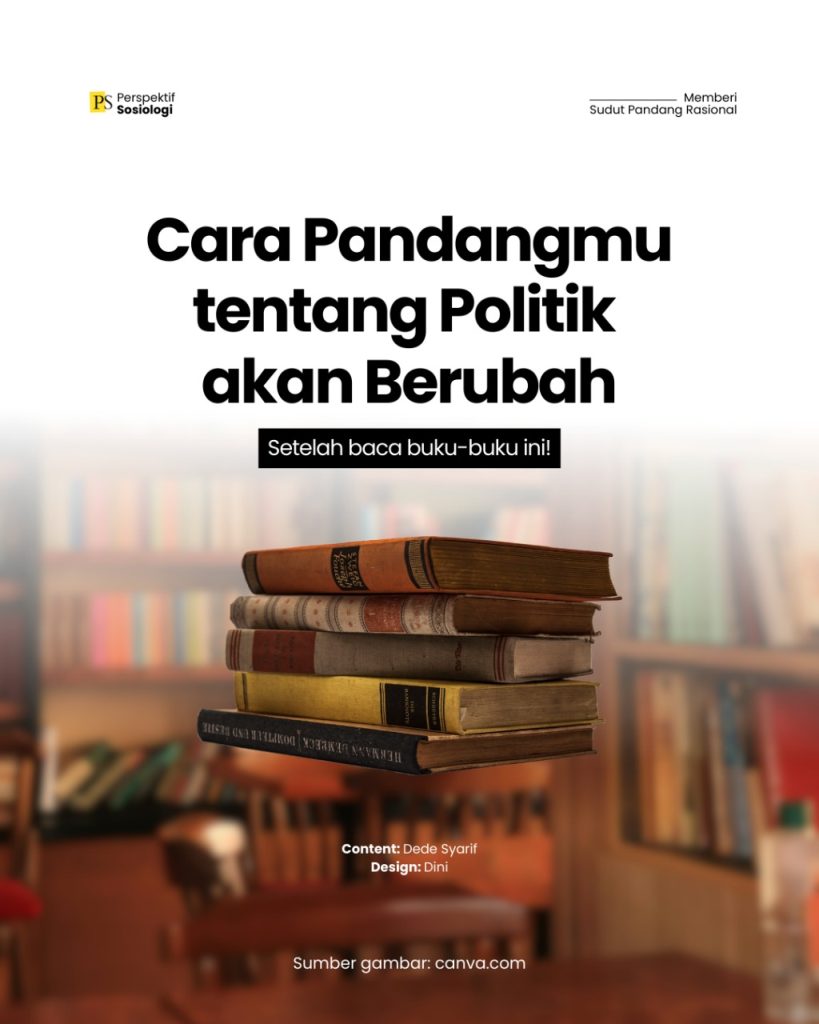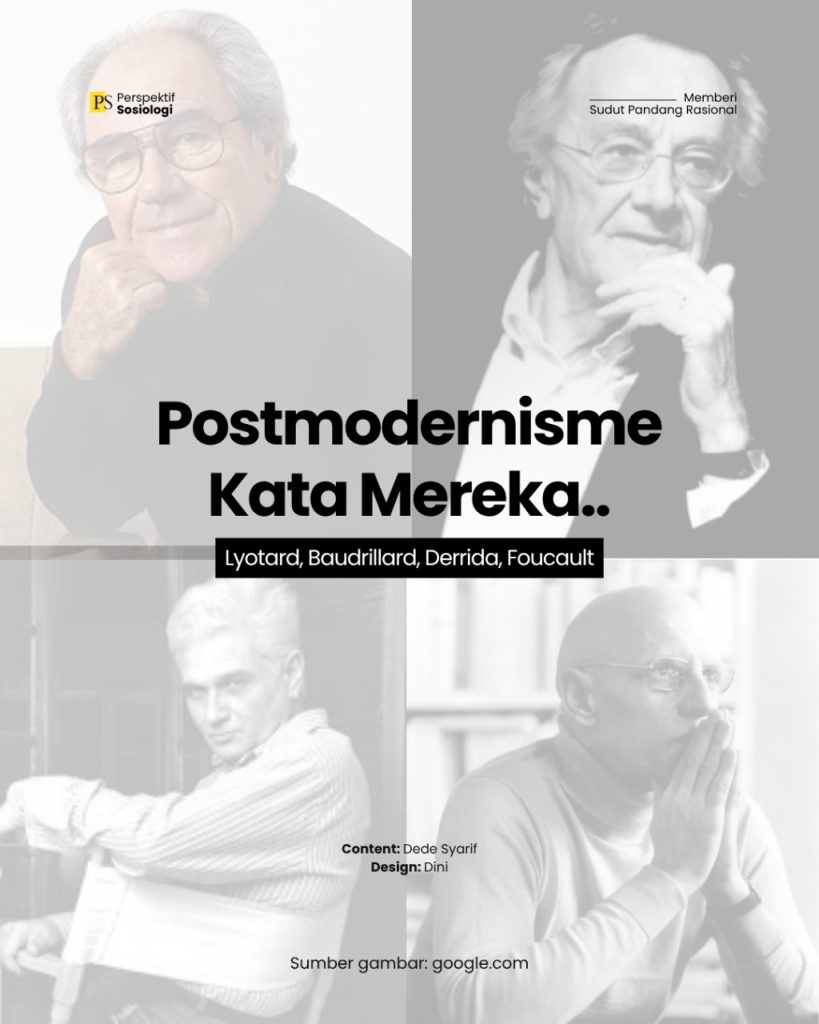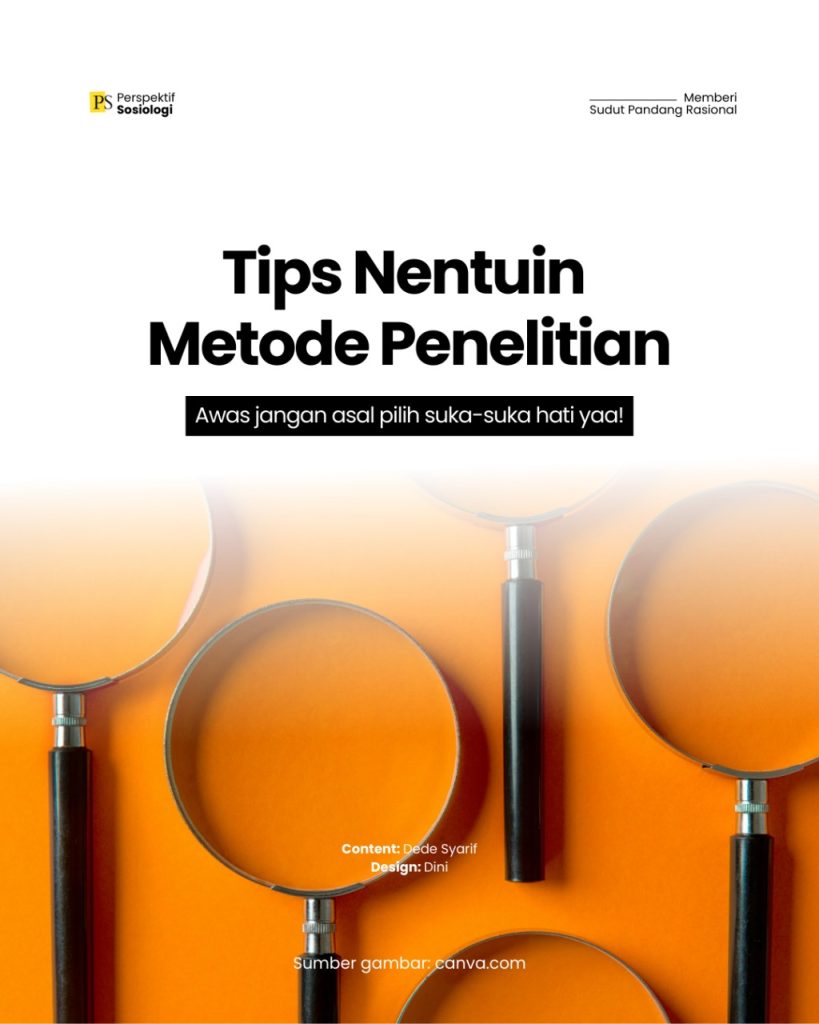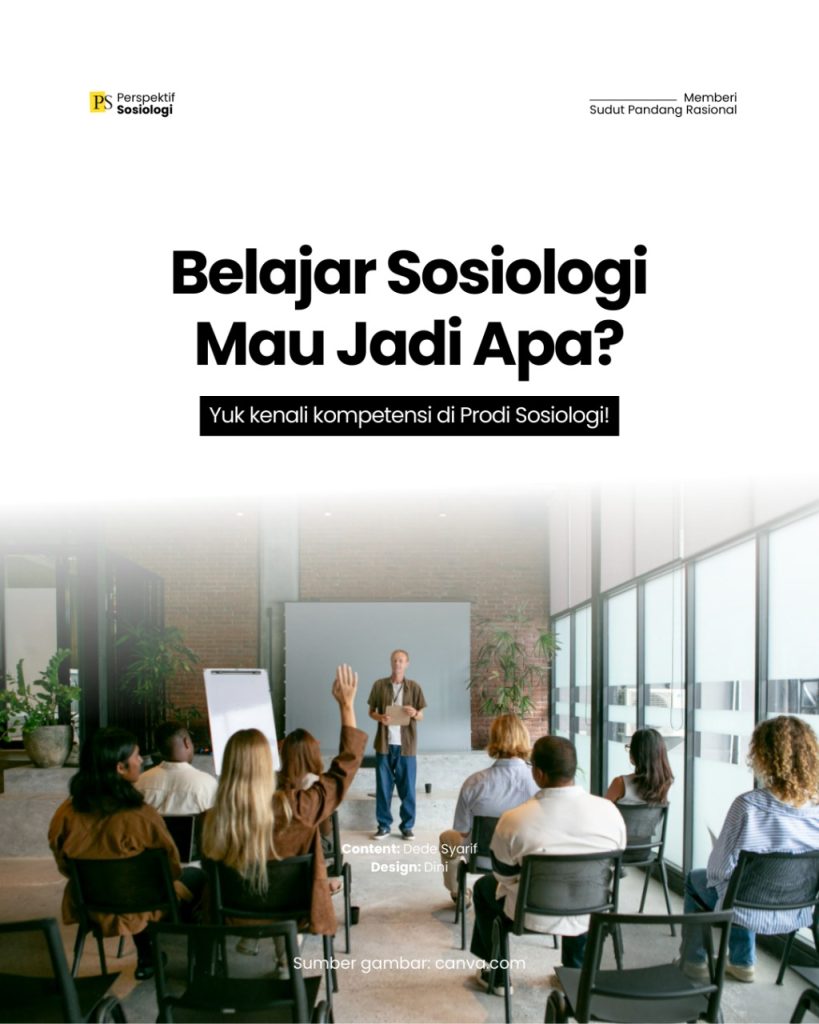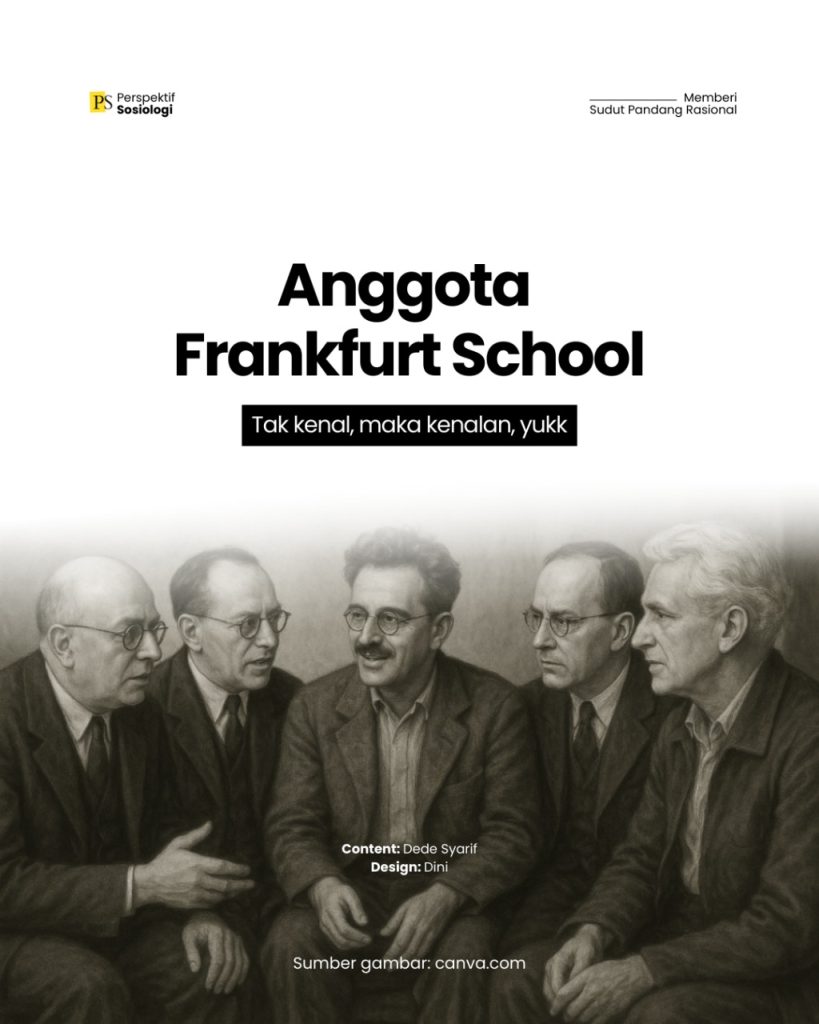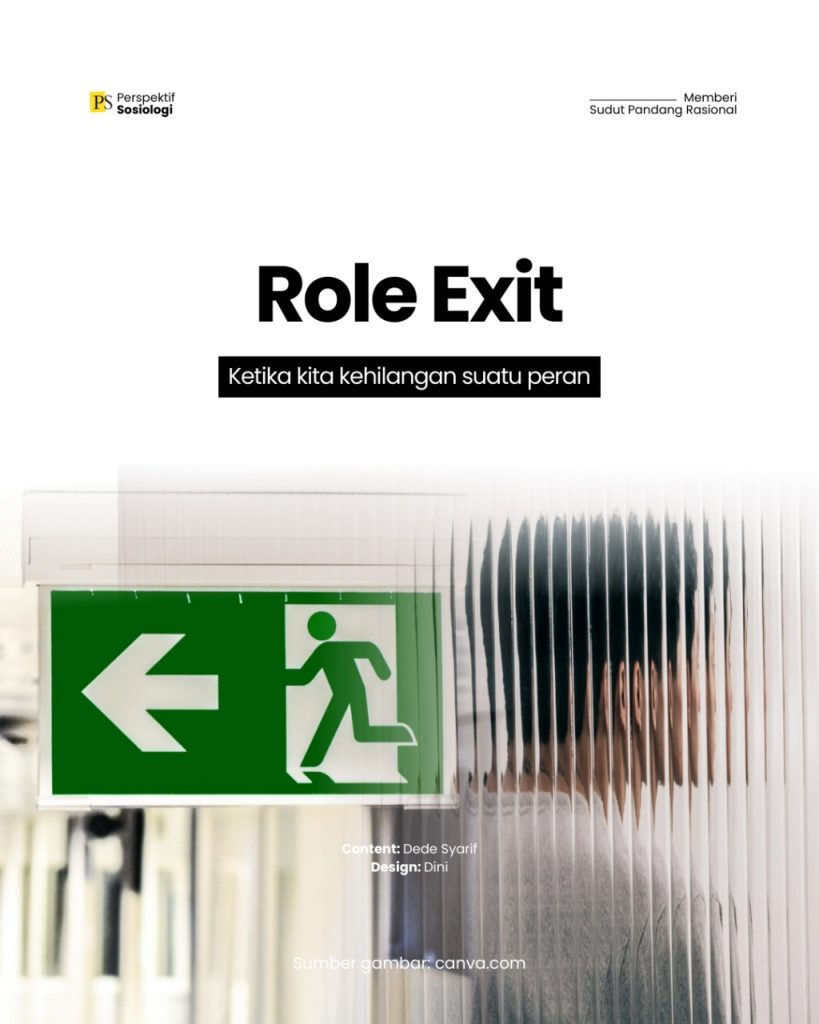Konsep Performative Boy: Jadi “Boti” untuk Validasi
Konsep Konsep Performative Boy: Jadi “Boti” untuk Validasi Fenomena performative boy belakangan ramai dibicarakan, terutama di kalangan Gen Z dan media sosial. Istilah ini merujuk pada laki-laki yang menampilkan sisi feminin atau lembut, bukan semata karena nyaman dengan dirinya sendiri, tetapi lebih sebagai cara untuk menarik perhatian perempuan atau memperoleh validasi sosial. Bukan Tentang Jati Diri Perilaku ini bukanlah ekspresi diri yang tulus. Sebaliknya, ia lebih mirip pencitraan atau strategi sosial untuk terlihat peka, berwawasan, dan relatable di mata perempuan. Artinya, ada kesenjangan antara apa yang ditampilkan dan apa yang sebenarnya diyakini atau dirasakan. Pencitraan dan Validasi Tujuan utama dari perilaku performative boy adalah mendapatkan perhatian, pujian, atau penerimaan dari orang lain. Validasi ini biasanya datang dari perempuan atau lingkaran sosial yang menganggap perilaku lembut sebagai sesuatu yang ideal atau menarik. Beda dengan “Pria Baik” Berbeda dengan “pria baik” (nice guy) yang tampil apa adanya, seorang performative boy cenderung terlihat dibuat-buat. Sikapnya sering kali terkesan dipaksakan, sehingga sulit dibedakan apakah itu betul-betul bagian dari dirinya atau hanya “topeng” sosial. Pro dan Kontra Fenomena ini menuai beragam tanggapan. Ada yang menilai performative boy sekadar gimmick atau strategi pencitraan kosong. Namun, ada pula yang melihatnya sebagai langkah awal menuju kesadaran gender, meskipun masih dangkal, karena setidaknya laki-laki mulai menampilkan sisi yang tidak sepenuhnya maskulin tradisional. Contoh Perilaku Beberapa contoh yang sering dikaitkan dengan tren ini antara lain: membawakan atau memamerkan buku feminis, minum matcha, memakai totebag, mengikuti tren fashion yang lembut, berbicara soal kesehatan mental, hingga memberi kesan sangat suportif terhadap perempuan. Fenomena performative boy menunjukkan bagaimana konstruksi maskulinitas bisa berubah sesuai tuntutan sosial. Di satu sisi, ia bisa dianggap manipulatif, namun di sisi lain, bisa juga dilihat sebagai pintu masuk menuju maskulinitas baru yang lebih cair dan reflektif. Dr. Dede Syarif Dr. Dede Syarif adalah akademisi dan sosiolog UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lulusan Sosiologi UGM. Ia aktif dalam pengembangan ilmu sosiologi, termasuk melalui short course di Jerman dan Australia. Pendiri Perspektif Sosiologi ini kini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi FISIP UIN Bandung. Editor: Paelani Setia Lulusan Sosiologi yang pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa di Unisel, Selangor, Malaysia. Aktif menulis di bidang kajian sosiologi, agama, dan religious studies. Saat ini menjabat sebagai Manajer sekaligus Co-Founder komunitas kajian Perspektif Sosiologi. Address-card Instagram Share artikel ini yuk! Facebook-f Link Twitter Instagram Whatsapp