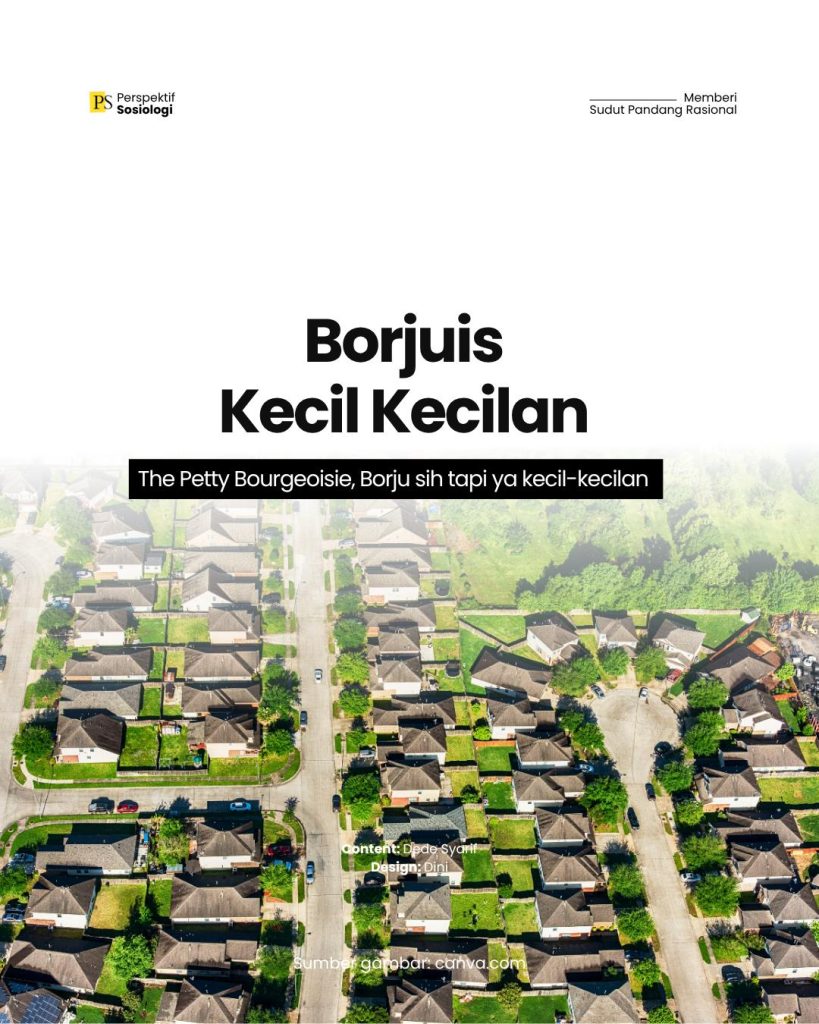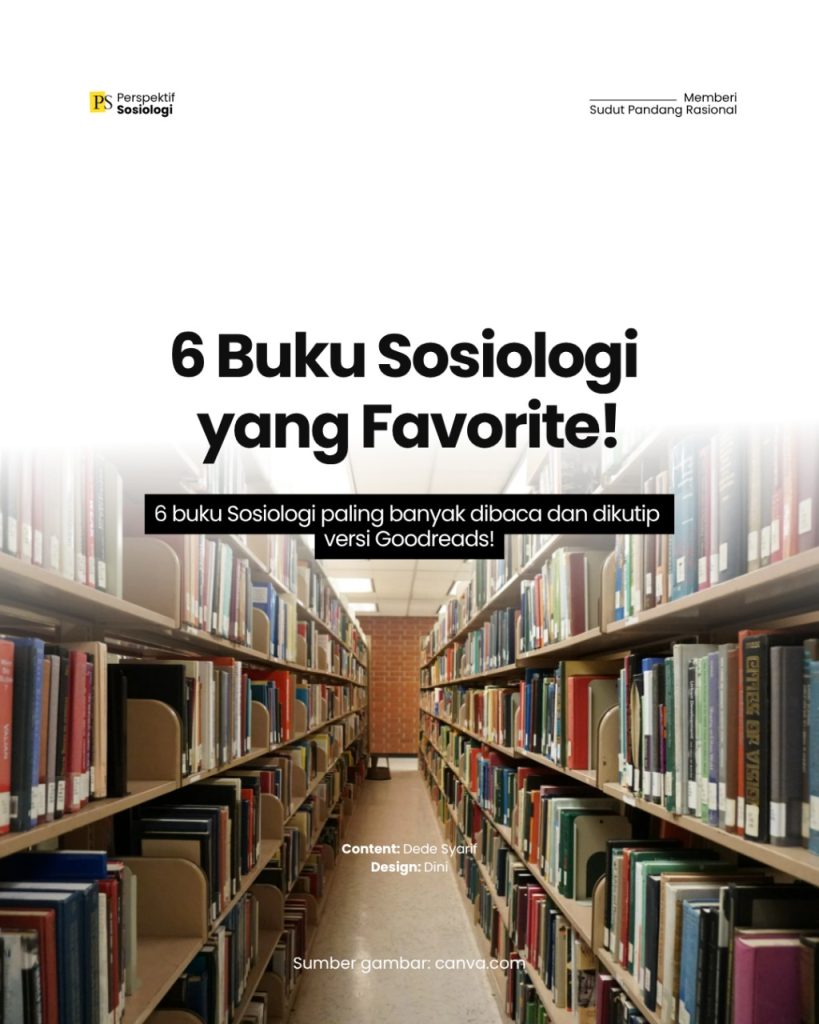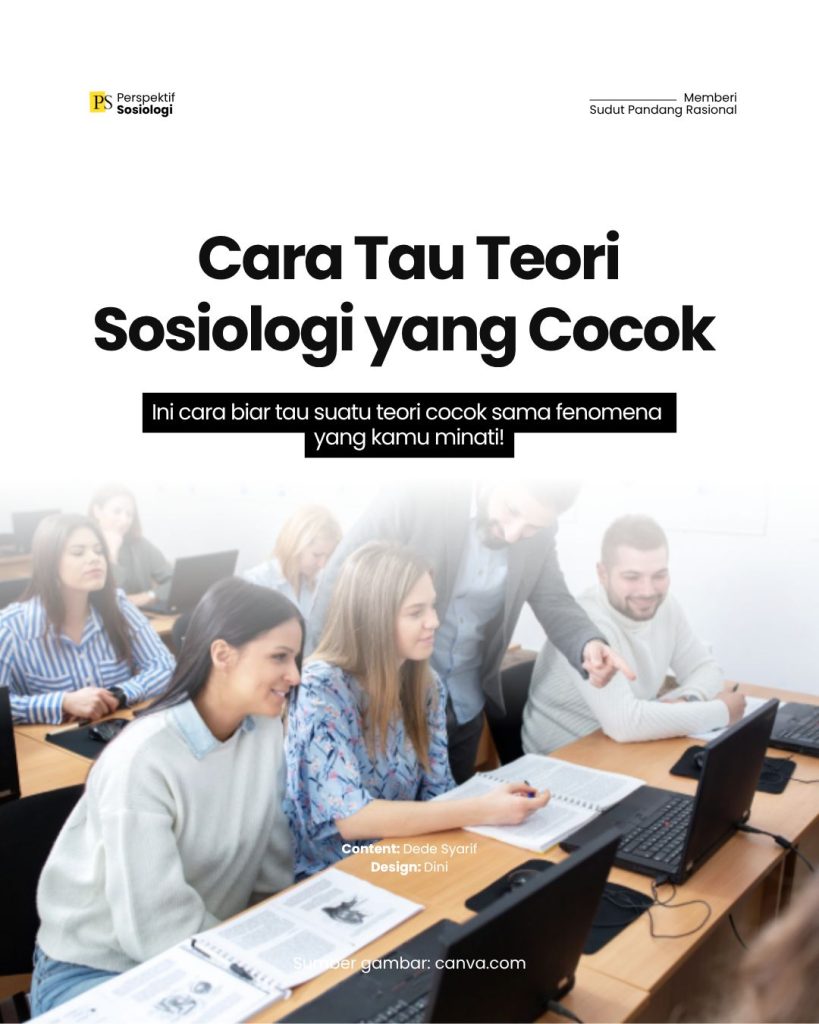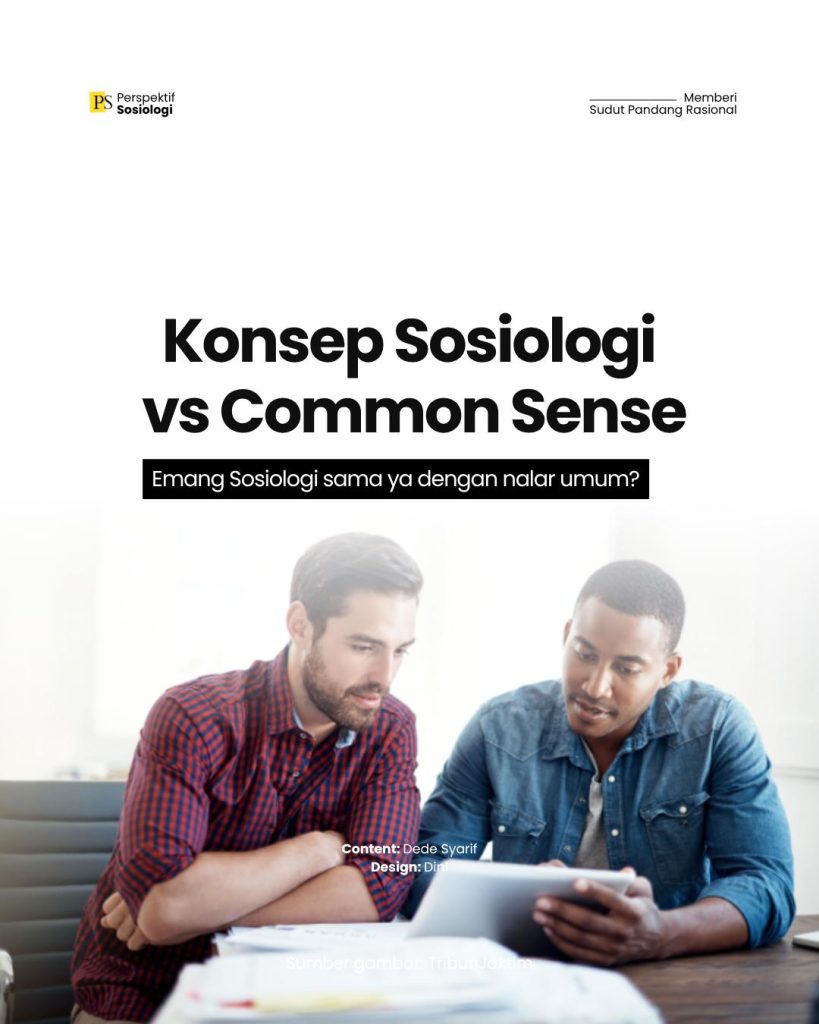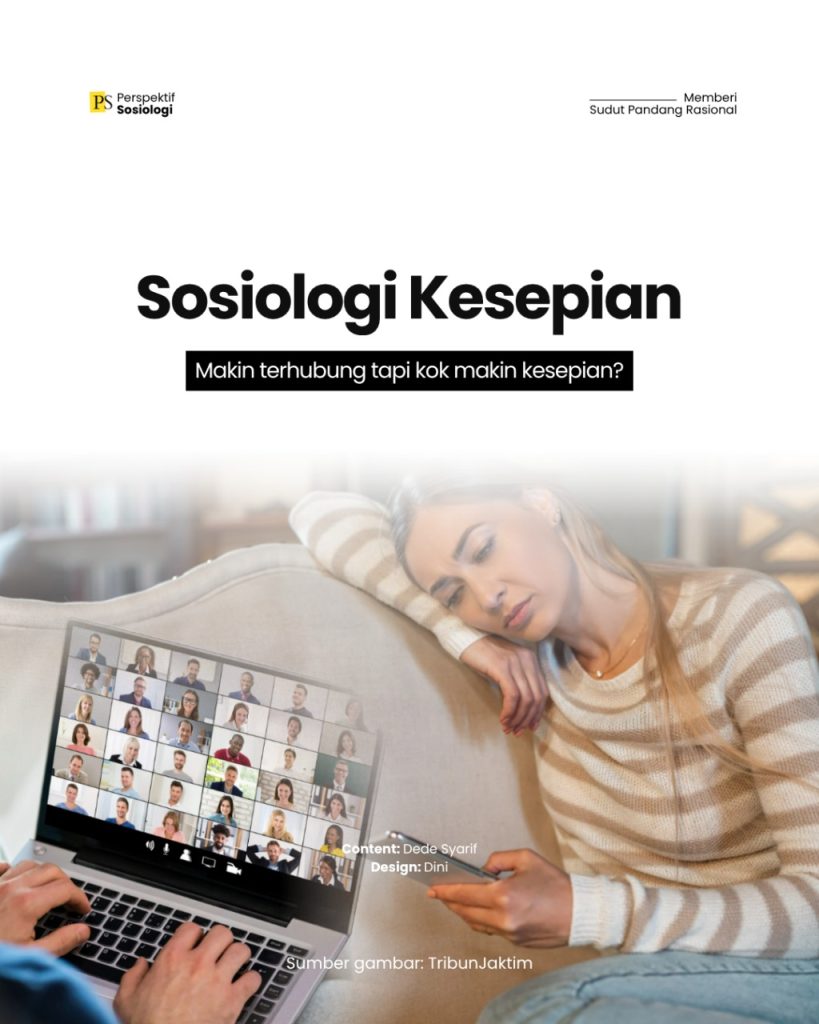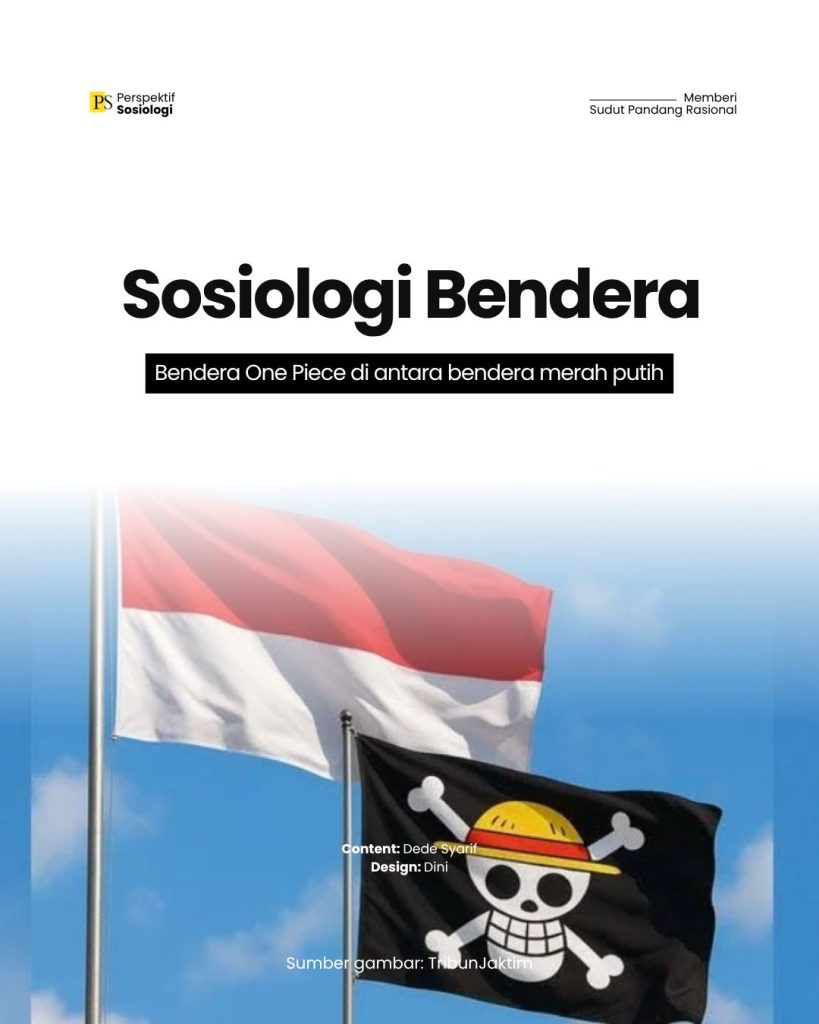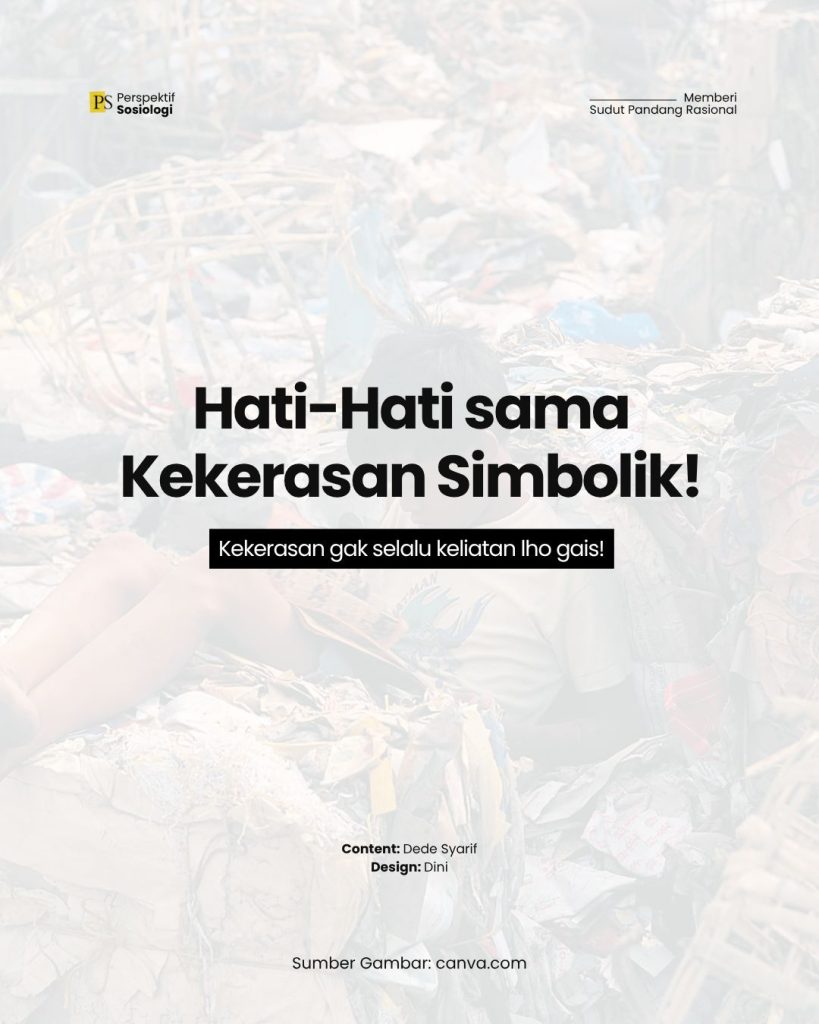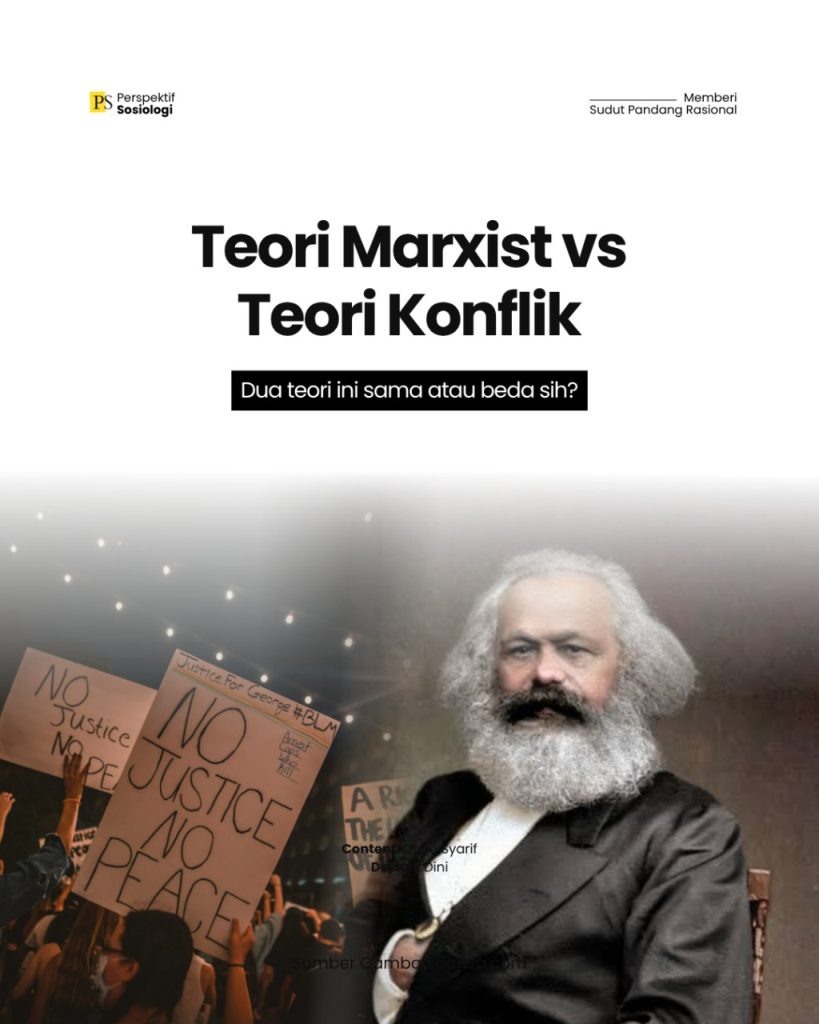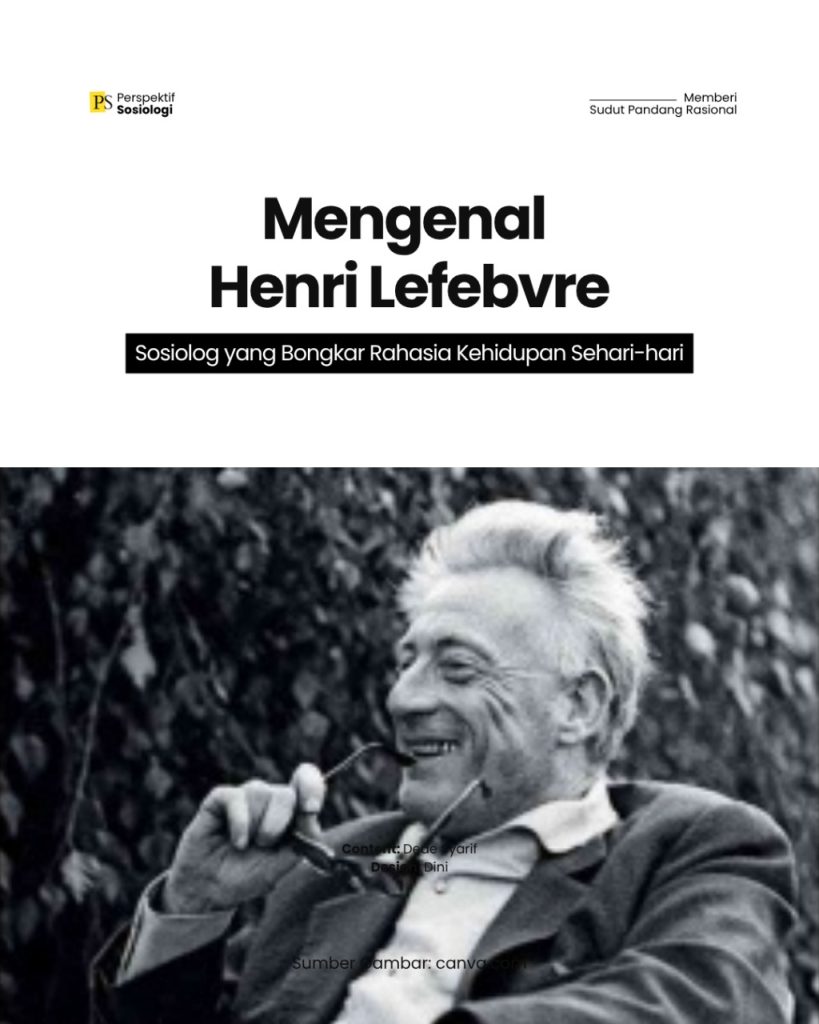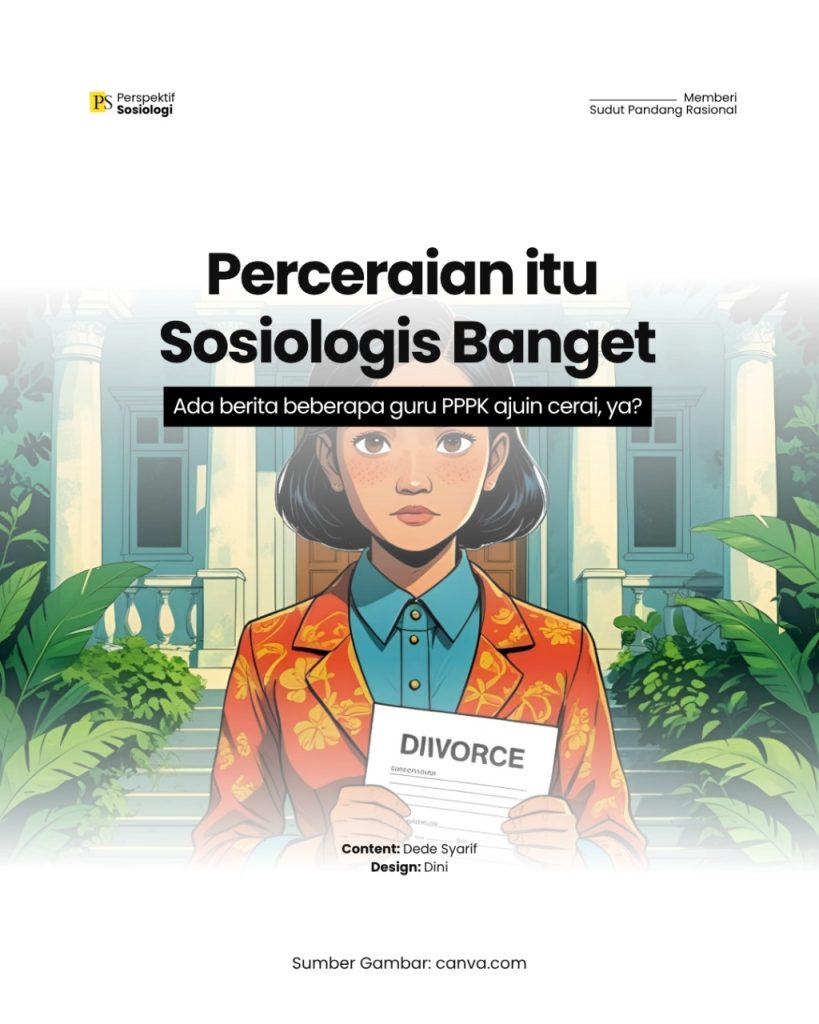Borjuis Kecil: Borjuis Tapi Kecil-kecilan
Konsep Borjuis Kecil: Borjuis Tapi Kecil-kecilan Istilah “borjuis kecil” mengacu pada kelas dalam teori kelas Marx. Mereka disebut sebagai “borjuis kecil” karena sebagian besar pekerjaannya dilakukan secara mandiri, atau dengan mempekerjakan beberapa buruh dalam kegiatan ekonomi mereka. Kelas ini sering dikaitkan dengan pemilik toko kecil, pengrajin independen, atau produsen kecil yang berfungsi sebagai penyangga antara kelas kapitalis (borjuis) dan kelas pekerja (proletariat).Posisi di Antara Dua KelasBorjuis kecil berada dalam posisi unik di tengah masyarakat, terjebak di antara dua kutub, yakni borjuis besar dan proletariat. Posisi ini menyebabkan mereka sering terombang-ambing oleh kepentingan ekonomi yang bertentangan, yang membuat mereka menjadi kelas yang cair secara ideologis dan politis. Di satu sisi, mereka dapat mengambil peran revolusioner dengan mendukung perubahan bersama pekerja, namun di sisi lain, mereka juga bisa bersikap konservatif, terutama jika kepentingan ekonomi mereka terancam. Oleh karena itu, meskipun mereka didefinisikan secara ekonomi, posisi mereka dalam hal ideologi dan politik lebih fleksibel.Perjuangan dan Pergolakan LoyalitasPada tahun 1840-an, borjuis kecil, yang merasa tidak puas dan tertekan oleh kelaparan, berjuang bersama mahasiswa dan proletar perkotaan untuk menuntut reformasi liberal serta pengakuan hak-hak pekerja. Namun, gerakan ini berakhir dengan pergolakan anarkis, yang mengarah pada perubahan dalam aliansi politik mereka. Akhirnya, borjuis kecil beralih ke gerakan kontra-revolusioner yang melibatkan kaum tani konservatif, borjuis, dan sisa-sisa kekuatan feodal. Hal ini mengarah pada berdirinya Republik Prancis Kedua dengan presiden Napoleon III yang kemudian menjadi Kaisar Prancis.Dari Borjuis Kecil ke Kelas MenengahPada akhir abad ke-20, istilah “borjuis kecil” mulai jarang digunakan dan digantikan dengan istilah “kelas menengah” (Poulantzas, 1979). Para ahli membedakan borjuis kecil dari proletariat dan borjuis besar dengan berfokus pada pekerjaan mental yang mereka lakukan, yang berbeda dengan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh kelas pekerja. Perbedaan ini menggambarkan bagaimana peran borjuis kecil bertransformasi dalam masyarakat kapitalis, hingga akhirnya mereka menjadi bagian dari kelas menengah yang sekarang merupakan bagian penting dari ekonomi kapitalis modern.Sumber:Poulantzas, Nicos. Kelas dalam Kapitalisme Kontemporer. NLB, 1975 (asli 1973). Dr. Dede SyarifDr. Dede Syarif adalah akademisi dan sosiolog UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lulusan Sosiologi UGM. Ia aktif dalam pengembangan ilmu sosiologi, termasuk melalui short course di Jerman dan Australia. Pendiri Perspektif Sosiologi ini kini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi FISIP UIN Bandung. Editor: Paelani SetiaLulusan Sosiologi yang pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa di Unisel, Selangor, Malaysia. Aktif menulis di bidang kajian sosiologi, agama, dan religious studies. Saat ini menjabat sebagai Manajer sekaligus Co-Founder komunitas kajian Perspektif Sosiologi. Share artikel ini yuk! Facebook-f Link Twitter Instagram Whatsapp