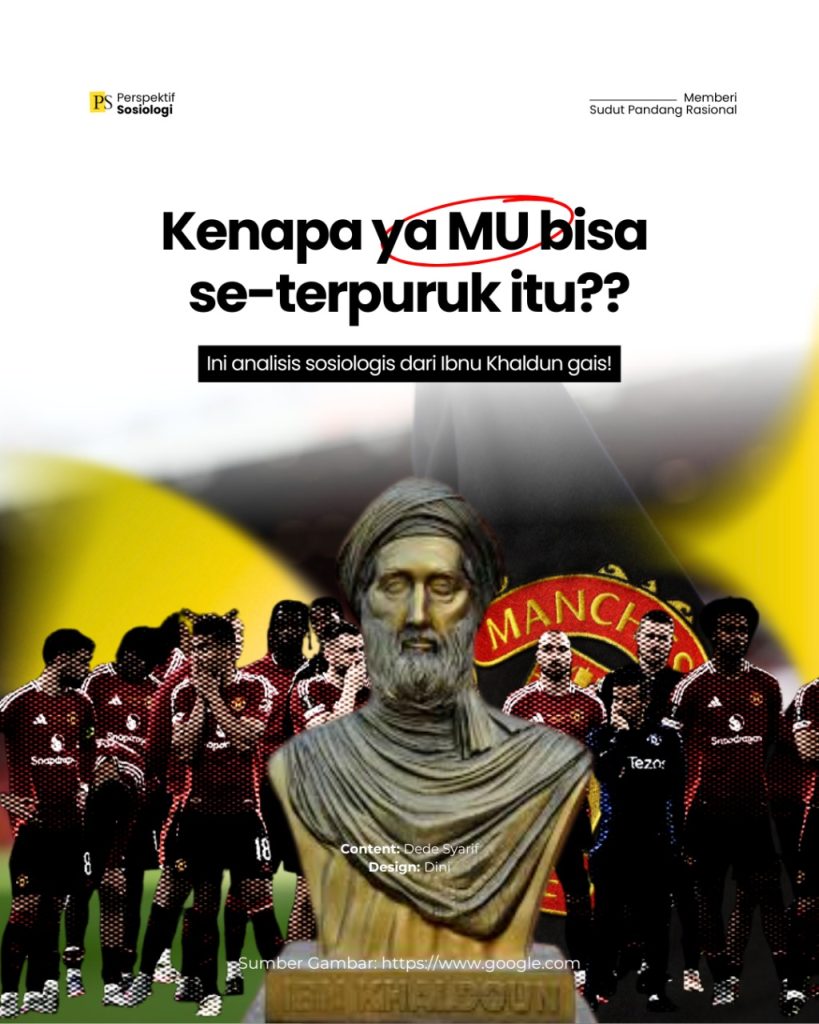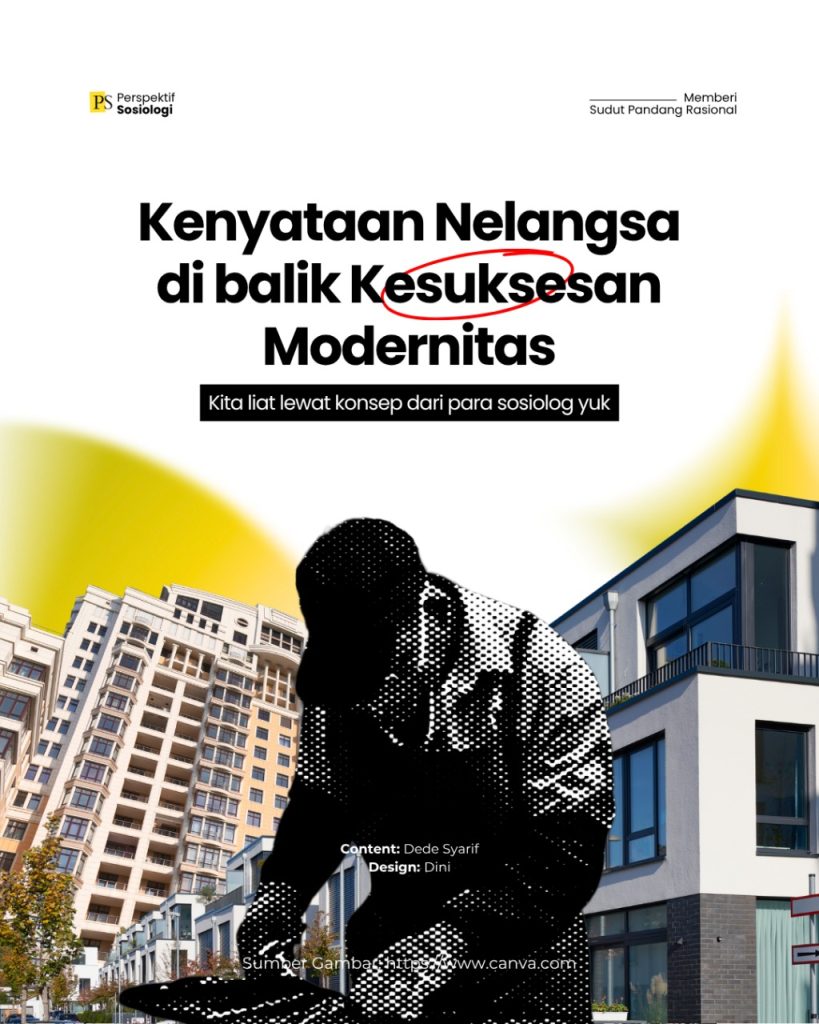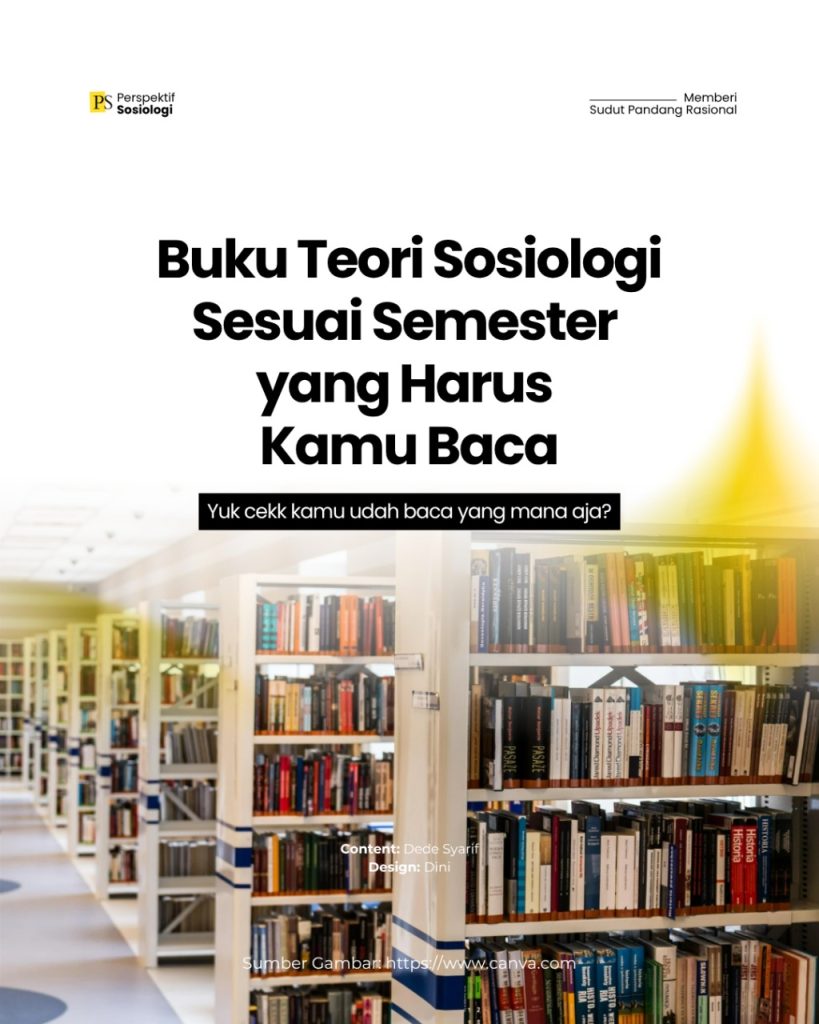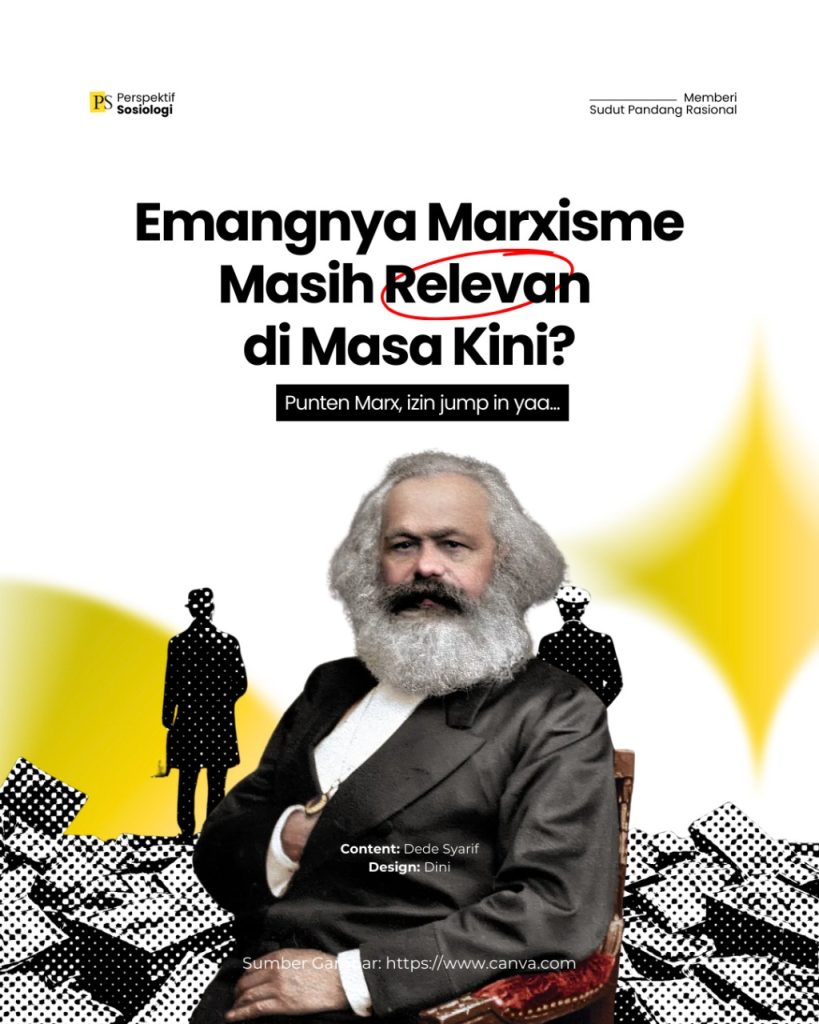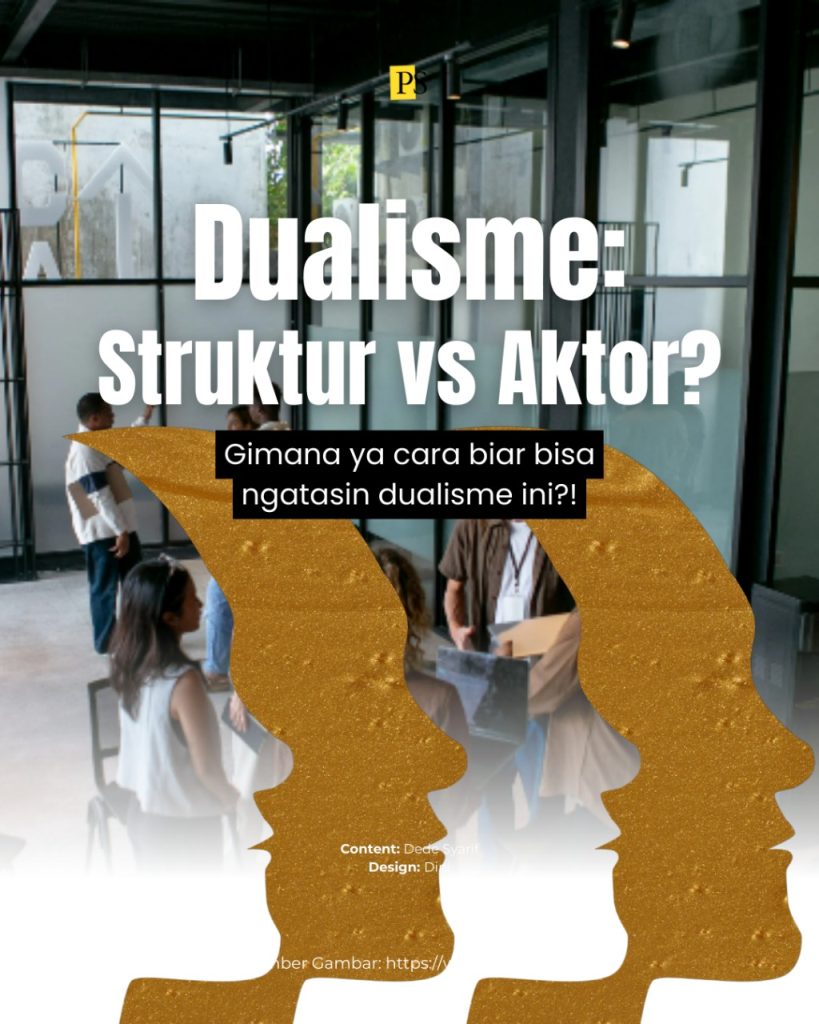Kenapa Manchester United Terpuruk? Analisis Sosiologis dari Ibnu Khaldun
PoV Kenapa Manchester United Terpuruk? Analisis Sosiologis dari Ibnu Khaldun Manchester United (MU) adalah salah satu klub sepak bola paling legendaris di dunia. Sepanjang sejarahnya, MU sudah melalui masa-masa gemilang dan juga periode sulit yang membuat para pendukungnya bertanya-tanya: mengapa klub sebesar ini bisa terpuruk? Untuk menjawabnya, kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang mungkin tak biasa — yaitu teori siklus kekuasaan dari Ibnu Khaldun, seorang sosiolog dan sejarawan besar dari abad ke-14. Ibnu Khaldun dan Teori Siklus Kekuasaan: Relevansi untuk Dunia Sepak Bola Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak sosiologi modern, yang mengemukakan sebuah teori mendalam tentang bagaimana kekuasaan dan peradaban lahir, berkembang, kemudian akhirnya jatuh. Menariknya, walaupun Khaldun hidup jauh sebelum sepak bola ditemukan, konsepnya sangat relevan ketika kita ingin memahami dinamika naik-turunnya sebuah institusi besar seperti klub sepak bola. Ia mengenalkan konsep “asabiyyah”, yang berarti solidaritas kelompok yang kuat dan menjadi modal utama bagi sebuah kekuatan untuk bangkit dan menaklukkan, serta “umran”, yakni kemajuan dan perkembangan peradaban itu sendiri. Teori siklus ini menjelaskan bahwa tidak ada kekuasaan atau peradaban yang akan bertahan selamanya dalam puncak kejayaannya. Semua mengalami proses naik dan turun secara alami. Dalam konteks MU, kita bisa menelusuri bagaimana klub ini melewati siklus tersebut, dari titik awal yang penuh semangat, mencapai masa kejayaan, dan kini sedang menghadapi masa kemunduran. Empat Tahapan Siklus Menurut Ibnu Khaldun Menurut Ibnu Khaldun, siklus kekuasaan terbagi menjadi empat tahapan utama yang saling berkesinambungan. Pertama adalah Bangkitnya Kekuatan Baru, di mana sebuah kelompok atau komunitas dengan solidaritas tinggi (asabiyyah) berhasil menaklukkan lawan dan mendirikan kekuasaan baru. Kedua, ketika kekuatan tersebut semakin mantap, masuk ke tahap Kemakmuran dan Pertumbuhan di mana ekonomi, budaya, dan kekuatan politik berkembang pesat. Namun, seperti halnya roda yang berputar, siklus ini tidak selalu mulus. Tahap ketiga adalah Kemunduran, di mana faktor internal seperti kemewahan berlebihan, rasa puas diri, serta praktik korupsi mulai merusak soliditas dan efektivitas kekuatan itu. Tekanan dari luar pun turut melemahkan posisi mereka. Akhirnya, di tahap keempat yaitu Kejatuhan dan Penggantian, kekuatan yang melemah itu digantikan oleh kelompok lain yang memiliki asabiyyah lebih kuat, dan siklus pun dimulai kembali. Siklus MU: Dari Awal Mula hingga Masa Terpuruk Fase Penaklukan dan Awal Kejayaan Manchester United mulai menancapkan taringnya pada awal abad ke-20, ketika mereka memenangkan gelar Liga Inggris pertama pada musim 1907–08. Perpindahan ke Old Trafford pada 1910 menjadi simbol ambisi besar klub ini. Namun, perjalanan tidak selalu mulus — pada dekade 1920-an dan 1930-an, MU mengalami naik turun antara Divisi Pertama dan Kedua, dipengaruhi oleh krisis keuangan dan pergantian struktur internal. Walau begitu, semangat dan solidaritas kelompok mulai tumbuh sebagai modal dasar membangun kekuatan. Era Keemasan: Kemakmuran dan Pertumbuhan di Bawah Ferguson Era keemasan MU paling kentara setelah Sir Matt Busby mengambil alih pada 1945, tetapi puncak kejayaan benar-benar diraih pada masa Sir Alex Ferguson sejak 1986. Ferguson bukan hanya manajer, melainkan sosok yang membangun kembali fondasi asabiyyah dalam klub—menggabungkan generasi lama seperti Bryan Robson dan Mark Hughes dengan talenta muda “Class of ’92” seperti Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, dan Gary Neville. Di bawah kepemimpinannya, MU mencatat sejarah dengan 13 gelar Liga Premier, menciptakan era dominasi yang tak tertandingi dan membuktikan bagaimana solidaritas kelompok dan budaya klub bisa memacu kemajuan luar biasa. Masa Kemunduran: Saat Soliditas Mulai Renggang Tapi tidak ada yang abadi. Pada 8 Mei 2013, Ferguson pensiun dan meninggalkan kursi manajer yang sulit untuk diisi. Peralihan kepemimpinan ini menandai awal fase kemunduran MU. Setelah bertahun-tahun di bawah kendali Ferguson, klub kehilangan soliditas internalnya. Ganti manajer yang berulang kali terjadi menimbulkan ketidakpastian, mengikis rasa kebersamaan dan tujuan yang selama ini menjadi kekuatan utama klub. Faktor-faktor internal seperti rasa puas diri, kurangnya kesatuan visi, dan tekanan dari persaingan yang semakin ketat mulai menimbulkan keretakan. Bahkan, kekalahan memalukan seperti kalah dari tim ASEAN All Star 1-0 semakin memperjelas bahwa MU sedang mengalami penurunan yang nyata. Refleksi: Apa yang Bisa Dipetik dari Siklus Ini? Melihat keadaan MU melalui teori Ibnu Khaldun, kita bisa menyadari bahwa kejayaan maupun kemunduran bukanlah perkara kebetulan atau sekadar performa pemain di lapangan. Lebih dari itu, semua berakar pada aspek sosial dan budaya internal klub—solidaritas, semangat juang, dan kesatuan tujuan (asabiyyah) yang menjadi pondasi kekuatan. Jika MU ingin kembali bangkit, mereka harus membangun ulang fondasi ini. Mengembalikan budaya kerja sama yang kuat, membentuk identitas yang jelas, dan menumbuhkan semangat juang yang tak tergoyahkan. Dalam siklus peradaban, fase kemunduran adalah peluang untuk peremajaan dan kelahiran kekuatan baru yang segar. Kesimpulan: Siklus Sejarah MU Masih Berlanjut Manchester United sedang berada pada titik krusial dalam siklus sejarahnya. Meski saat ini terpuruk, bukan berarti ini adalah akhir dari cerita mereka. Sejarah dan teori Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa asabiyyah baru dapat muncul, dan dengan itu datang kesempatan untuk bangkit dan meraih kejayaan kembali. Bagi para pendukung MU, ini saatnya bersabar dan terus memberi dukungan—karena dalam siklus kekuasaan, kebangkitan selalu mengikuti kejatuhan. Masa depan MU ada di tangan mereka yang mampu membangun solidaritas dan semangat juang baru. Dr. Dede Syarif Dr. Dede Syarif adalah seorang akademisi dan sosiolog dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang menempuh pendidikan sosiologi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia dikenal aktif dalam pengembangan ilmu sosiologi melalui berbagai kegiatan akademik, termasuk mengikuti short course di Jerman dan Australia. Selain itu, Dr. Dede merupakan pendiri komunitas kajian Perspektif Sosiologi yang berfokus pada analisis isu-isu sosial kontemporer. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Sosiologi di tingkat S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Bandung Address-card Instagram Share yuk artikel ini… Facebook-f Link Twitter Instagram Whatsapp