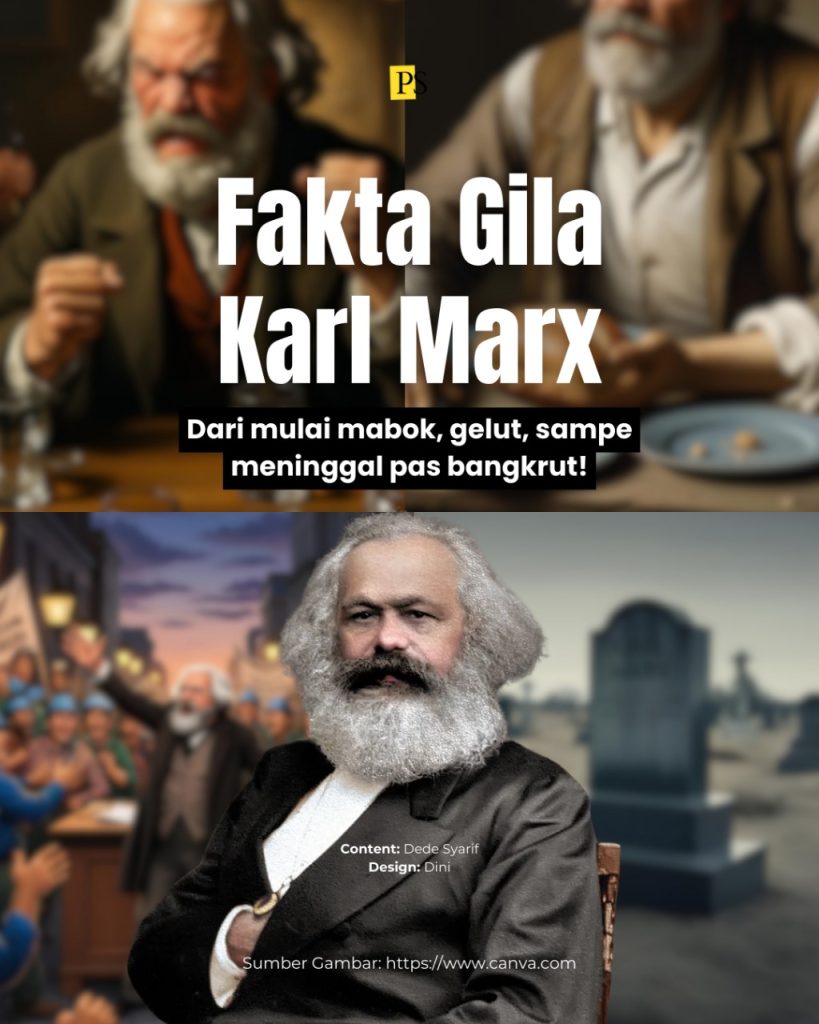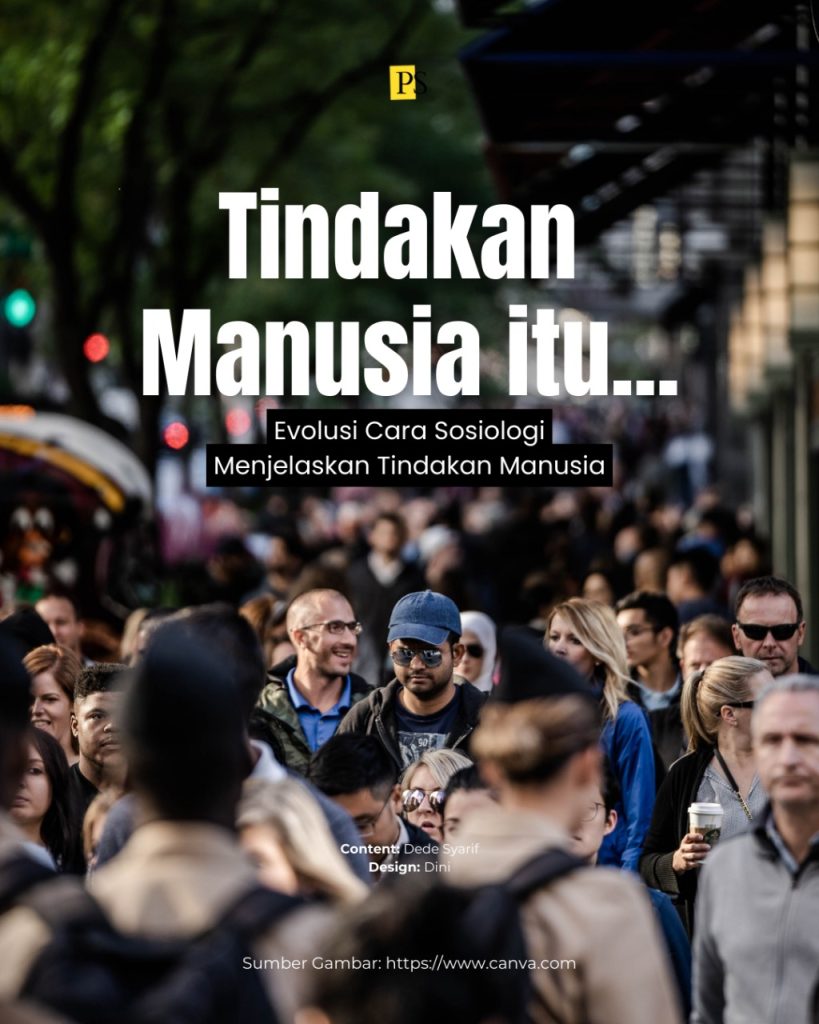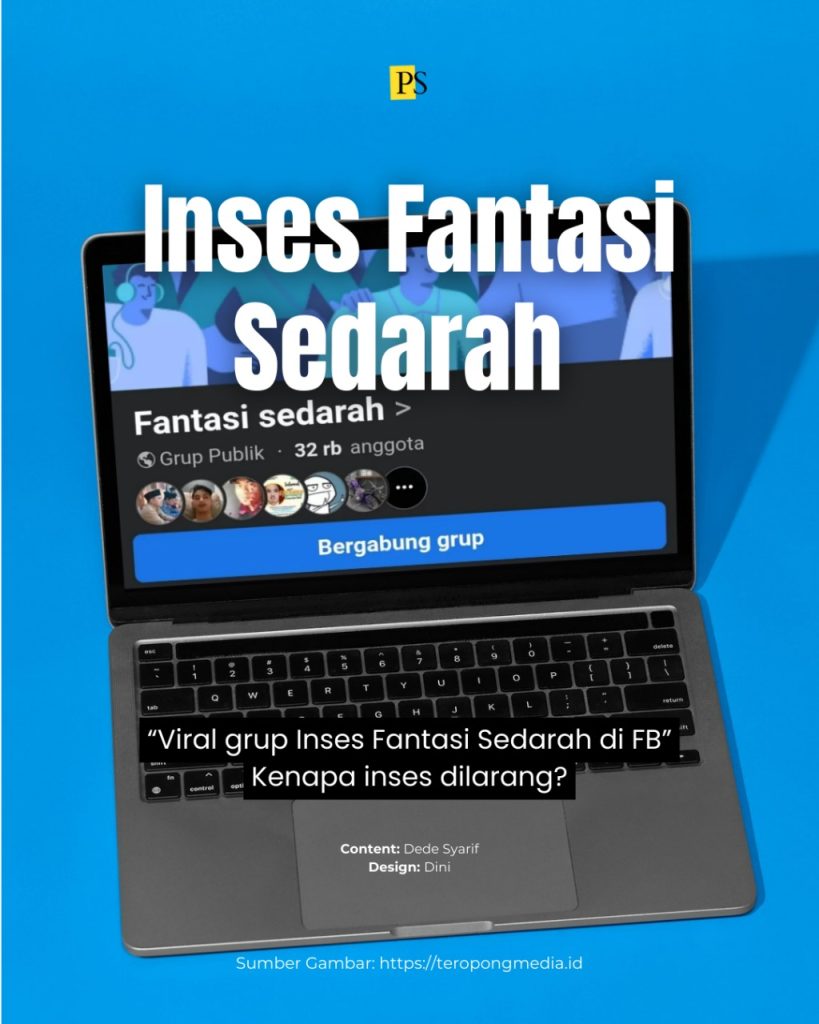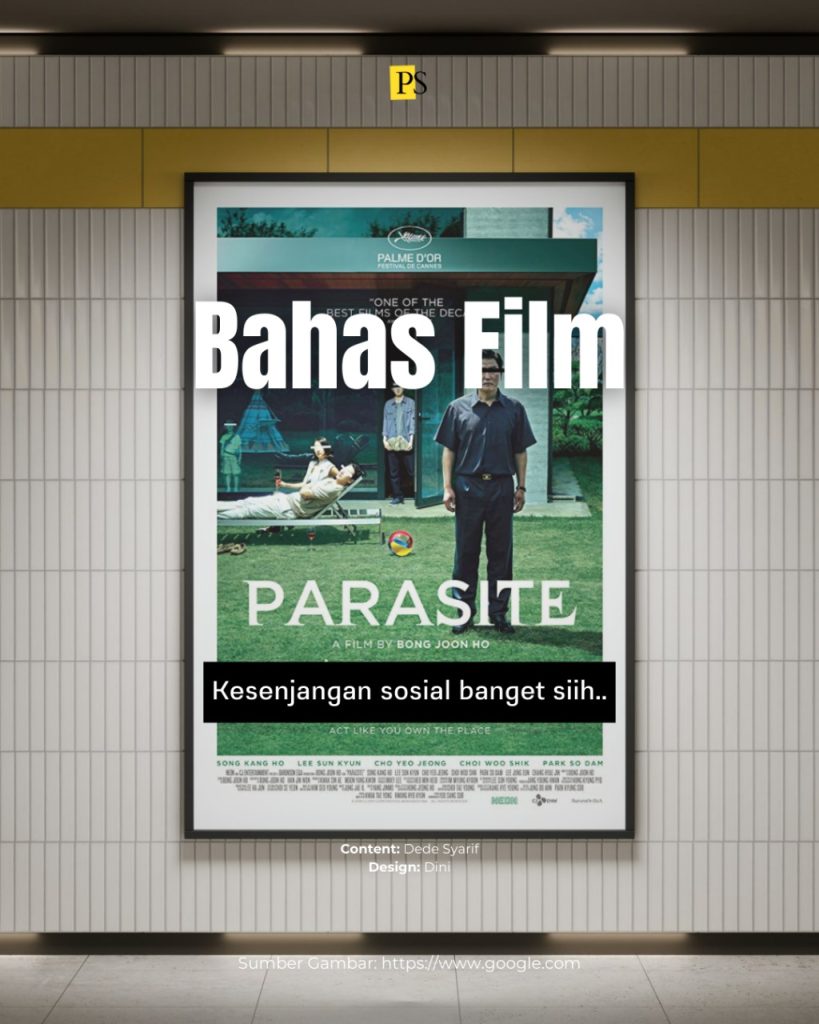5 Fakta Gila Tentang Karl Marx
Karl Marx dikenal sebagai bapak komunisme, pemikir besar dalam sejarah filsafat dan sosiologi. Tapi di balik gagasan-gagasannya yang serius, hidup Marx juga dipenuhi cerita-cerita nyeleneh dan tragis yang jarang dibahas di buku teks. Berikut lima fakta menarik (dan gila) tentang Karl Marx: 1. Suka Mabuk dan GeludSaat masih jadi mahasiswa di Universitas Bonn, Marx dikenal doyan minum dan sering terlibat perkelahian. Ia belajar filsafat G.W.F. Hegel dan bergabung dengan kelompok Hegelian Muda yang radikal. Kelakuannya sempat bikin heboh hingga dia pernah dipenjara karena mabuk dan berkelahi dengan mahasiswa lain. 2. Manusia Tanpa NegaraDi tahun 1840-an, Marx hidup seperti orang tanpa negara. Ia diusir dari Prusia tahun 1842, diusir lagi dari Prancis pada 1845, ditolak oleh Belgia di tahun 1848, dan terpaksa meninggalkan Prusia sekali lagi pada tahun yang sama. Hidupnya berpindah-pindah tanpa status kewarganegaraan tetap. 3. Istrinya Pernah Menggadaikan Celananya untuk Beli MakananSetelah pindah ke Inggris pada 1849, kehidupan Marx dan keluarganya dilanda kemiskinan. Mereka pernah diusir dari apartemen karena tak sanggup bayar sewa. Marx bahkan sempat menggunakan nama palsu untuk menghindari penagih utang. Yang paling menyedihkan: istrinya, Jenny, sampai harus menggadaikan celana milik Marx demi bisa membeli makanan. 4. Diancam Dibunuh karena Dianggap Kurang RadikalMeski dikenal revolusioner, Marx ternyata dianggap “kurang radikal” oleh sebagian kalangan. August Willich, mantan komandan militer Prusia dan sesama aktivis, bahkan sempat mengancam ingin membunuh Marx karena dianggap tidak cukup revolusioner. 5. Meninggal Bangkrut dan Hanya Dihadiri 11 Orang di PemakamannyaKehidupan Marx di penghujung usianya benar-benar tragis. Dalam suratnya kepada sahabat sekaligus pendukung finansialnya, Friedrich Engels, ia pernah menulis: “Kehidupan buruk seperti ini tidak layak untuk dijalani.” Marx meninggal dunia dalam keadaan bangkrut pada 14 Maret 1883. Pemakamannya di London hanya dihadiri oleh 11 orang. Sumber: Joe Carter, 5 Crazy Facts about Karl Marx, FEE Stories, 16 September 2018