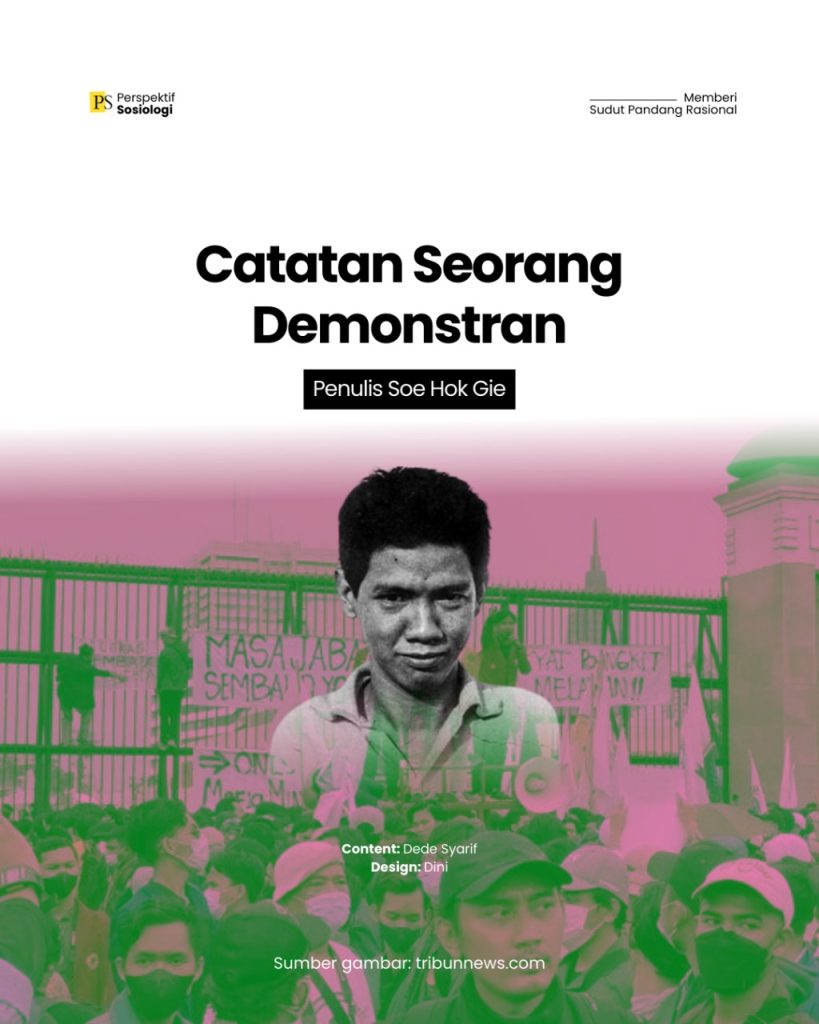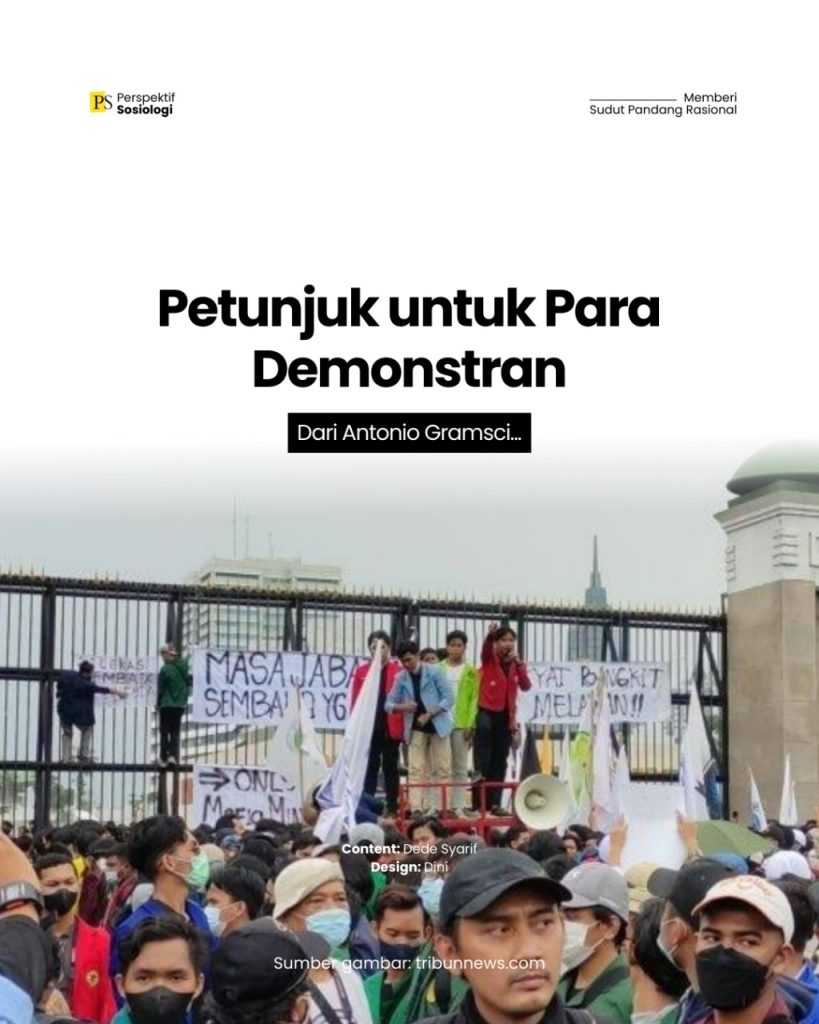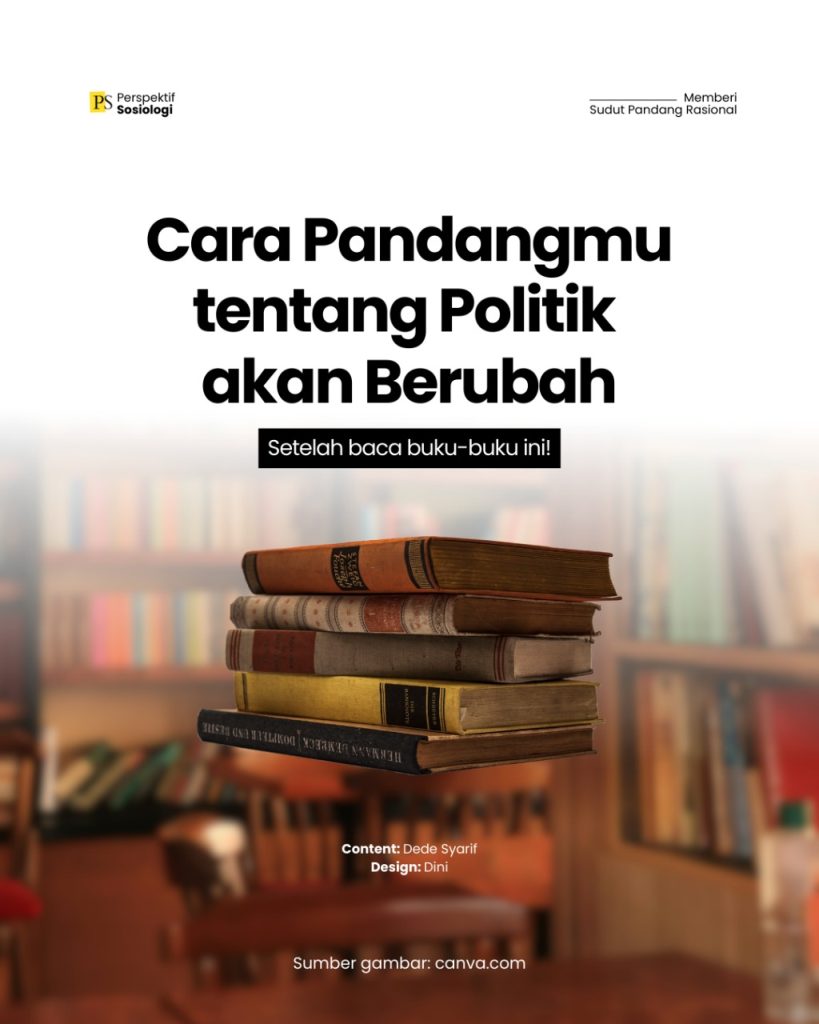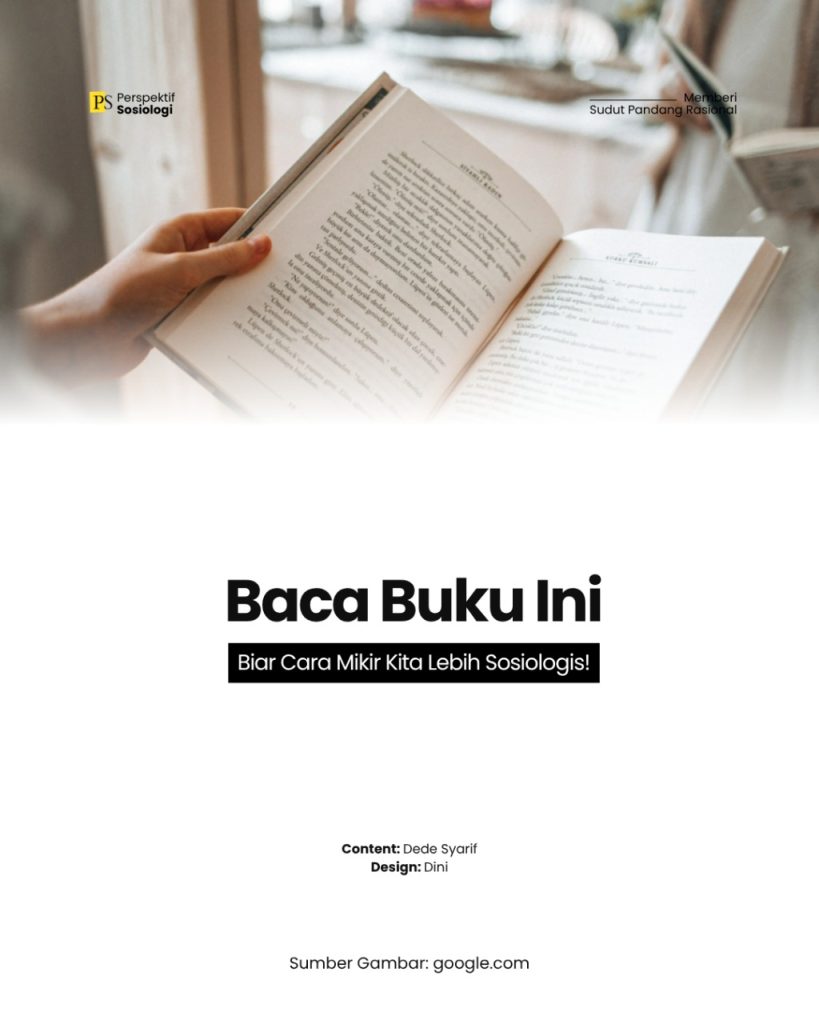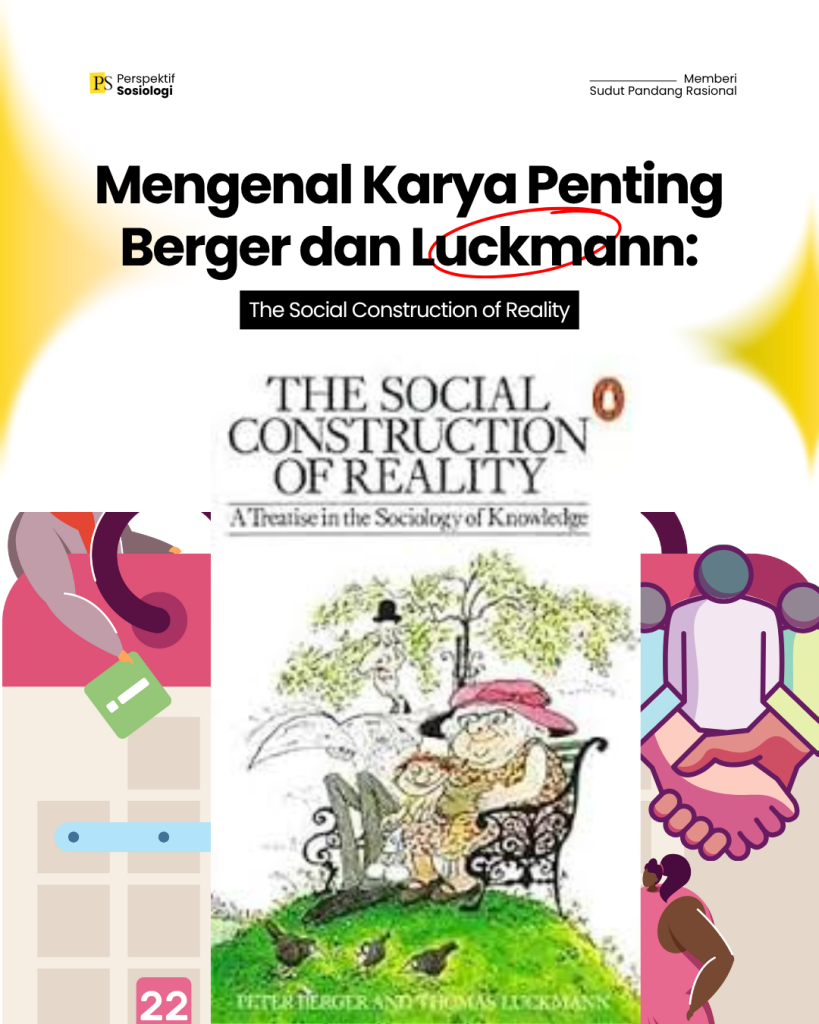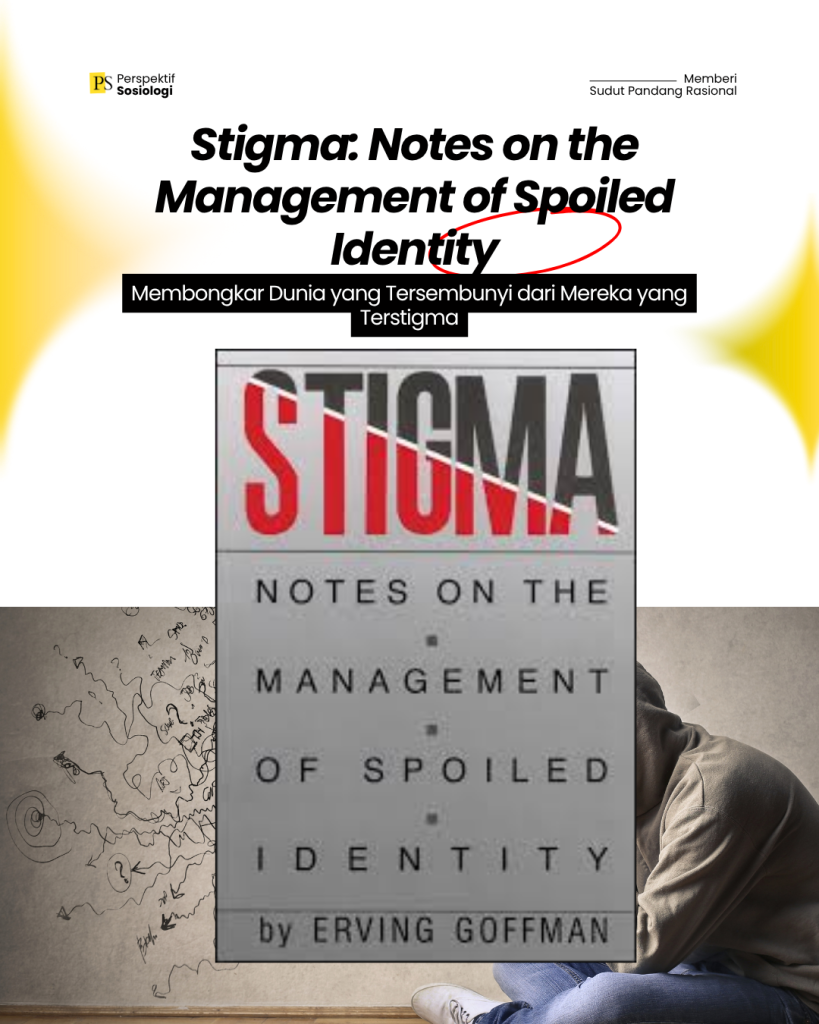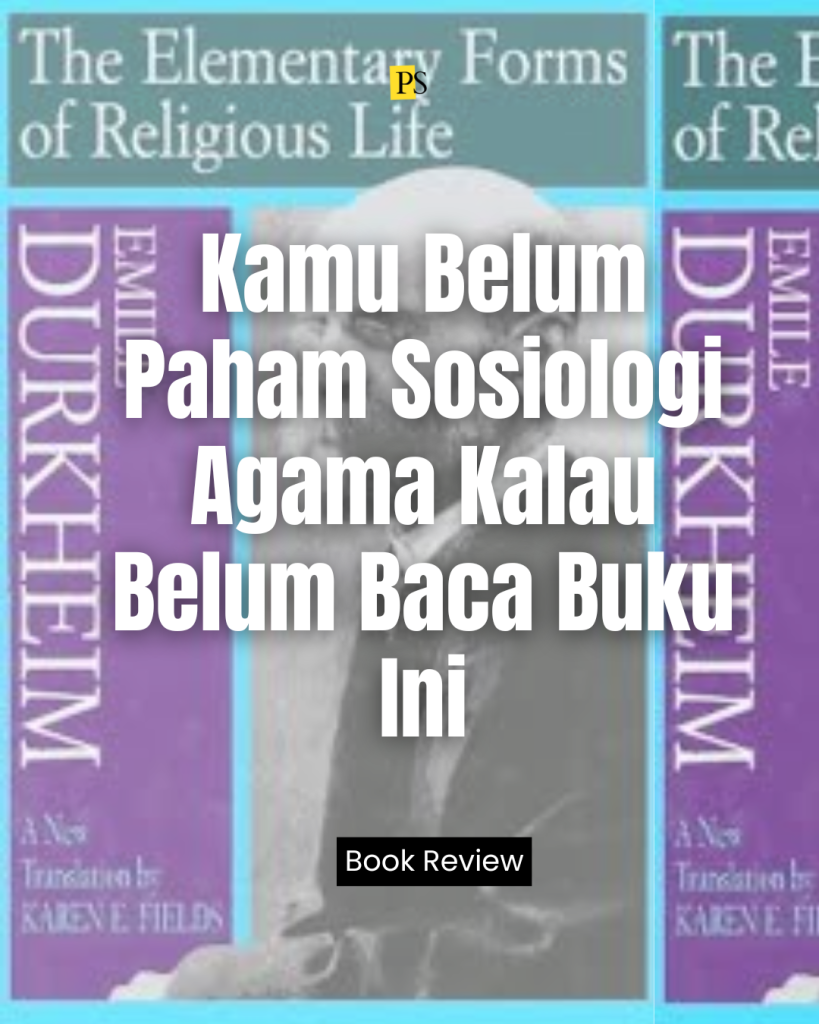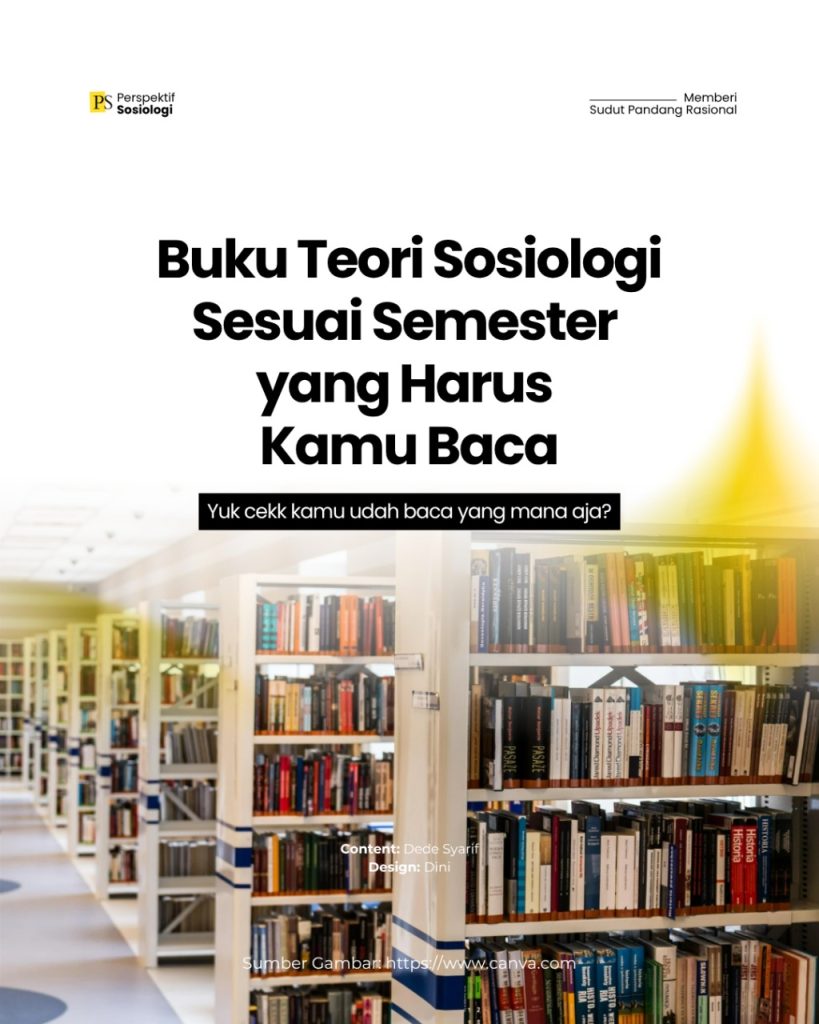Catatan Seorang Demonstran – Soe Hok Gie
Book Review Catatan Seorang Demonstran – Soe Hok Gie (Pustaka LP3ES Indonesia) “Bagiku ada sesuatu yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan: dapat mencintai, dapat iba hati, dapat merasai kedukaan. Tanpa itu semua maka kita tidak lebih dari benda. Berbahagialah orang yang masih mempunyai rasa cinta, yang belum sampai kehilangan benda yang paling bernilai itu. Kalau kita telah kehilangan itu maka absurdlah hidup kita.”— Soe Hok Gie Potret Seorang Aktivis Buku Catatan Seorang Demonstran adalah refleksi hidup dan perjuangan Soe Hok Gie, seorang mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang hidup di tengah gejolak politik Orde Baru. Tidak hanya seorang intelektual, Gie juga seorang pecinta alam, yang menyeimbangkan idealismenya dengan keindahan pegunungan yang sering ia daki. Melalui catatan harian, ia menghadirkan kesaksian langsung tentang pergulatan sosial-politik Indonesia di masa penuh ketidakadilan. Struktur dan Isi Buku Buku ini dibagi ke dalam delapan bagian: Soe Hok Gie: Sang Demonstran – pengantar tentang siapa Gie dan reputasinya. Masa Kecil – kisah keluarganya sebagai keturunan Tionghoa di Indonesia. Di Ambang Remaja – awal kesadarannya terhadap ketidakadilan sosial. Lahirnya Seorang Aktivis – langkah awal Gie masuk ke dunia pergerakan mahasiswa. Catatan Seorang Demonstran – catatan utama yang mencerminkan idealisme dan kritiknya. Perjalanan ke Amerika – perspektif global yang memperkaya wawasannya. Politik, Pesta, dan Cinta – sisi personal, pergulatan emosional, dan relasi sosial Gie. Mencari Makna – refleksi filosofis atas hidup, kemanusiaan, dan kemerdekaan individu. Isi dan Gagasan Utama Secara garis besar, buku ini menyingkap sosok Soe Hok Gie sebagai aktivis kampus dengan idealisme yang tajam. Gie bukan hanya menulis untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menyuarakan kepentingan publik, terutama kaum kecil dan termarjinalkan. Sebagai seorang keturunan Tionghoa, Gie sadar akan posisinya di tengah masyarakat yang sering memandang perbedaan etnis sebagai stigma, namun ia tetap memilih tegak di atas nilai universal: keadilan dan kemanusiaan. Dalam catatan-catatan yang penuh gairah intelektual, Gie mengkritik keras kesenjangan sosial, kebijakan pemerintah yang diskriminatif, serta sikap elit politik yang sering menindas rakyat kecil. Kritiknya bukanlah sembarang teriakan, tetapi analisis tajam yang ditulis dengan refleksi mendalam. Relevansi Sosial dan Politik Melalui catatan ini, kita dapat membaca dinamika sosial-politik Indonesia dari sudut pandang seorang demonstran yang merasakan langsung denyut jalanan. Ia berusaha menggugah keberanian mahasiswa untuk bersikap kritis, menolak tunduk pada intervensi kekuasaan politik, dan menempatkan prinsip kemanusiaan di atas kepentingan golongan maupun agama. Gie mengingatkan bahwa mahasiswa harus tetap menjaga kewarasan dan integritas, bahkan ketika berada dalam arus besar yang mencoba menyeret mereka. Sikapnya yang konsisten memilih menjadi “manusia merdeka” menjadikan sosok Gie relevan hingga kini. Kenapa Mahasiswa Harus Membacanya? Catatan Seorang Demonstran bukan hanya buku sejarah, melainkan cermin bagi generasi muda. Di tengah derasnya intervensi kekuasaan, buku ini menjadi pengingat agar mahasiswa tidak kehilangan daya kritis. Membaca Gie berarti belajar mencintai bangsa dengan cara yang jujur, keras, tetapi tetap berakar pada nurani kemanusiaan. Dr. Dede Syarif Dr. Dede Syarif adalah akademisi dan sosiolog UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lulusan Sosiologi UGM. Ia aktif dalam pengembangan ilmu sosiologi, termasuk melalui short course di Jerman dan Australia. Pendiri Perspektif Sosiologi ini kini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi FISIP UIN Bandung. Editor: Paelani Setia Lulusan Sosiologi yang pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa di Unisel, Selangor, Malaysia. Aktif menulis di bidang kajian sosiologi, agama, dan religious studies. Saat ini menjabat sebagai Manajer sekaligus Co-Founder komunitas kajian Perspektif Sosiologi. Address-card Instagram Share artikel ini yuk! Facebook-f Link Twitter Instagram Whatsapp