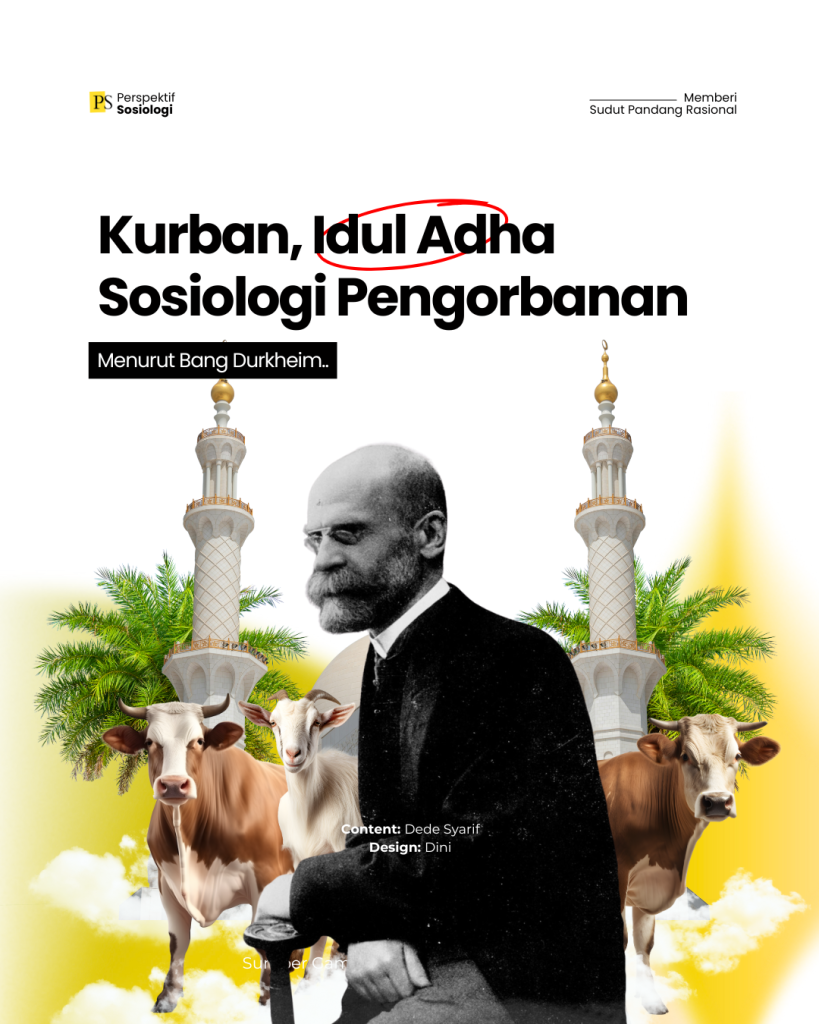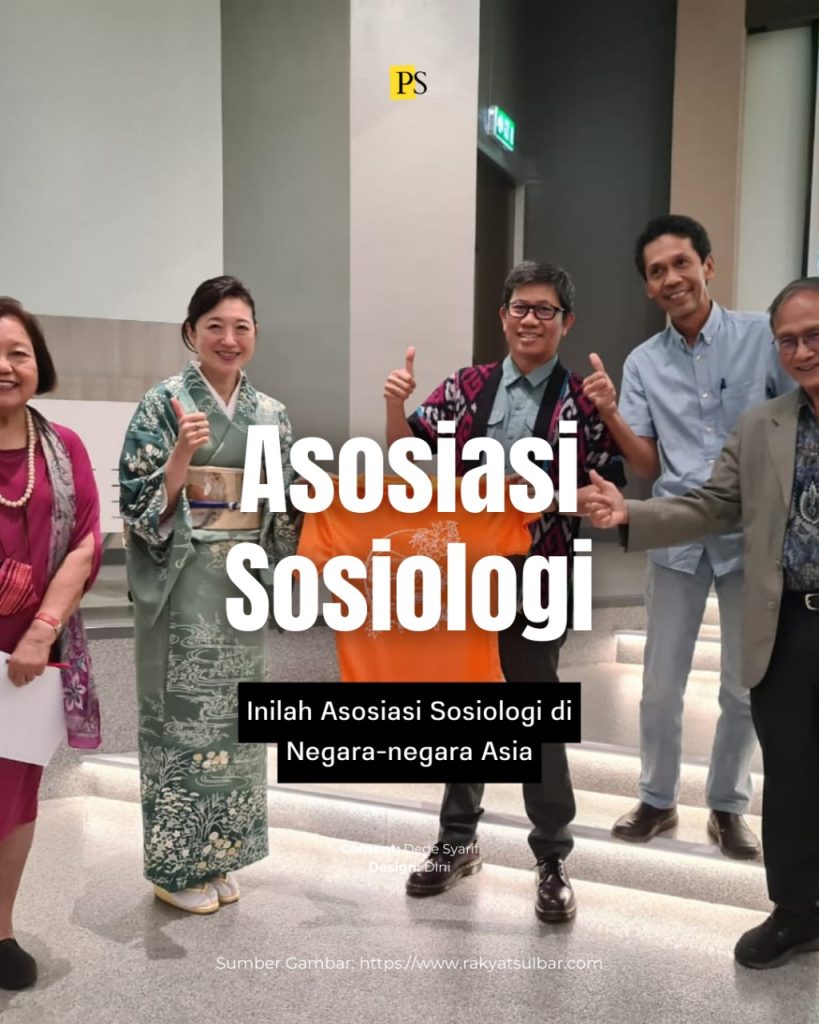Kurban, Iduladha, dan Sosiologi Pengorbanan Menurut Émile Durkheim
Info Kurban, Idul Adha, dan Sosiologi Pengorbanan Menurut Émile Durkheim Idul Adha atau Hari Raya Kurban merupakan salah satu momen penting dalam tradisi keagamaan umat Islam. Namun, di balik praktik penyembelihan hewan kurban, terdapat makna sosial dan simbolis yang dalam. Émile Durkheim, seorang sosiolog klasik, memberikan kerangka teoretis untuk memahami pengorbanan sebagai praktik sosial dan religius yang melibatkan lebih dari sekadar tindakan fisik. Bagi Durkheim, pengorbanan bukan hanya ibadah, tetapi juga medium yang menghubungkan manusia dengan yang sakral. Apa Itu Ritual Pengorbanan? Pengorbanan merupakan tindakan mempersembahkan sesuatu yang berharga—baik berupa harta benda, hewan, atau bahkan manusia—kepada entitas ilahi sebagai bentuk pemujaan atau upaya pendamaian. Tradisi ini tidak eksklusif milik Islam, tetapi sudah ada sejak masa peradaban Ibrani, Yunani kuno, hingga komunitas-keagamaan paling awal. Dalam perspektif Durkheim, ritual pengorbanan ini menjadi fondasi dalam sistem keagamaan, karena mengandung fungsi sosial yang kuat dalam membentuk kohesi komunitas. Asal-usul Istilah dan Makna Qurban Kata sacrifice berasal dari bahasa Latin sacrificus, gabungan dari sacra (hal-hal suci) dan facere (membuat atau melakukan). Dalam konteks Islam, istilah kurban atau ḏabiḥa (ذَبِيْحَة) memiliki akar dari bahasa Arab dan Ibrani, yakni qurban atau korban, yang menunjukkan pendekatan atau kedekatan kepada Tuhan. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya menyimbolkan ketaatan, tetapi juga bentuk komunikasi spiritual antara manusia dan Tuhan. Fungsi Sosial dan Religius Pengorbanan Durkheim menekankan bahwa pengorbanan bukan hanya ritual, tetapi proses transformasi yang mendalam bagi mereka yang terlibat. Ia berfungsi sebagai media penyucian dan sebagai alat untuk membangun kembali ikatan sosial dalam komunitas. Dalam upacara keagamaan, hewan yang dikorbankan berperan sebagai perantara antara dunia profan (yang biasa) dan dunia sakral (yang suci). Karena kesucian bersifat “tak tersentuh”, mediasi harus dilakukan melalui simbol yang bisa dihancurkan—yaitu hewan kurban. Dengan kata lain, korban menjadi medium komunikasi yang mempertemukan dua ranah eksistensial manusia. Sakralitas dan Dunia yang Terpisah Pengorbanan menurut Durkheim adalah jembatan penghubung sekaligus pemisah antara dunia sakral dan profan. Ia adalah pintu simbolis yang hanya bisa dibuka melalui tindakan ritus pengorbanan. Tindakan ini melibatkan proses memberi dan menerima melalui pengorbanan subjek yang dikuduskan. Itulah sebabnya, dalam banyak tradisi keagamaan di dunia—baik di masa lalu maupun sekarang—pengorbanan selalu menempati posisi inti dalam praktik beragama. Ia menegaskan kembali keterikatan komunitas terhadap nilai-nilai sakral dan memperbaharui hubungan mereka dengan kekuatan transendental. Sumber:Durkheim, Émile. (1995 [1912]). The Elementary Forms of Religious Life: The Totemic System in Australia. K. E. Fields. Free Press, New York.Faherty, R. L. (2022, January 30). Sacrifice. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/sacrifice-religion Dr. Dede Syarif Dr. Dede Syarif adalah seorang akademisi dan sosiolog dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang menempuh pendidikan sosiologi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia dikenal aktif dalam pengembangan ilmu sosiologi melalui berbagai kegiatan akademik, termasuk mengikuti short course di Jerman dan Australia. Selain itu, Dr. Dede merupakan pendiri komunitas kajian Perspektif Sosiologi yang berfokus pada analisis isu-isu sosial kontemporer. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Sosiologi di tingkat S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Bandung Address-card Instagram Share yuk artikel ini… Facebook-f Link Twitter Instagram Whatsapp