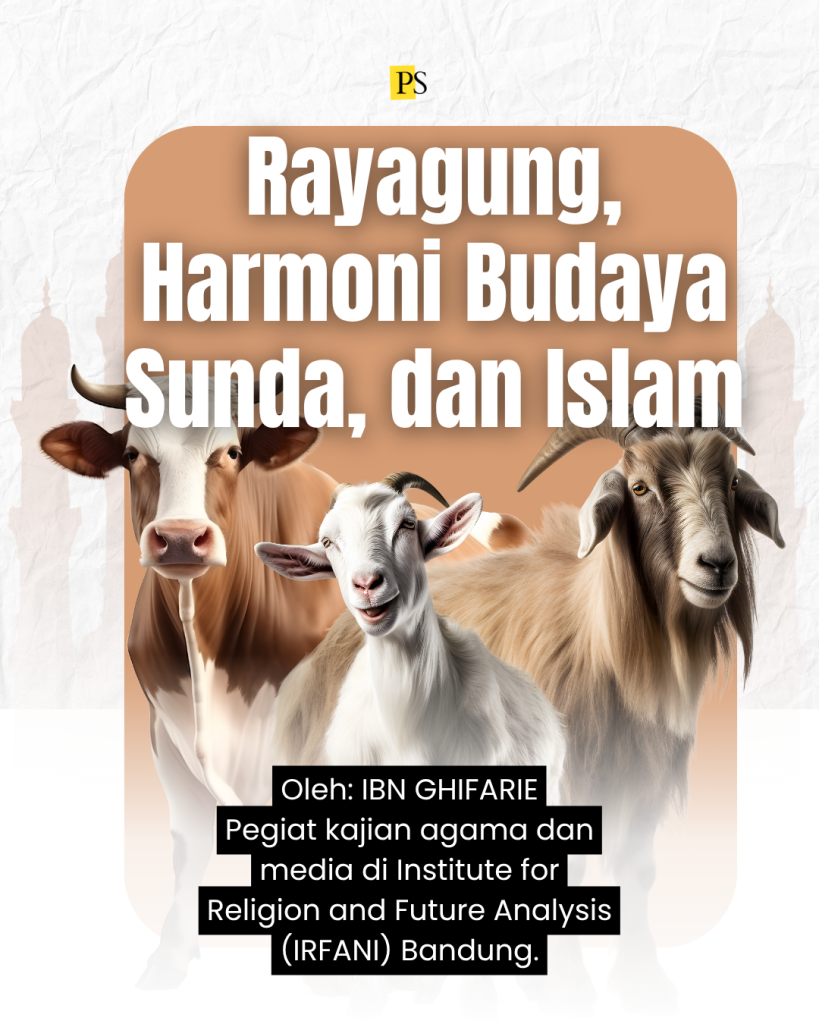Kolom Rayagung, Harmoni Budaya Sunda, dan Islam Rayagung merupakan salah satu bulan yang istimewa dalam tradisi dan keyakinan umat Islam. Ini merujuk pada bulan Zulhijah, yang dikenal erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji, Idulkurban (Iduladha), lebaran haji, puasa Arafah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa bulan Zulhijah termasuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan Allah, selain Muharam dan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada hari-hari yang lebih agung, dan amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari itu, melebihi sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid pada hari-hari tersebut.” Saking istimewanya, Rasulullah menganjurkan puasa Arafah bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nabi bersabda, “Berpuasa di hari Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang.” Tentunya ini menunjukkan betapa besar keutamaan bulan Zulhijah, khususnya pada sepuluh hari pertama. Berbeda dengan bulan Zulkaidah, yang dalam masyarakat Sunda dikenal sebagai bulan “hapit”, untuk aktivitas sosial seperti hajatan (pernikahan, khitanan) cenderung sedikit, baik di desa maupun di kota. Justru terus tumbuh berkembang, marema saat bulan Zulhijah. Walhasil, sangat erat nilai-nilai budaya dan religi dan turut memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat dalam menyambut Rayagung. Makna RayagungRupanya bagi Dede Syarif, keistimewaan bulan Rayagung menginspirasi cara beragama orang Sunda. Dalam kosmologi urang Sunda dikenal hari baik. Setiap waktu baik itu tiba, maka masyarakat melaksanakan berbagai perhelatan penting, seperti pernikahan, nyunatan anak, memulai usaha, bahkan membangun rumah. Salah satu bulan yang diyakini sebagai bulan baik adalah bulan Rayagung ini. Maka pada setiap bulan Rayagung tiba, kita menjumpai berbagai acara penting seperti resepsi pernikahan. Pilihan pada bulan ini, barangkali dilatarbelakangi bulan ini merupakan bulan yang dimuliakan Allah. Dengan berharap pada keistimewaan bulan ini, maka acara penting dilangsungkan, terutama yang menyangkut taliparanti (life circle) dalam kehidupan masyarakat Sunda. Rayagung dengan segala keistimewaannya telah menggoreskan sktsa pada potret kebudayaan masyarakat Sunda. Goresan ini menciptakan mozaik kekayaan tradisi yang menjadi energi dalam kehidupan sosial, keagamaan dan ekonomi masyarakat muslim di dunia (Sunda). Inilah titik yang dalam The Elementary Forms of Religious Life (1912) Emile Durkheim disebut sebagai ritual. Sebuah unsur keagamaan dimana masyarakat menciptakan nilai-nilai suci (sacral) yang akan mereka hormati untuk dijadikan aturan sosial (social order) dalam kehidupan mereka sebagai sebuah masuarakat beragama. Ritual menjadikan agama, keyakinan tertentu menjadi unik, khas dan berbeda dengan keyakinan lain. Pada wilayah ini, agama merupakan ekspresi dan terjemahan para penganutnya dalam ruang sosial masing-masing (Radea Juli A Hambali & Dede Syarif [ed], 20-10:99-103). Takdir Sunda-IslamIslam yang hadir di tatar Sunda ini telah memperkaya potensi kemanusiaan orang Sunda sendiri sebagaimana budaya Sunda, dengan caranya sendiri telah ikut andil dalam memperkaya peradaban Islam. Bagi masyarakat Sunda Islam yang masih menjadikan kesundaannya sebagai identitas dan bagian integral dirinya. Islam dipandang sebagai lokus yang memberi ruang formal sebagai penyempurna dalam mewadahi pengalaman batin dan nilai-nilai kearifan lokal dan pengalaman batin masyarakat Sunda (Ahmad Gibson Albustomi, 2012; ix-x). Di tangan Hasan Mustapa, Sunda dan esoterisme Islam menjadi menyatu tak ubahnya gula dan peueut-nya (manisnya). Seolah Hasan Mustapa hendak menunjukkan bahwa Sunda dan Islam adalah sesuatu yang compatible. Hal ini tidak terlepas dari kerangka berpikirnya yang dengan tegas merestui hubungan “saling mengisi” antara Islam dan budaya lokal kesundaan, bukan hubungan saling menegasikan. Kalaupun ada pertentangan-pertentangan antara keduanya, maka hal itu hanya terjadi pada level yang bersifat permukaan saja. Bahasa diperlakukan Hasan Mustapa sebagai media untuk mencari kemungkinan makna-makna baru, menjadi dinamis, dan terbuka. Dalam ungkapannya, Nya basa wayang kalangkangTapi dalangna pribadi… Kumaha alam pribadiNyusul-nyusul alam baturTangtu béda babasanPerbawa ati birahiBéda alam moal sarua rasana Dengan ungkapan lain, Islam tidak perlu membid’ahkan tradisi lokal, apalagi menganggapnya sebagai kafir, tapi harus mengakomodasi tradisi itu menjadi bagian tak terpisahkan dari agama itu sendiri agar seorang yang beragama tidak kemudian kehilangan tautan budayanya, supaya tidak kehilangan orientasi kulturalnya. Ini sebagaimana dahulu Tuhan ‘meminjam’ bahasa Arab dengan segala nafas kulturalnya untuk mewadahi gagasan-Nya (Al-Quran). Beragama tidak otomatis harus menjadi manusia Arab dengan segala atribut budaya yang mengitarinya. Bahkan menjadi manusia Sunda sejati justru adalah cermin melakukan perjalanan tanpa batas terhadap jantung keberagamaan itu sendiri. Maka, menjadi dapat dipahami metafora yang digunakan Hasan Mustapa sebagai idiom yang hidup tumbuh dalam alam pikiran masyarakat Sunda, seperti rebung dengan bambu atau pohon aren dengan caruluk (buah aren), untuk menggambarkan awor-nya (melekat) hubungan antara hamba (kaula) dengan Tuhan (Gusti). Dalam cerita-cerita lain yang berkembang di masyarakat Sunda, seperti Mundinglaya Dikusumah, Hariang Banga, Ciung Wanara, Sunan Ambu, Prabu Siliwangi, Ratu Galuh, dan Dayang Sumbi, untuk ‘mengganti’ cerita tokoh-tokoh Islam, dan sebagainya. Dengan suluknya yang penuh lambang, yang kemudian dijadikannya sebagai bagian dari sejarah pengalaman kesehariannya, maka agama (Islam) dan budaya (Sunda) di tangan Hasan Mustapa benar-benar mampu tampil melampaui tapal batas formalisme dan menusuk ke jantung (mataholang) penghayatan religiositas dan lipatan-lipatan tradisi. Dengan demikian, “Islam Sunda” menjadi sesuatu yang wajar, satu varian yang kehadirannya tidak perlu dipersoalkan sebagaimana varian Islam India, Islam Persia, Islam Arab, Islam Melayu, dan sebagainya. Menghidupkan kembali sulukala Hasan Mustapa menjadi amat penting diperhatikan di tengah situasi kebangsaan dan aras kesundaan yang akhir- akhir ini malah didominasi oleh pemikiran dan gerakan Islam puritan yang lebih mengedepankan aspek “wadah” ketimbang “isi”, lebih menonjolkan arabisme daripada jiwa kesundaannya. Padahal justru, sebagaimana ditulis Ali Harb (1996), semarak ritual keagamaan yang simbolistik hanya akan menyusutkan substansi moralitas dan spirit keagamaan. Sebaliknya, keberagamaan yang substantif akan memperteguh nilai-nilai ideal agama itu sendiri serta menginspirasikan perubahan sosial dan budaya ke arah ruang hidup yang berharkat (Asep Salahudin, 2017: 41-42). Dengan demikian, penyelenggaraan pernikahan, sunatan, dan syukuran haji dalam momentum Rayagung menjadi bukti nyata harmonisasi antara budaya Sunda dan ajaran Islam. Ini sekaligus mencerminkan identitas Muslim Jawa Barat yang berakar kuat pada khazanah kearifan lokal. Pasalnya, bangsa yang besar tidak akan melupakan tradisi dan budayanya sendiri. Justru, keberadaan budaya daerah, seperti budaya Sunda, merupakan salah satu pilar penting yang menopang keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. IBN GHIFARIE Pegiat kajian agama dan media di Institute for Religion and Future Analysis (IRFANI) Bandung. Instagram Share yuk artikel ini… Facebook-f Link Twitter Instagram Whatsapp