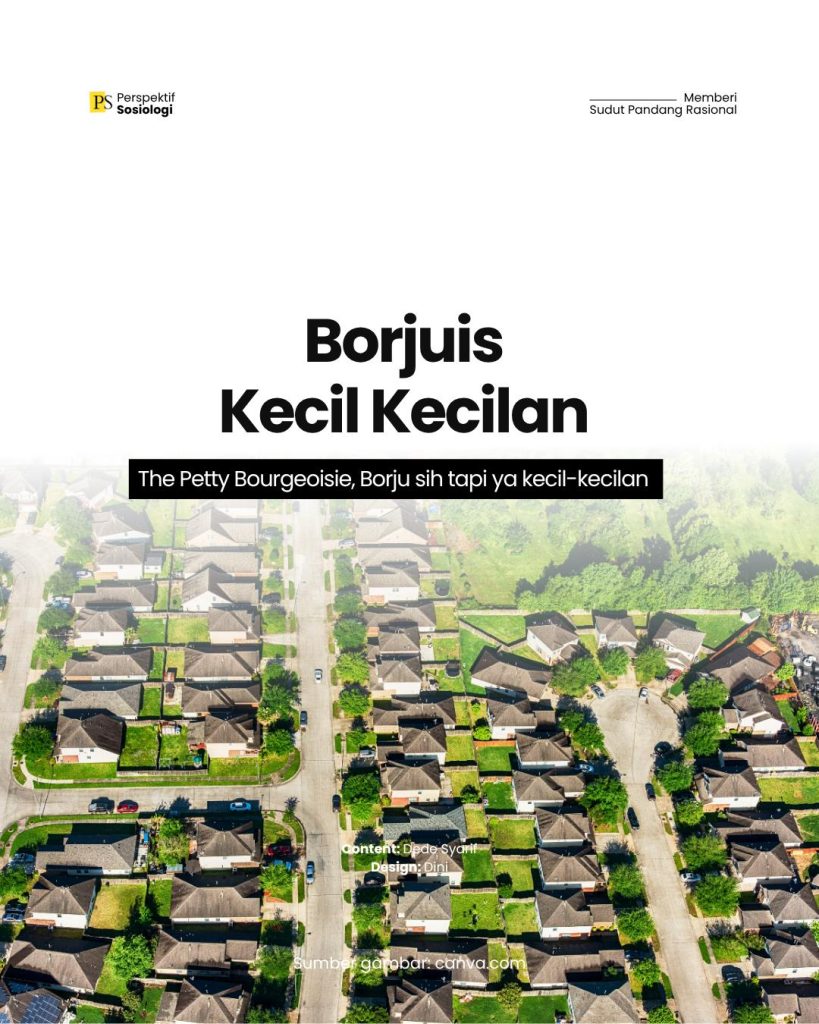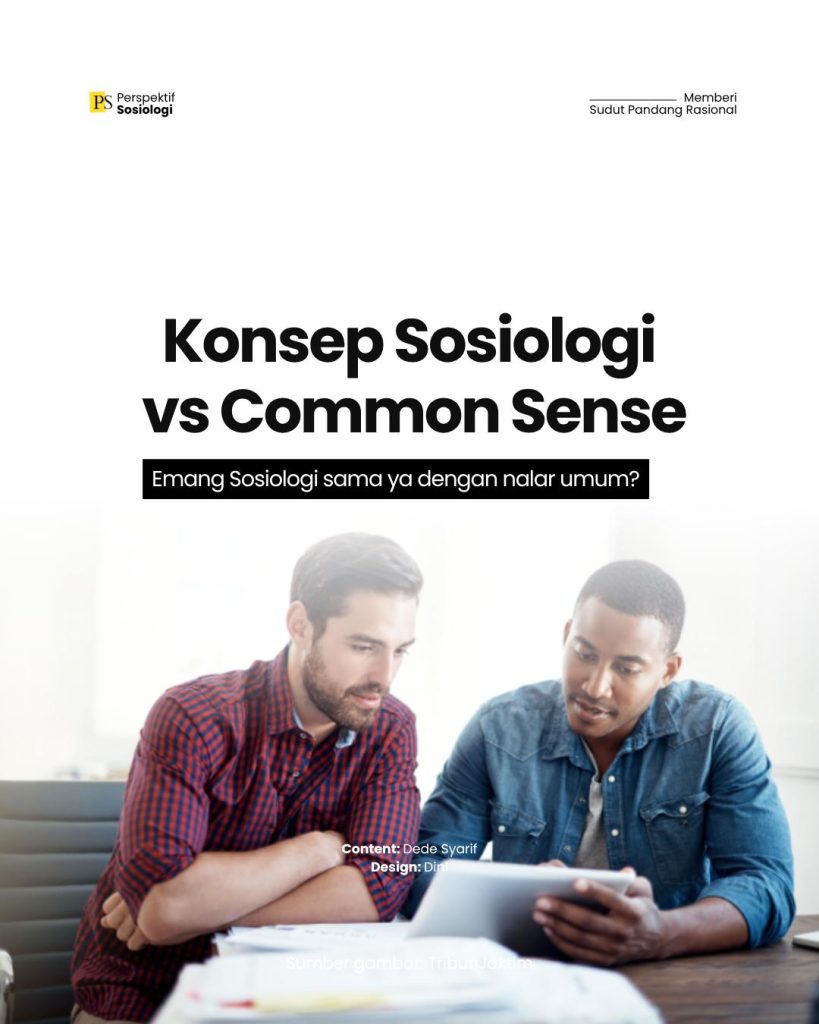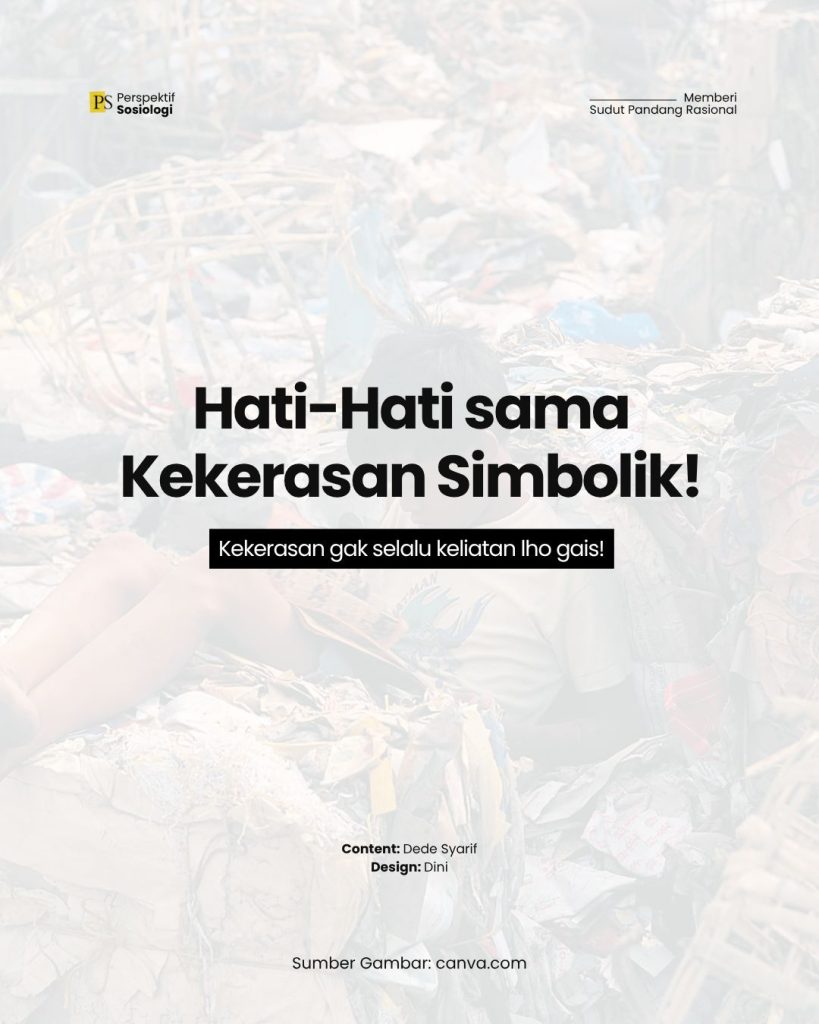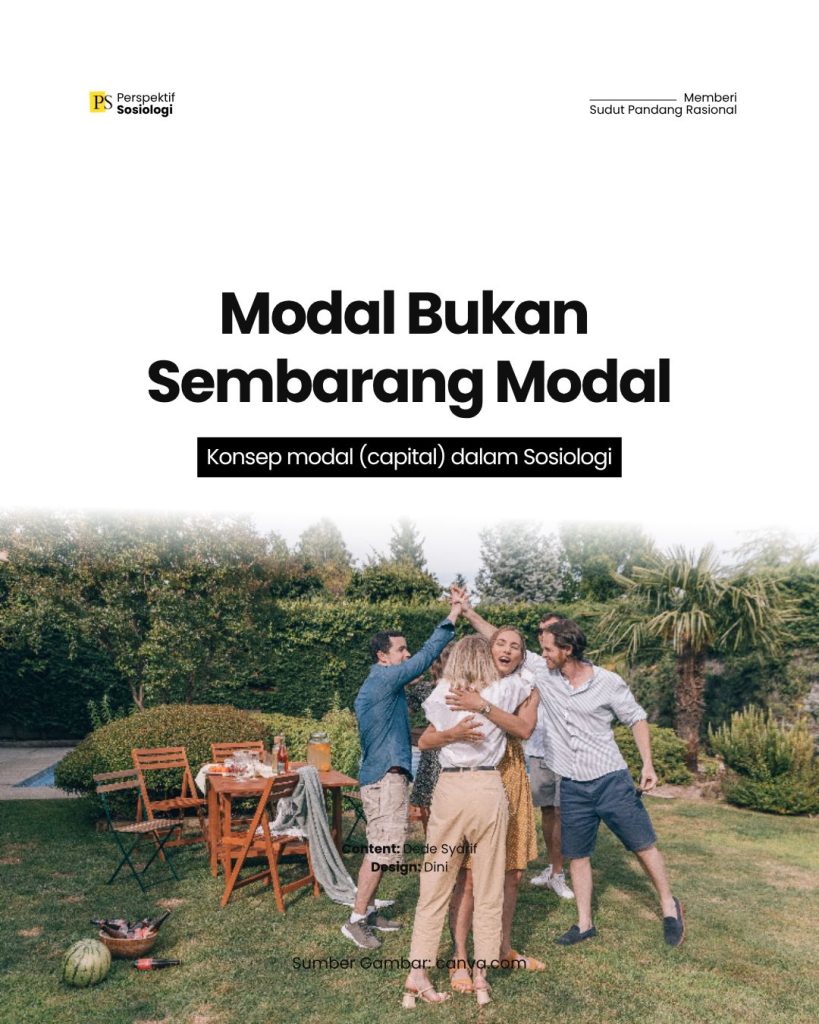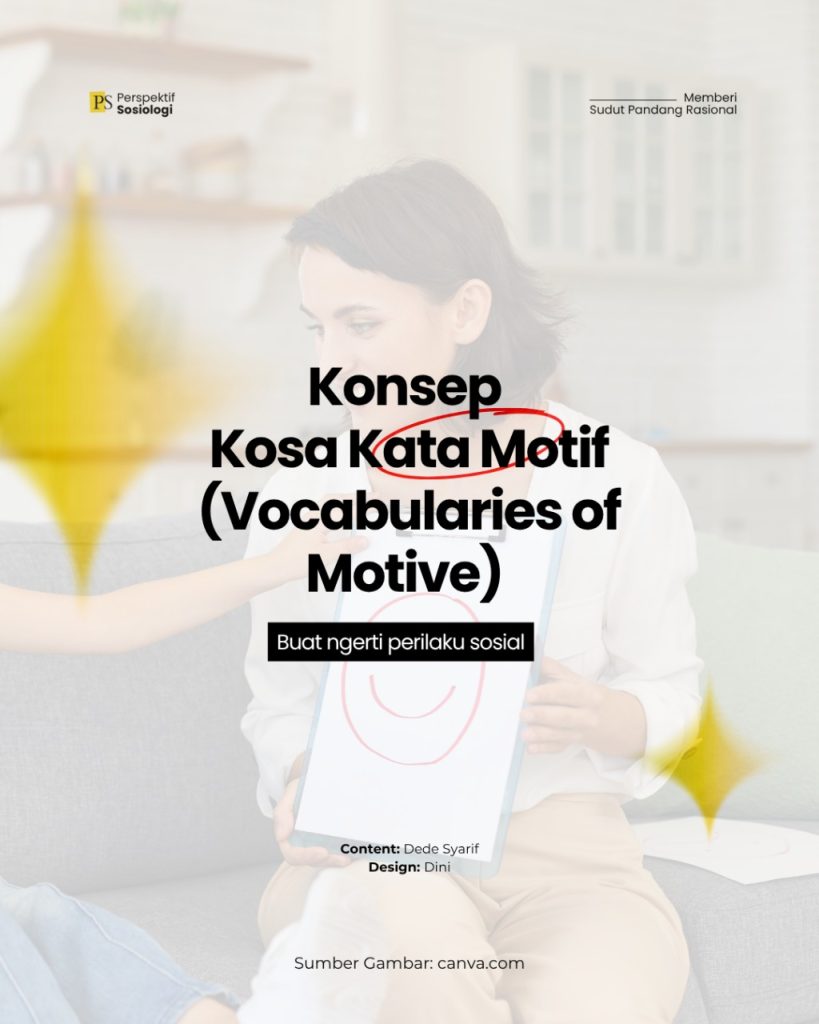Metateori: Teori di Atas Teori
Konsep Metateori: Teori di Atas Teori Apa Itu Metateori? Metateori dapat dipahami sebagai teori di atas teori. Berbeda dengan teori sosiologi konvensional yang berfungsi menjelaskan realitas sosial, metateori justru meneliti kembali teori-teori itu sendiri. Dengan kata lain, metateori adalah alat analisis yang digunakan untuk memeriksa hakikat, struktur, dan fungsi teori. Ia membantu sosiolog melihat lebih kritis bagaimana sebuah teori dibangun, termasuk asumsi epistemologis, metodologi, hingga bias yang melatarbelakanginya. Tujuan Metateori Metateori tidak sekadar menelaah teori, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih mendalam. Intinya adalah untuk mengungkap bias dan perspektif tersembunyi yang membentuk suatu teori. Dengan cara ini, sosiolog dapat memahami tidak hanya isi teori, tetapi juga bagaimana teori itu muncul, berkembang, dan berfungsi dalam konteks tertentu. Mengapa Metateori Penting? Refleksi Teoretis – Metateori mendorong sosiolog untuk merefleksikan kerangka teoretis yang mereka gunakan. Ini memastikan bahwa asumsi dasar dari teori tidak diabaikan, melainkan diakui dan dapat dievaluasi secara kritis. Dialog Antar-Perspektif – Dengan menelaah asumsi dasar dari berbagai teori, metateori memfasilitasi dialog antara perspektif teoretis yang berbeda. Hal ini memperkaya pemahaman kita tentang fenomena sosial karena mampu menyingkap persamaan sekaligus perbedaan di antara teori. Mendorong Inovasi Teori – Metateori tidak berhenti pada kritik, tetapi juga membuka ruang bagi pembaruan dan inovasi teori. Dengan melihat teori klasik dalam konteks baru, sosiolog dapat menghasilkan teori-teori yang lebih relevan dengan kondisi sosial kontemporer. Contoh Hasil Metateori: Teori McDonaldization Salah satu contoh nyata hasil dari praktik metateori adalah Teori McDonaldization yang dikembangkan George Ritzer. Ritzer melakukan refleksi terhadap teori birokrasi Max Weber, terutama pada konsep rasionalitas. Ia menemukan bahwa prinsip-prinsip rasionalisasi yang dikemukakan Weber—efisiensi, prediktabilitas, kalkulasi, dan kontrol—juga berlaku dalam sistem restoran cepat saji modern, khususnya McDonald’s.Dengan demikian, teori birokrasi klasik Weber berhasil dikontekstualisasikan ke dalam fenomena kontemporer, yaitu budaya konsumsi dan organisasi bisnis global. Inilah bukti bagaimana metateori tidak hanya mengkritisi teori lama, tetapi juga melahirkan kerangka baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dr. Dede Syarif Dr. Dede Syarif adalah akademisi dan sosiolog UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lulusan Sosiologi UGM. Ia aktif dalam pengembangan ilmu sosiologi, termasuk melalui short course di Jerman dan Australia. Pendiri Perspektif Sosiologi ini kini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi FISIP UIN Bandung. Editor: Paelani Setia Lulusan Sosiologi yang pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa di Unisel, Selangor, Malaysia. Aktif menulis di bidang kajian sosiologi, agama, dan religious studies. Saat ini menjabat sebagai Manajer sekaligus Co-Founder komunitas kajian Perspektif Sosiologi. Share artikel ini yuk! Facebook-f Link Twitter Instagram Whatsapp