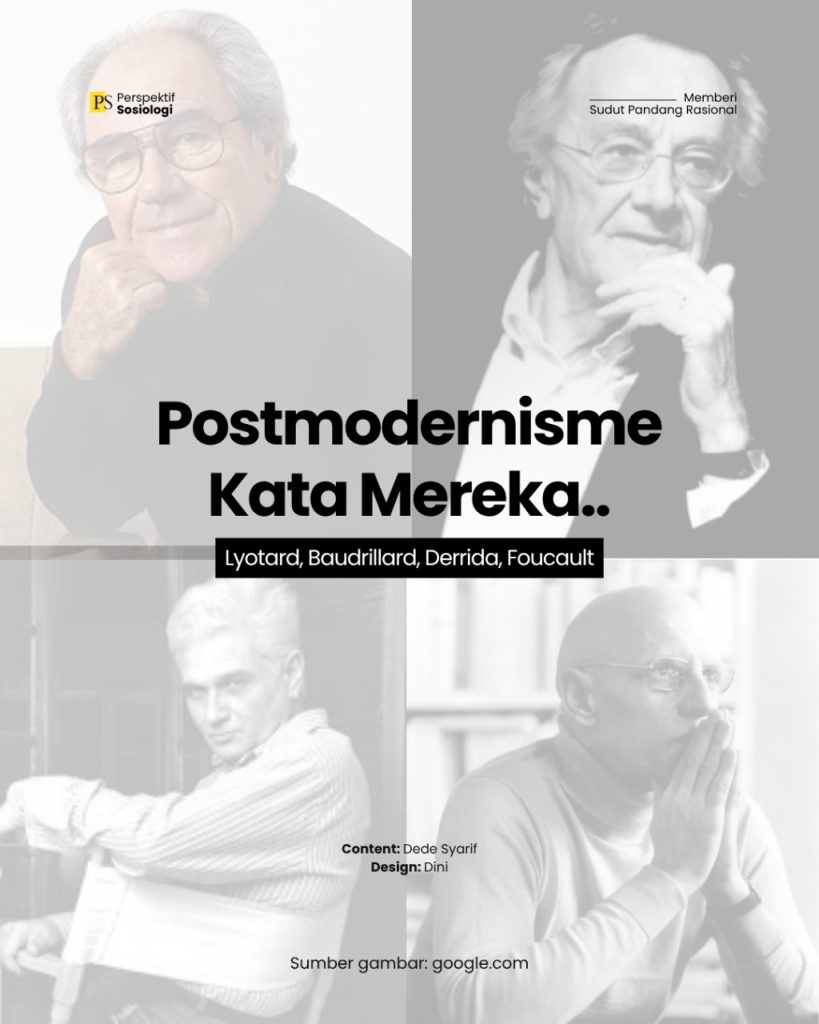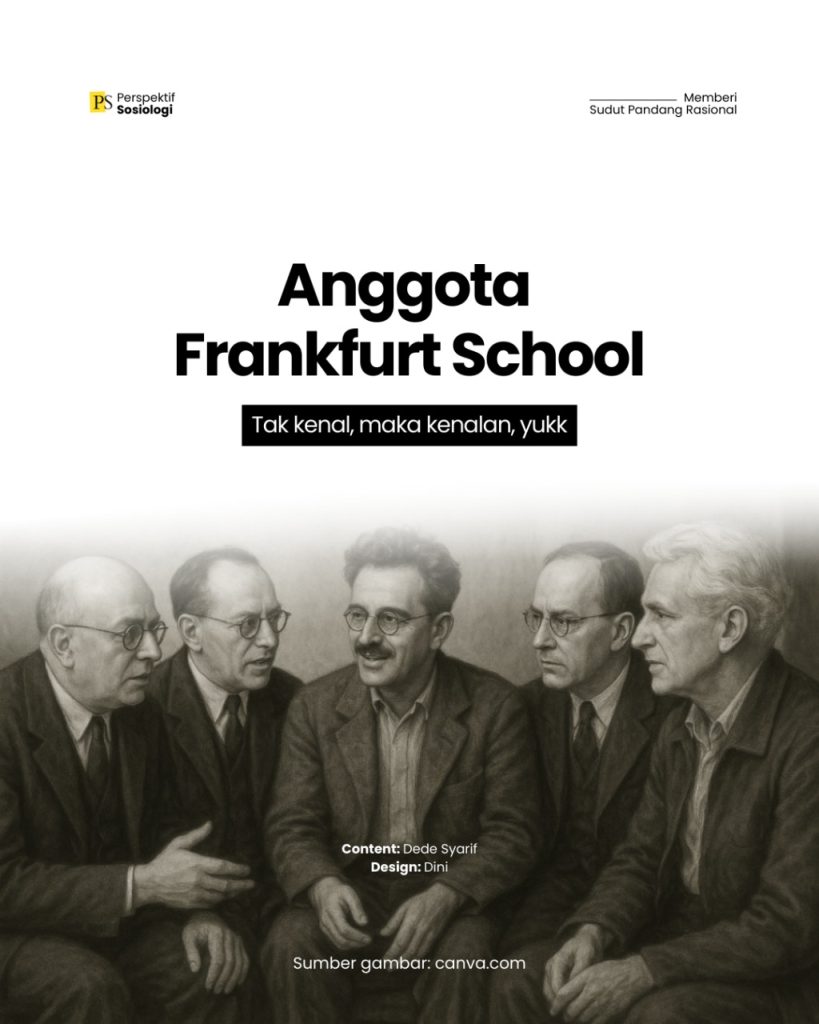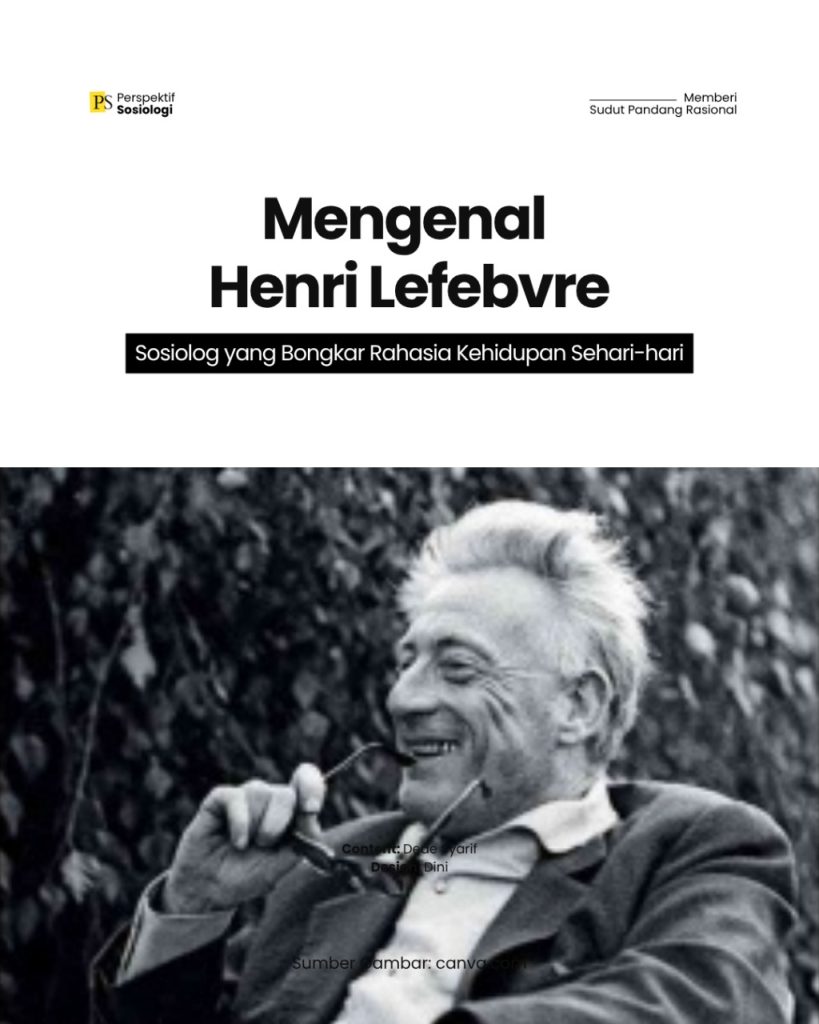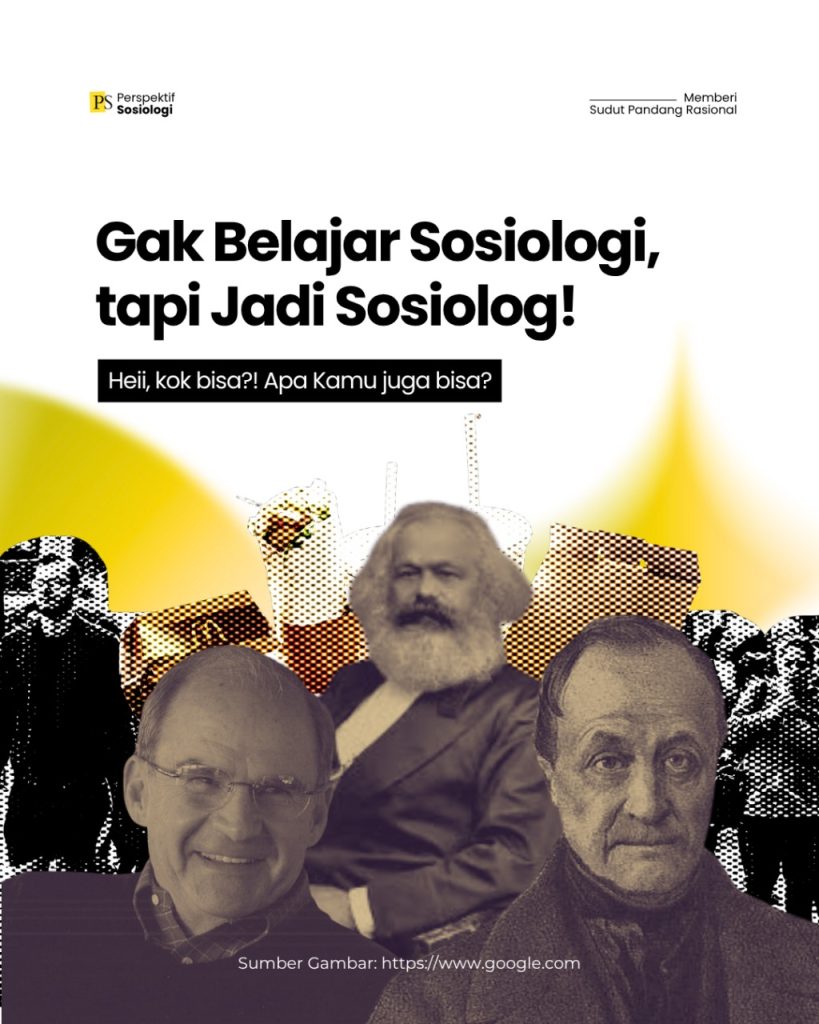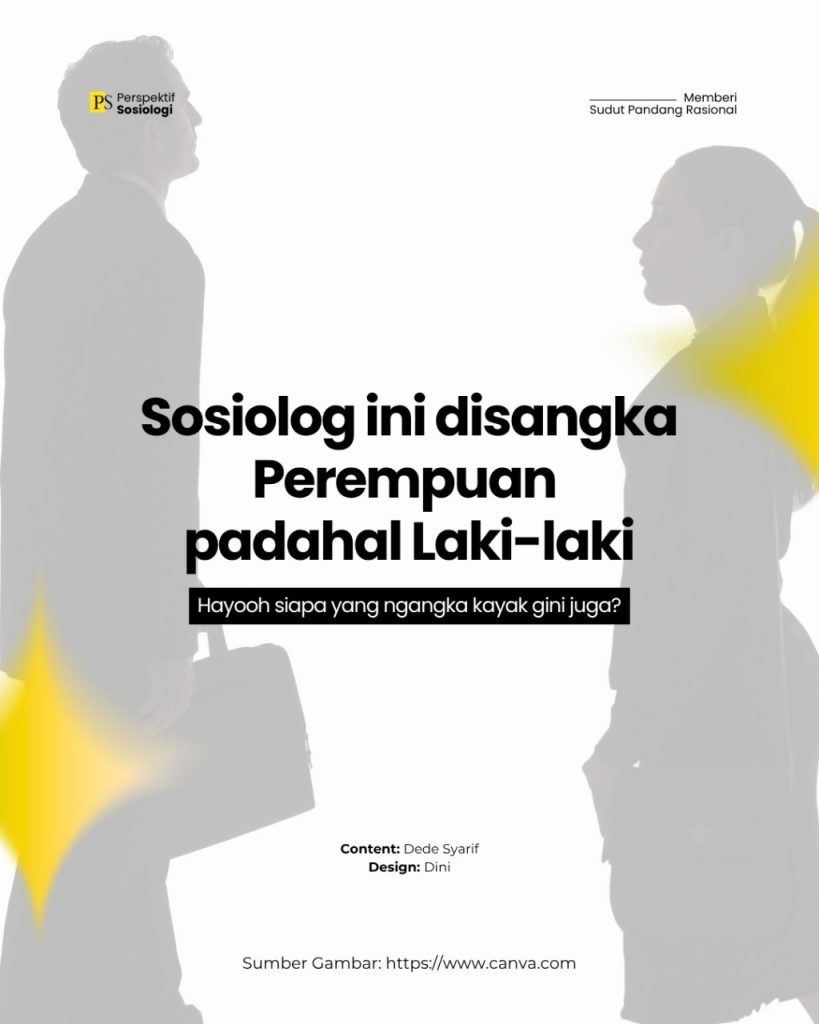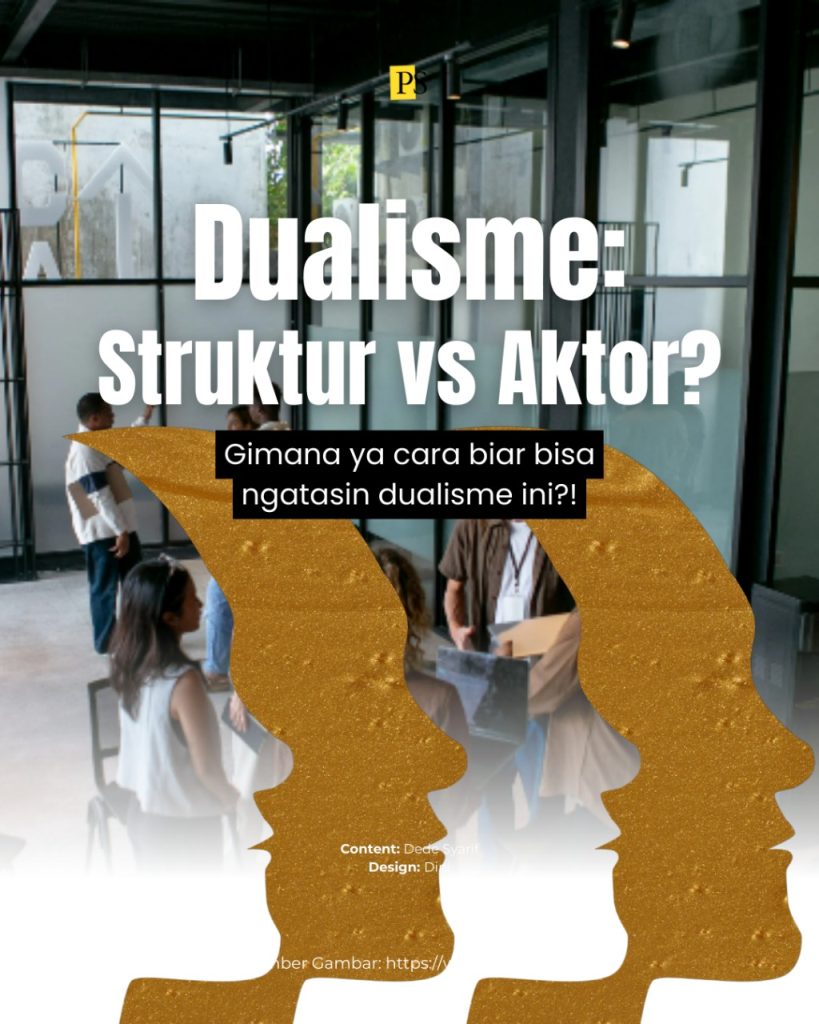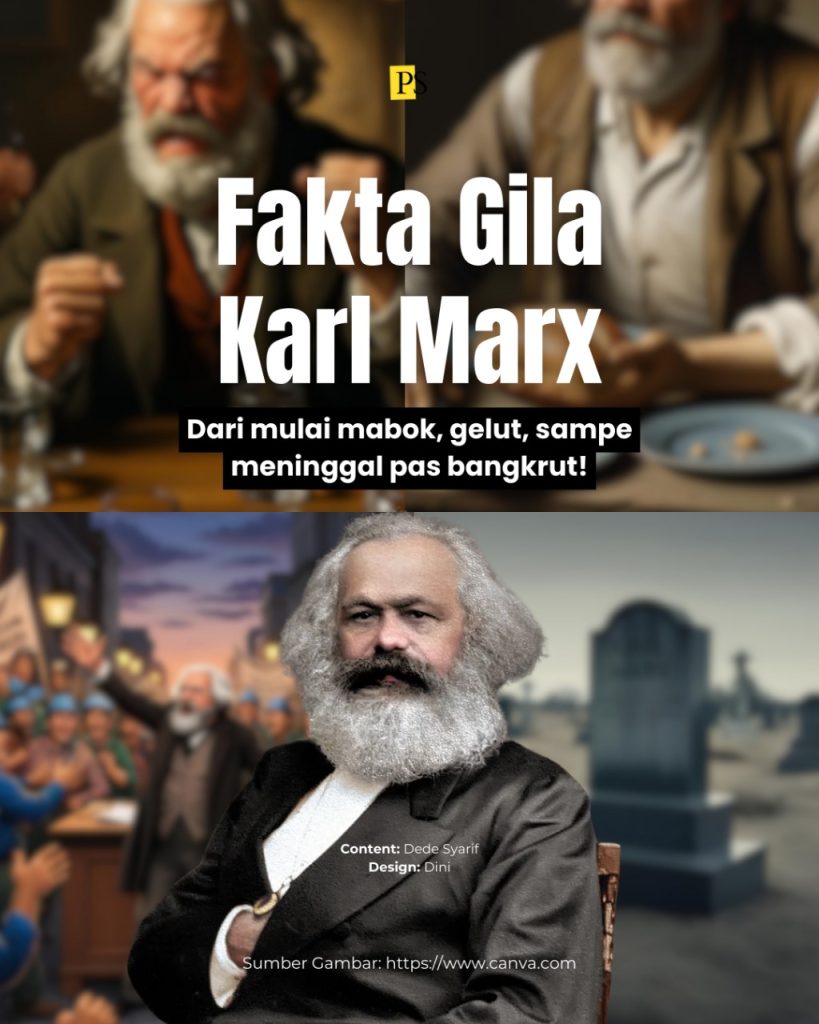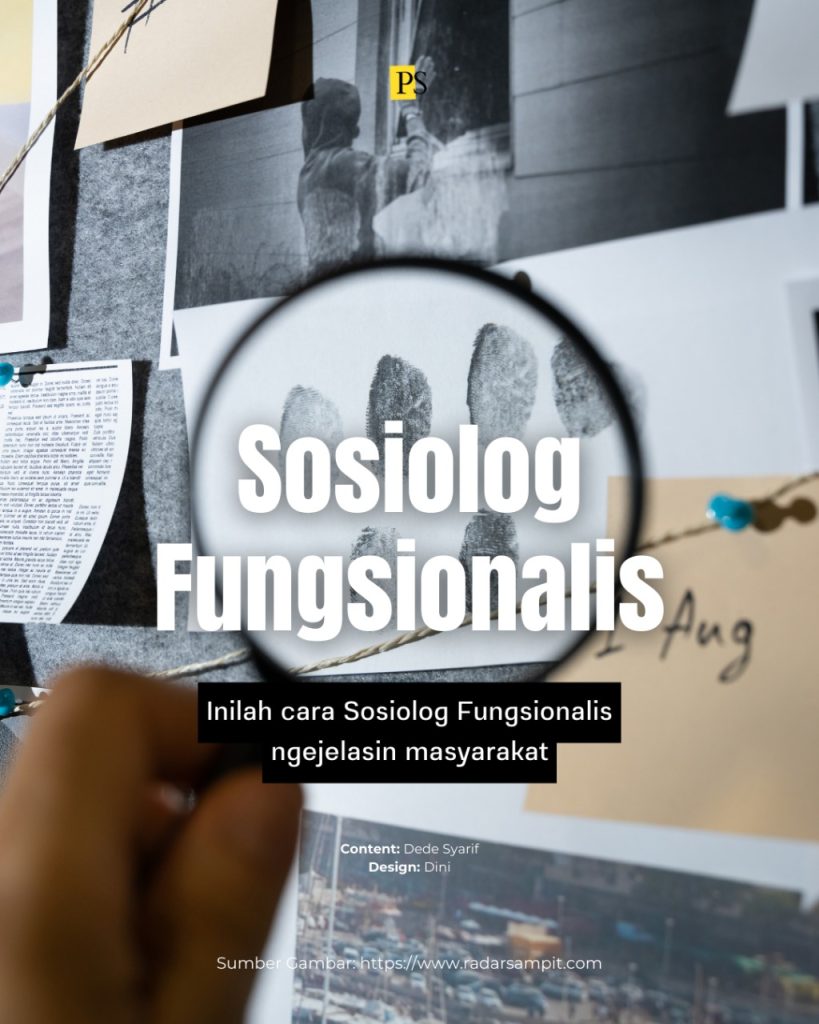Memahami Dunia Postmodern: Suara Para Pemikir Besar
Mengenal Tokoh Memahami Dunia Postmodern: Suara Para Pemikir Besar Kehidupan modern yang kita jalani kini telah banyak berubah. Kompleksitas dunia saat ini tidak lagi sepenuhnya bisa dijelaskan dengan teori sosiologi klasik atau modern. Karena itu, muncul kebutuhan akan kerangka berpikir baru—teori postmodern—untuk memahami perubahan yang begitu cepat dalam masyarakat, budaya, dan pengetahuan. Lalu, apa kata para pemikir besar tentang dunia postmodern ini? Berikut pandangan tokoh-tokoh kunci yang membentuk fondasi pemikiran postmodern. Jean-François Lyotard: Akhir dari Meta-Narasi Lyotard menegaskan bahwa di era postmodern, tidak ada lagi meta-narasi—cerita besar yang mampu menjelaskan segala hal tentang dunia. Narasi tunggal seperti “kemajuan” atau “rasionalitas” yang dulu diyakini mampu memberi jawaban universal, kini dipandang tidak memadai. Sebaliknya, Lyotard menekankan pentingnya menghargai keragaman cerita kecil (petit narratives) yang muncul dari pengalaman individu maupun komunitas. Jean Baudrillard: Dunia Hiperrealitas Baudrillard berpendapat bahwa realitas di masyarakat postmodern telah berubah secara radikal. Kita tidak hanya hidup dalam kenyataan yang nyata, tetapi juga dalam hiperrealitas—realitas yang dibentuk oleh simulasi, tanda, dan media. Televisi, iklan, dan internet menciptakan dunia buatan yang sering kali lebih berpengaruh dibanding kenyataan itu sendiri. Dengan demikian, batas antara realitas dan ilusi semakin kabur. Jacques Derrida: Dekonstruksi Oposisi Biner Derrida menolak pandangan bahwa kenyataan bisa dipahami hanya melalui oposisi biner seperti benar–salah, baik–buruk, atau rasional–irasional. Menurutnya, dikotomi semacam ini adalah hasil konstruksi kekuasaan yang tersembunyi. Karena itu, ia menawarkan metode dekonstruksi: membongkar teks, bahasa, dan makna untuk mengungkap kompleksitas dan keragaman yang selama ini ditutupi oleh narasi dominan. Michel Foucault: Pengetahuan dan Kekuasaan Foucault menyoroti hubungan erat antara pengetahuan dan kekuasaan. Ia berpendapat bahwa pengetahuan tidak pernah netral, melainkan selalu diproduksi dalam kerangka relasi kekuasaan. Dengan kata lain, apa yang dianggap “benar” dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh siapa yang berkuasa dan bagaimana mereka mendefinisikan kebenaran itu. Penutup Para pemikir postmodern ini membantu kita melihat bahwa dunia saat ini penuh dengan keragaman, simulasi, dan relasi kekuasaan yang tersembunyi. Mereka mengingatkan bahwa tidak ada satu teori tunggal yang bisa menjelaskan segalanya. Sebaliknya, pemahaman tentang masyarakat postmodern harus dibangun dari keberagaman perspektif, keterbukaan terhadap perbedaan, dan kesadaran kritis atas bagaimana realitas dikonstruksi. Dr. Dede Syarif Dr. Dede Syarif adalah akademisi dan sosiolog UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lulusan Sosiologi UGM. Ia aktif dalam pengembangan ilmu sosiologi, termasuk melalui short course di Jerman dan Australia. Pendiri Perspektif Sosiologi ini kini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi FISIP UIN Bandung. Editor: Paelani Setia Lulusan Sosiologi yang pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa di Unisel, Selangor, Malaysia. Aktif menulis di bidang kajian sosiologi, agama, dan religious studies. Saat ini menjabat sebagai Manajer sekaligus Co-Founder komunitas kajian Perspektif Sosiologi. Address-card Instagram Share artikel ini yuk! Facebook-f Link Twitter Instagram Whatsapp