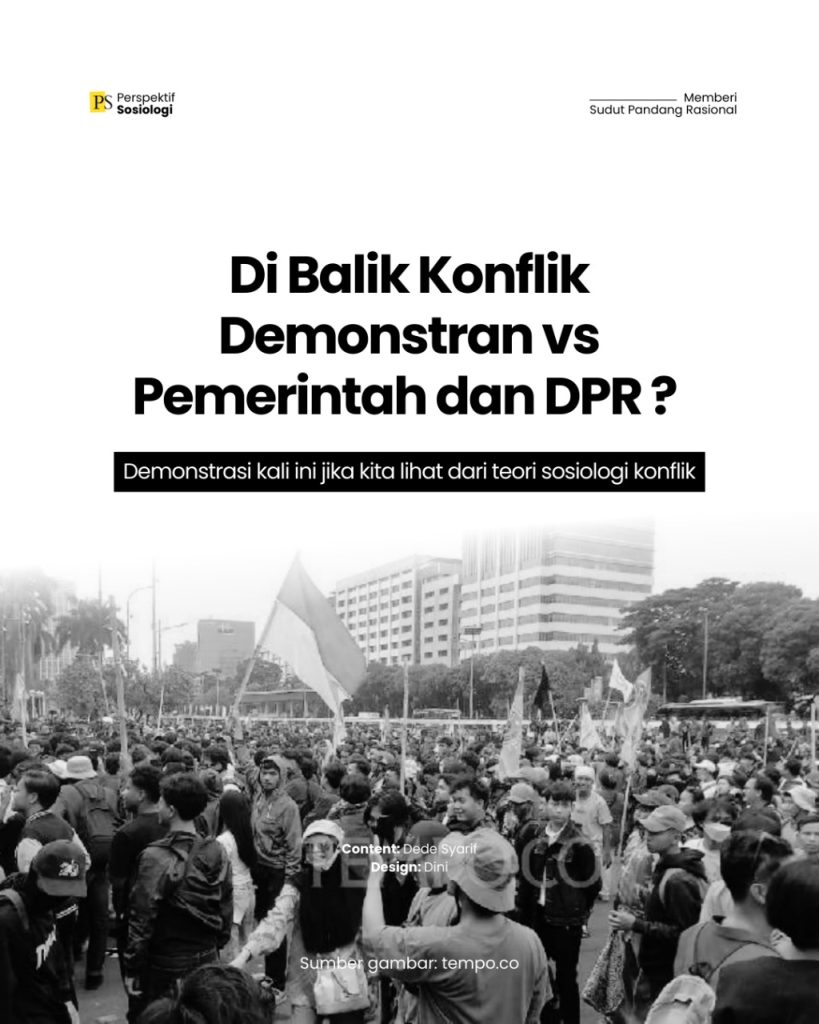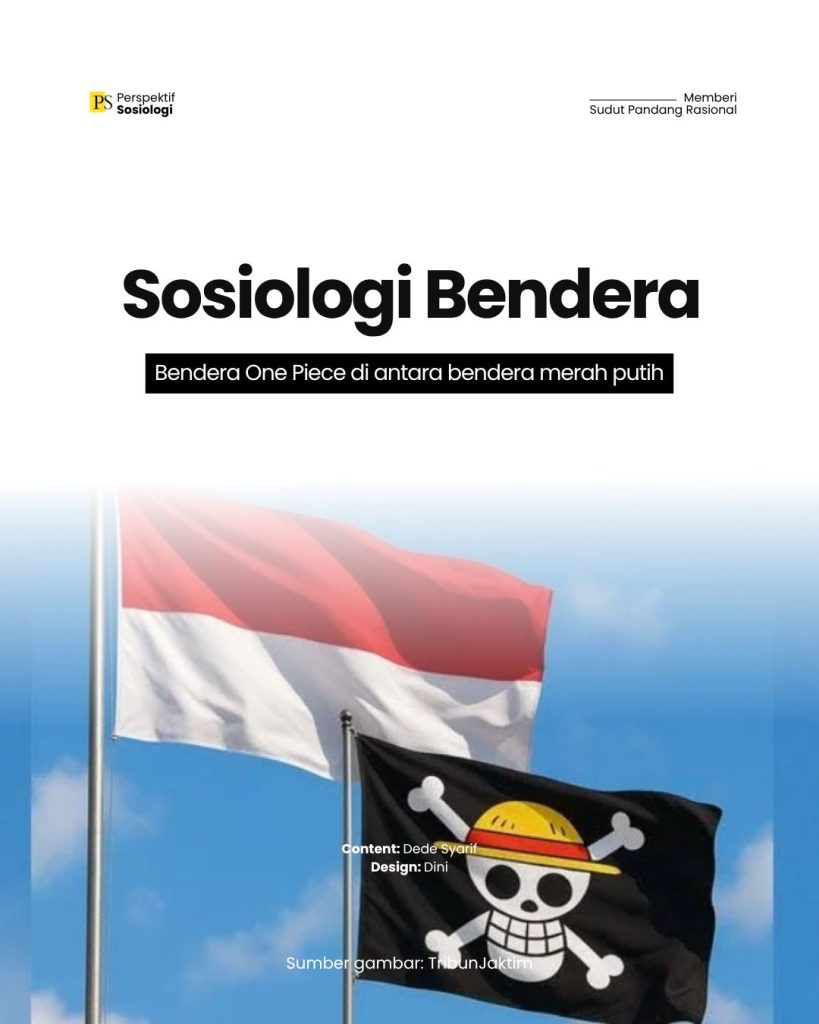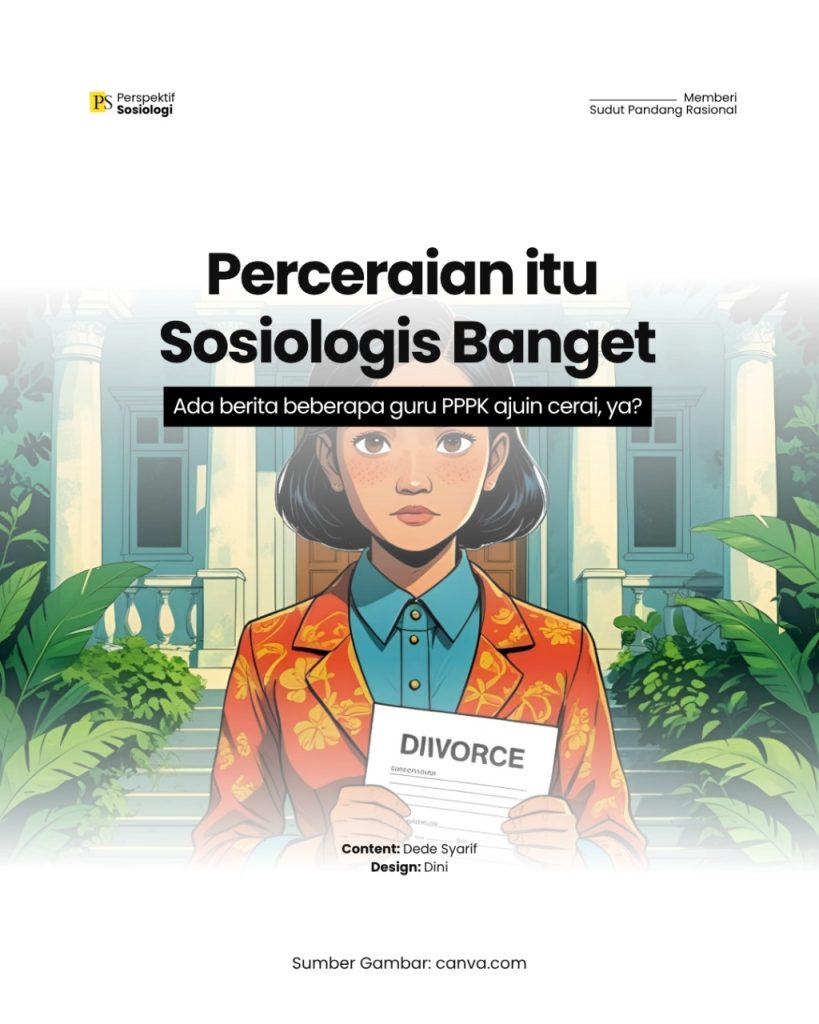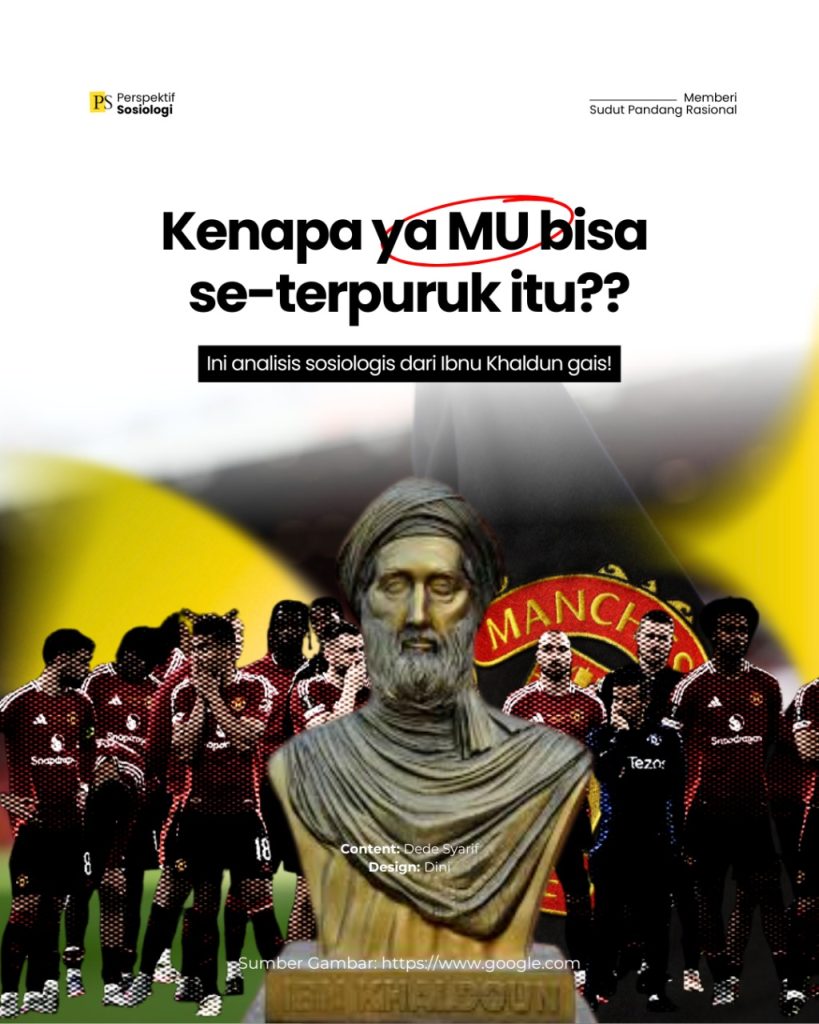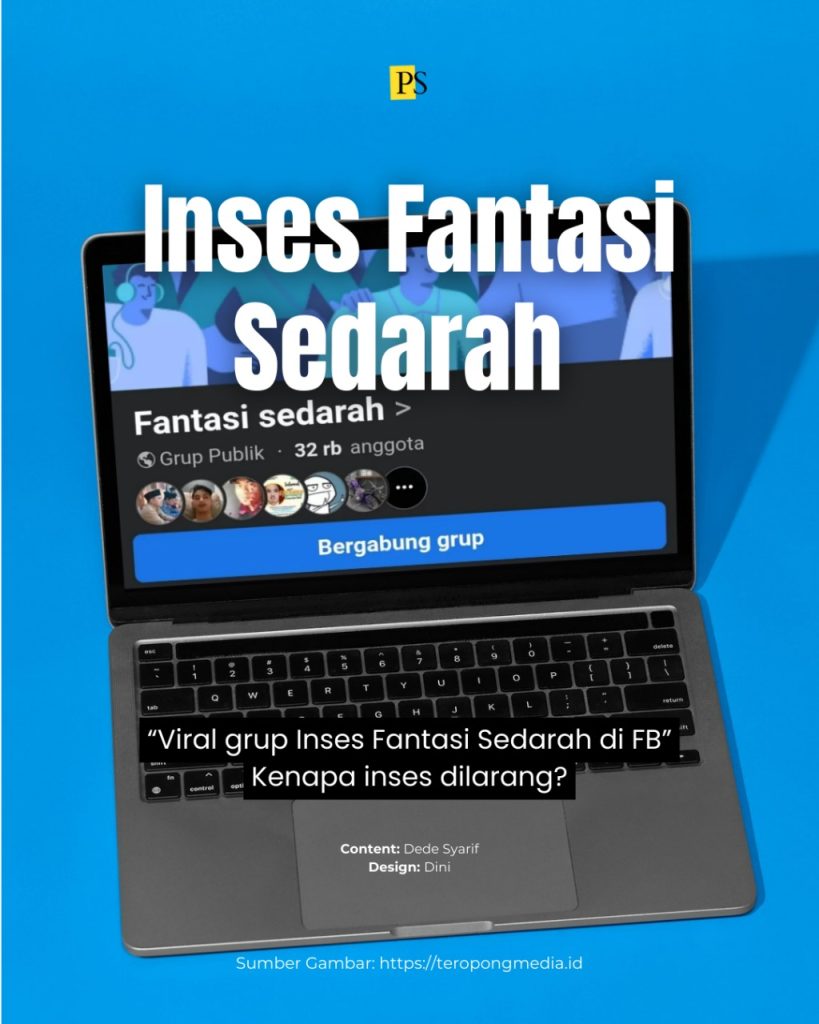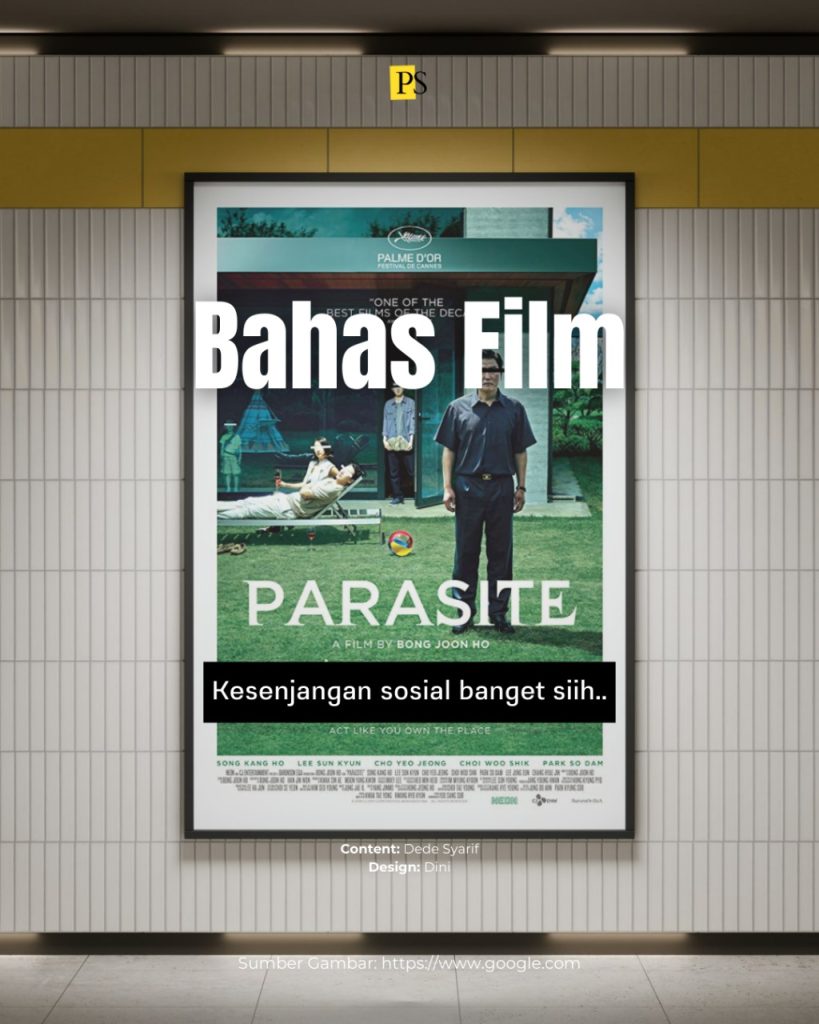Demonstrasi dan Teori Konflik Lewis A. Coser: Membaca Ulang Relasi Pemerintah, DPR, dan Rakyat
Ringkasan Teori Demonstrasi dan Teori Konflik Lewis A. Coser: Membaca Ulang Relasi Pemerintah, DPR, dan Rakyat Demonstrasi besar yang terjadi belakangan ini tidak dapat dipandang hanya sebagai reaksi spontan masyarakat, melainkan sebagai akumulasi ketidakpuasan terhadap kebijakan dan sikap elit politik. Awalnya, aksi massa dipicu oleh keputusan pemerintah menaikkan pajak di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin sulit serta sikap sebagian anggota DPR yang dianggap arogan. Namun, seiring berjalannya waktu, demonstrasi ini berkembang melampaui isu ekonomi. Ia menjadi momentum bagi publik untuk mengekspresikan berbagai bentuk kekecewaan dan tuntutan yang sebelumnya terpendam, menjadikannya ruang artikulasi sosial-politik yang lebih luas. Dua Bentuk Konflik dalam Perspektif Coser Untuk memahami dinamika demonstrasi ini, teori konflik Lewis A. Coser menjadi pisau analisis yang relevan. Coser membedakan konflik ke dalam dua kategori utama, yakni konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis muncul karena adanya pertentangan kepentingan yang bersifat material, sedangkan konflik non-realistis lebih terkait dengan ekspresi perlawanan dan perbedaan ideologis. Membaca demonstrasi melalui dua lensa ini membantu kita memahami bahwa aksi massa tidak hanya berbicara tentang persoalan kesejahteraan, tetapi juga menyangkut nilai, prinsip, dan legitimasi politik. Konflik Realistis: Ketimpangan Material sebagai Pemicu Konflik realistis dalam demonstrasi ini dapat ditelusuri pada kesenjangan material yang nyata. Buruh dan pekerja menuntut keadilan ekonomi ketika mereka menyaksikan ketimpangan yang mencolok antara upah yang mereka terima dengan tunjangan anggota DPR yang mencapai ratusan juta rupiah. Di tengah kesulitan ekonomi yang semakin menekan masyarakat, kesenjangan ini dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang melukai rasa keadilan publik. Bagi kelompok ini, demonstrasi adalah sarana untuk menekan pemerintah dan DPR agar lebih responsif terhadap tuntutan kesejahteraan rakyat. Konflik Non-Realistis: Ekspresi Ideologi dan Perlawanan Di sisi lain, muncul pula konflik non-realistis yang tidak semata-mata berhubungan dengan kebutuhan material. Mahasiswa dan sebagian elemen masyarakat melihat demonstrasi sebagai medium untuk mengekspresikan perbedaan ideologis mereka terhadap cara negara dijalankan. Bagi kelompok ini, persoalan yang dihadapi bukan sekadar tentang gaji atau tunjangan, tetapi tentang prinsip keadilan, demokrasi, dan tata kelola negara. Demonstrasi menjadi panggung perlawanan simbolik terhadap kekuasaan yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai moral dan ideologis yang seharusnya menjadi dasar kehidupan berbangsa. Upaya Meredakan Konflik: Antara Ekonomi dan Ideologi Menyelesaikan konflik realistis relatif lebih sederhana karena dapat ditempuh melalui pemenuhan tuntutan material, misalnya dengan memperbaiki kebijakan kesejahteraan, memperhatikan upah buruh, atau menyesuaikan beban ekonomi rakyat. Namun, konflik non-realistis jauh lebih kompleks. Ia tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan ekonomi, melainkan menuntut reformasi politik yang lebih substansial, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan dialog terbuka dengan publik. Konflik non-realistis hanya dapat diredakan apabila pemerintah dan DPR mampu membangun legitimasi politik yang lebih kuat dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai keadilan sosial. Sumber:Coser, Lewis Alfred (1954). Toward a Sociology of Social Conflict (PhD). Columbia University. ProQuest. Dr. Dede Syarif Dr. Dede Syarif adalah akademisi dan sosiolog UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lulusan Sosiologi UGM. Ia aktif dalam pengembangan ilmu sosiologi, termasuk melalui short course di Jerman dan Australia. Pendiri Perspektif Sosiologi ini kini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi FISIP UIN Bandung. Editor: Paelani Setia Lulusan Sosiologi yang pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa di Unisel, Selangor, Malaysia. Aktif menulis di bidang kajian sosiologi, agama, dan religious studies. Saat ini menjabat sebagai Manajer sekaligus Co-Founder komunitas kajian Perspektif Sosiologi. Address-card Instagram Share artikel ini yuk! Facebook-f Link Twitter Instagram Whatsapp